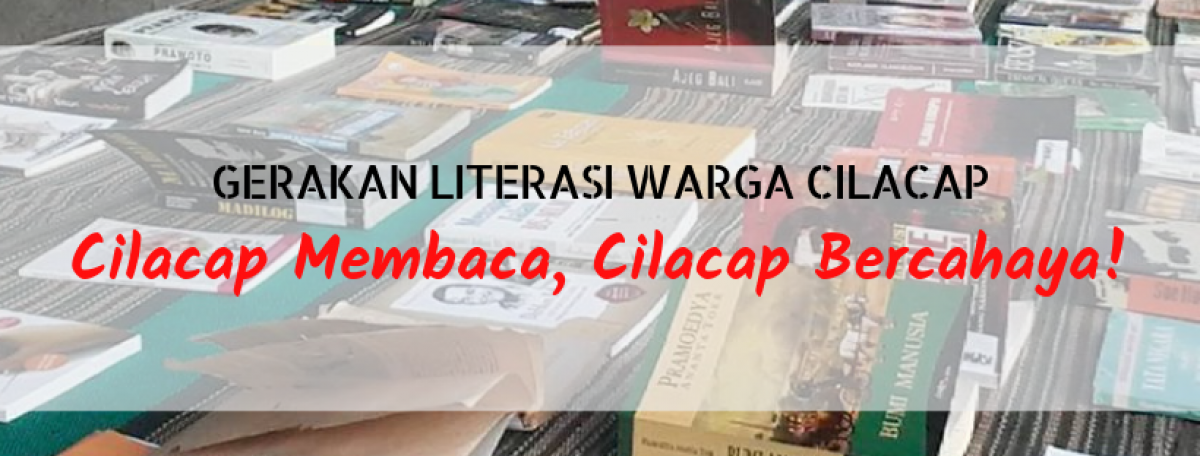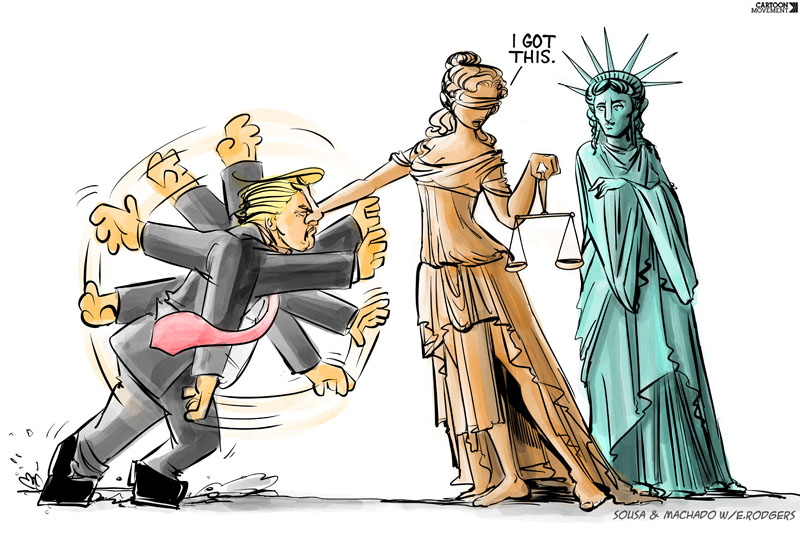___
*)Ditulis oleh Toto Priyono. Esais humaniora. Bermukim di Cilacap.
_
Tidak akan pernah habis untuk dibahas, kemajuan dan tumbal dari kemajuan tersebut sepertinya memang “benar”: akan menjadi nyata dalam realita kehidupan manusia.
Mungkin, berpikir akan sesuatu membuat manusia menjadi tahu sesuatu. Tentu sesuatu yang diperkirakan itu akan terjadi saat ini, maupun di masa depan sebagai pemenuhan jalinan dalam berkehidupan setiap manusia.
Memang tak dapat dipungkiri, semua manusia mendambakan kemajuan. Tetapi perkara menjalani kehidupan maju tersebut, apakah tidak memundurkan kaum-kaum yang tidak dapat maju dengan adanya konsep kemajuan itu; jika pada akhirnya hanya manusia-manusia tertentu saja yang dapat untung di sana?
Ini tidak hanya menjadi pertanyaan tetapi juga menjadi suatu kekhawatiran sosial yang mungkin tidak disadari banyak orang. Kehidupan bermuara pada modernitas, pembangunan, dan harapan-harapan kemudahan zaman; yang memang akan menjadi sesuatu yang harus dikejar sebagai impian banyak manusia saat ini maupun yang kini tengah berpikir jauh sebagai lompatan ke depan.
Namun kuatnya sistem kapitalisme dalam mempengaruhi kehidupan manusia sungguh sudah melampaui. Bukan tidak setuju dengan sistem ini, tetapi jika modal hanya ditujukan pada perolehan keuntungan semata, pada akhirnya, siapa yang akan memperhatikan nasib mereka—dalam hal ini “manusia” yang terpinggirkan dari wacana bermodal itu sendiri?
Sesuatu yang hanya akan menciptakan teka-teki, namun dalam hal kajian terhadap sesuatu, teka-teki itu selalu saja dapat untuk dipecahkan. Lebih jauh lagi, tujuannya bukan hanya untuk terpecah, tetapi harus memberi solusi kongkrit pada setiap obyek masalah; yang harus dihadapi bersama yakni sebagai sebuah jalan untuk menang secara bersama-sama dalam balutan bentuk ideal kemanusiaan.
Dalam menjalankan sebuah sistem sendiri, apapun bentuknya, memang dibutuhkan kerelaan pada obyek kemanusiaan yang harus menjadi tujuan. Tetapi sekali lagi, kemajuan dalam sistem apapun itu, jika tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ideologi yang humanis akan menjadi kenyataan kosong bagi kehidupan manusia.
Kembali pada sub pokok bicara “kemanusiaan” di abad ke-21 ini, apakah akan sesuai jika di dalam ranah keilmuannya sendiri, ilmu humaniora dipandang sebagai keilmuan yang menciptakan penganggur bagi negeri sekelas dan sebesar Indonesia? Mungkin menjadi apa yang dinamakan kemajuan industri dan teknologi, semua bentuk keilmuan harus pro kepada teknologi dan menciptakan banyak sumber daya manusia untuk kebutuhan industri itu sendiri?
Tetapi di dalam menjalaninya, kini sebagai masyarakat yang tentu lebih kompleks dari industri dan teknologi, mungkinkah tidak akan menjadi ketimpangan sendiri di dalam bermasyarakat tanpa ilmu humaniora di dalamnya? Bukankah dengan didukung teknologi maupun industri dan ilmu humaniora yang maju, akan menciptakan suatu terobosan-terobosan baru berkehidupan sosial secara seimbang? Negara sekelas Jerman sendiri saja tetap gigih membangun ilmu humaniora meskipun industri dan teknologi mereka juga sangat maju dan terkenal di dunia.
Bentuk ruang-ruang yang tidak tergarap oleh sisi kemanusiaan, bahkan akan menjadi ruang yang gelap untuk dilucuti keberadaannya, justru bukankah menjadi kecurigaan sendiri? Jangan-jangan, ilmu humaniora dikerdilkan di Indonesia untuk memperluas industrialisasi itu sendiri; yang diperuntukkan perolehan modal dari sistem kapitalisasi supaya mereka semakin kuat pengaruhnya di Indonesia dengan sistem ekonominya?
Berbagai kemungkinan-kemungkinan itu memang bisa saja akan terjadi. Jika ditelisik lebih dalam pun, manusia memang sudah tidak dapat lepas dari kapital. Semua digiring untuk butuh untuk kerja mencari uang sebanyak-banyaknnya dan belanja sepuasnya; meskipun sistem mengakomodasi mereka untuk tetap berhutang yang menjadi tali dengan permodalan.
Dalam setiap bentuk buaian akan sistem kapitalisme sendiri, memang semua tidak dengan lebih mudah untuk sama-sama mengingkari. Tentu karena semua manusia di dunia sudah diikat kuat dalam genggaman mereka—para manusia-manusia yang menang dalam sistem kapitalisme ini.
Seperti para pegawai rendahan sekelas gaji upah minimum kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal rendah saja, cita-citanya kini membeli smartphone seharga belasan juta. Apakah jika sudah seperti itu, dalam ideologinya sendiri mereka sudah diracuni oleh sistem; di mana mereka—manusia—mencari uang semata untuk bereksistensi dengan kemewahan yang ditawarkan juga oleh uang pada akhirnya?
Bukankah akan menjadi pertanyaan sendiri, ketika manusia semakin kuatnya dengan harapan perolehan uang dalam waktu kehidupannya, hal-hal yang penting seperti properti dalam bentuk agraria misalnya; yang masih banyak manusia desa akan semakin mudah dilepaskan untuk kepentingan pembangunan yang justru tidak menguntungkan mereka di masa depan: apakah penting punya uang banyak?
Tentang wacana yang akan menjadi kabur pada akhirnya; pembelian properti masyarakat, pembangunan atasnama modal untuk modal, dan semakin lemahnya daya pikir manusia; yang terus akan terbuai dengan kemewahan yang justru membelenggu mereka sendiri. Pada akhirnya, tetap kapitalis-kapitalis juga yang akan diuntungkan pada akhirnya.
Dan menjadi masyarakat di abad ke-21 ini, akan menciptakan kelas yang menang dan kalah pada akhirnya. Namun dalam praktiknya sendiri, sistem kapitalisme bukan tanpa kelebihan. Tentu di sini adalah hak milik tersebut sebagai bagian dari aset masyarakat itu sendiri. Mempertahankan aset itu—contohnya “agraria”—adalah upaya untuk menang di dalam masyarakat kapitalis.
Karena dalam sistem kapitalisme, pemenang adalah pemilik; dan itu mengapa kepemilikan agraria haruslah diperhatikan; supaya tidak terlalu jauh untuk sebuah pembangunan yang tetap akan memenangkan mereka: para pemodal dengan jumlah besar.
Pembangunan, Kemiskinan, dan Ancaman Kepemilikan Lahan
Ibarat bemain dengan logika sendiri, memang terlihat dalam kehidupan “maju” bukanlah sesuatu yang mengecewakan. Manusia memang ingin kehidupan maju dan membanggakan sebagai jawaban dari segala bentuk harapannya. Namun menjadi “maju” dalam bentuk pembangunan yang tidak disadari itu, kita harus bertanya: akan ada berapa manusia yang dimiskinkan oleh pembangunan itu?
Pertanyaan yang tidak dapat dilepas ini, dalam bayangan sendiri, pembangunan memang diperuntukkan untuk umum. Tetapi dalam menjadi umum, apakah tidak rancu ketika untuk menjadi penikmat fasilitas umum sendiri harus menyesuaikan kelas sosial antara kelas mampu dan tidak mampu dalam jumlah kapital?
Bagaimana pembangunan dalam kapitalisme, semua diorentasikan pada modal dan kembali lagi teruntuk modal. Siapakah yang tetap berjaya dalam hal ini; yakni tetap para pemodal!
Modal dan lajunya kehidupan abad 21 ini memang ibarat sebuah pertalian yang disepakati bersama. Sebagai tawaran-tawaran dari bermodal itu sendiri, apakah benar yang penting hari ini punya uang bukan punya sumber-sumber aset produksi untuk menunjang kehidupan itu sendiri? Inilah yang terkadang dikaburkan oleh keinginan menjadi bermodal itu sendiri.
Kebutuhan menjadi mewah, tidak berorentasi masa depan, dan kemudahan segala bentuk apapun asal punya modal “uang”; semua dapat terbeli termasuk yang “dikesankan oleh hidup dalam kesenangan dan kebahagiaan dari perolehan kapital mereka sendiri”.
Ideologi berpikir dengan kapitalis memang tengah menjadi wabah baru manusia abad ke-21. Sebagain besar dari mereka tidak menganggap penting aset yang produktif seperti agraria itu sendiri.
Sampai kapanpun, manusia tetap akan kembali pada alam untuk menanam apa yang mereka akan tanam sebagai bahan makanan. Jika pun nanti di masa depan akan ada makanan buatan yang lebih efisien, apakah sesuatu yang dibuat itu tidak akan membutuhkan alam pada akhirnya?
Alam sebagai ibu dan lahan untuk menanam manusia adalah bentuk kasih dari seorang ibu untuk kehidupan manusia. Dan apakah manusia akan peka terhadap kasih ibu “agraria” jika dibandingkan dengan kebutuhan pertalian mereka akan uang dan kemewahan—bukan dalam bentuk produktivitas pangan yang lebih dibutuhkan?
Pertanyaan tetap pertanyaan tetapi kenyataan merupakan bukti itu. Lahan-lahan di Pulau Jawa semakin tergerus industri dan pembangunan yang justru mengerdilkan produktivitas pangan Tanah Jawa itu sendiri sebagai simbol kemakmuran.
Pembangunan lahan industri pabrik, jalan tol, perumahan, dan sebagainya yang mengurangi secara membabi buta lahan di Tanah Jawa, bukan saja akan menimbulkan masalah sosial baru di masa yang akan datang. Tapi juga, ancaman-ancaman kemiskinan yang terus akan dirasakan manusia Jawa pada saatnya. Mungkin jika tanah Jawa dijadikan industri yang besar untuk Indonesia, secara garis besar apakah tidak akan tetap dimiskinkan jika sebagian besar masyarakat adalah buruh dengan keterbatasan upah, lalu di sana harga kebutuhan pokok seperti pangan harus tinggi harganya karena produksi pangan semakin sedikit?
Yang mungkin sudah terjadi tetapi tidak disadari, populasi penduduk Jawa yang semakin meningkat jumlahnya sendiri, bukan saja akan menjadi fokus baru di balik terus dibangunnya pembangunan dan tetap pembangunan.
Perumahan dan pabrik-pabrik industri mungkin sebagian dari itu, tetapi pembangunan jalan tol yang akan terus dibangun melingkari Tanah Jawa. Jika di bagian Jawa utara sudah dibangun jalan tol, kini giliran Jawa bagian selatan yang akan menerimanya. Mungkinkah bencana atau anugerah dari pembanguan itu?
Tentu perkaranya hanyalah berubahnya tranformasi lahan—yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat dan masih dinikmati hasilnya dari lahan tersebut sebagai lahan pangan—berganti aspal-aspal entah milik siapa. Bukankah jika milik negara, apakah semua lapisan masyarakat menikmati apa yang diusahakan negara? Bukankah yang tetap sejahtera adalah mereka-mereka para pegawai negara dengan bentuk sebagai yang katanya mengabdi pada masyarakat itu?
Pembangunan dalam sistem kapitalisme memang bukan saja tidak untuk sebagai sebuah keadilan. Jika bukan pemodal dan negara, hasilnya pun akan tetap dinikmati oleh mereka para kapitalis birokratis yang bersembunyi di balik jubah negara.
Mungkin jika harus dirasakan dampaknya lebih dalam, setiap apa yang disebut pembangunan, memang akan mengancam semua bentuk kepemilikan lahan. Terkadang tawaran yang menggiurkan dari uang hasil dari penjualan lahan itu menjadi sesuatu yang rancu. Dapatkan manusia akan mempertahankan lahan tanahnya jika apa yang menjadi ide-ide mereka sederhana; yakni menjadi hedonis dengan uang yang akan mereka peroleh?
Bukankah menjadi bukti itu sendiri bagaimana Jalan Tol Trans Jawa di bagian utara Jawa mengurangi poduksi pangan itu karena sawah yang digunakan sebagai pembangunan jalan sudah tidak produktif lagi, bahkan sudah mati?
Dan siapakah yang menerima berkah dari pembangunan itu; apakah mereka para kaum manusia terpinggirankan yang diuntungkan? Tentu yang dapat menikmati adalah mereka-mereka dengan keterpunyaan modal yang tinggi; di mana untuk masuk jalan tol saja harus punya mobil dan uang untuk mempergunakannya.
Masa depan agraria di Pulau Jawa memang sudah akan mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Bukan apa, mungkin dampak dari hari ini tidak akan terasa. Mereka yang menjual lahan-lahan mereka untuk pembangunan masih dapat menikmatinya untuk dirinya sendiri. Tetapi, bagaimana dengan keturunan mereka kelak?
Inilah sumber dari berbagai masalah itu. Di belahan bumi sana, berperang mempertahankan lahan, manusia usahakan mati-matian namun tawaran akan uang dan kemewahan hidup sesaat justru mengaburkan nilai-nilai perjuangan akan lahan itu sendiri.
Bahwasanya jelas di sini. Lahan, selama ia masih diolah oleh manusia, di sana akan terdapat kehidupan berapapun lintas generasinya. Untuk itu, mempertahankan lahan adalah mempertahankan akan abadinya kemakmuran bagi manusia.
Bukankah menjadi dasar dari berpikir itu sendiri—untuk manusia khususnya—yang mempunyai lahan agar tidak sebegitu mudahnya menjual lahannya; yang akhirnya di masa keturunannya, mereka tidak sejahtera karena tidak mempunyai lahan bagi kebutuhan pangan-pangan mereka?
Saat ini, sebab dari berbagai musabab itu, Tanah Jawa yang terkenal dengan kesuburannya bukan tidak mungkin di masa depan akan menjadi miskin karena alih fungsi lahan itu sendiri. Nahasnya bukan masyarakatnya yang menikmati, tetapi segelintir orang dalam sistem kapitalisme yang justru menikmati itu.
Kesadaran akan agraria untuk masa depan lebih baik bukan saja harus ditanamkan dengan berbagai tawaran ide-ide hedonisme sementara yang lebih menggiurkan; namun berpikir orentasi masa depan. Bukankah kemewahan hidup tidak akan terbawa mati dan manusia mati jika ia punya anak akan meninggalkan anaknnya? Akan diwarisi apa anak tersebut? Kemiskinan tidak punya lahan pangan?
Sesuatu yang belum terjadi dan akan direncanakan untuk terjadi adalah pembangunan Jalan Tol Trans Jawa segmen selatan Pulau Jawa. Bukan hanya akan menjadi ancaman nyata lagi bagi agraria Tanah Jawa kembali, namun akan menjadi momok kemiskinan lagi; yang akan terjadi berikutnya di masa depan masyarakat Jawa.
Pembangunan jalan tol segmen jalur selatan Jawa di satu Kabupaten Cilacap sendiri berpotensi akan kehilangan lahan sawah sekitar 537 hektar—dikutip oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Bukankah dari sini, kita dapat menghitung berapa dalam waktu sekali panen, kita kehilangan hasil dari panen pangan tersebut? Inikah yang akan diwariskan untuk keturunan kita dengan “kemiskinan” karena sudah tidak punya lahan lagi?
Menjadi masyarakat yang punya hak secara pribadi akan kepemilikan lahan, bukankah itu sebuah kekuatan masyarakat untuk menentang pembangunan yang justru memiskinkan?
Perkaranya, kini “kemewahan” yang banyak masyarakat pamerkan. Manusia akan selalu butuh uang untuk gaya hidup mereka dan apa yang mungkin dapat mereka jual sebagai akomodasi kemewahan adalah menjual lahan; yang juga merupakan solusi bagi masyarakat yang selalu kekurangan gaya dan melupakan pentingnya masa depan untuk anak-cucu mereka sendiri.