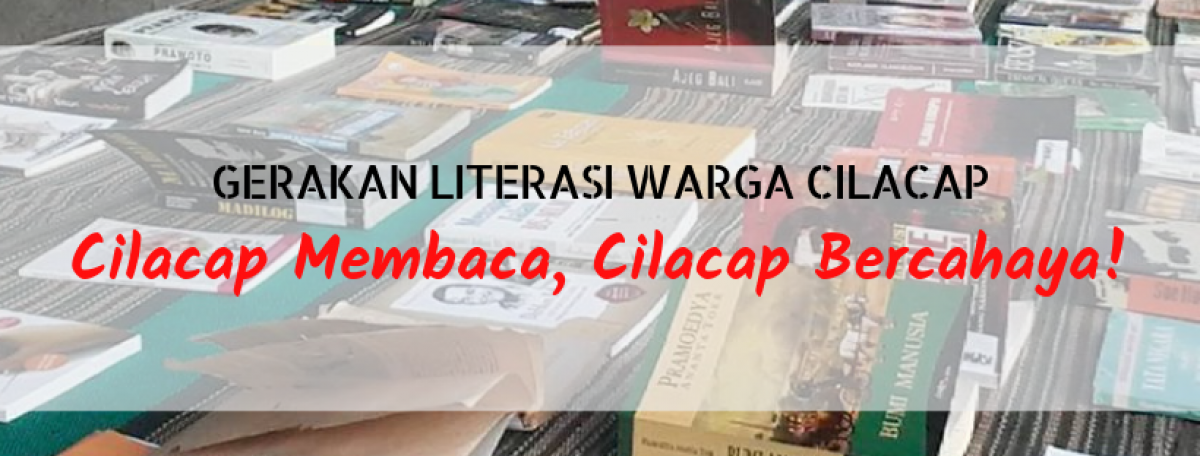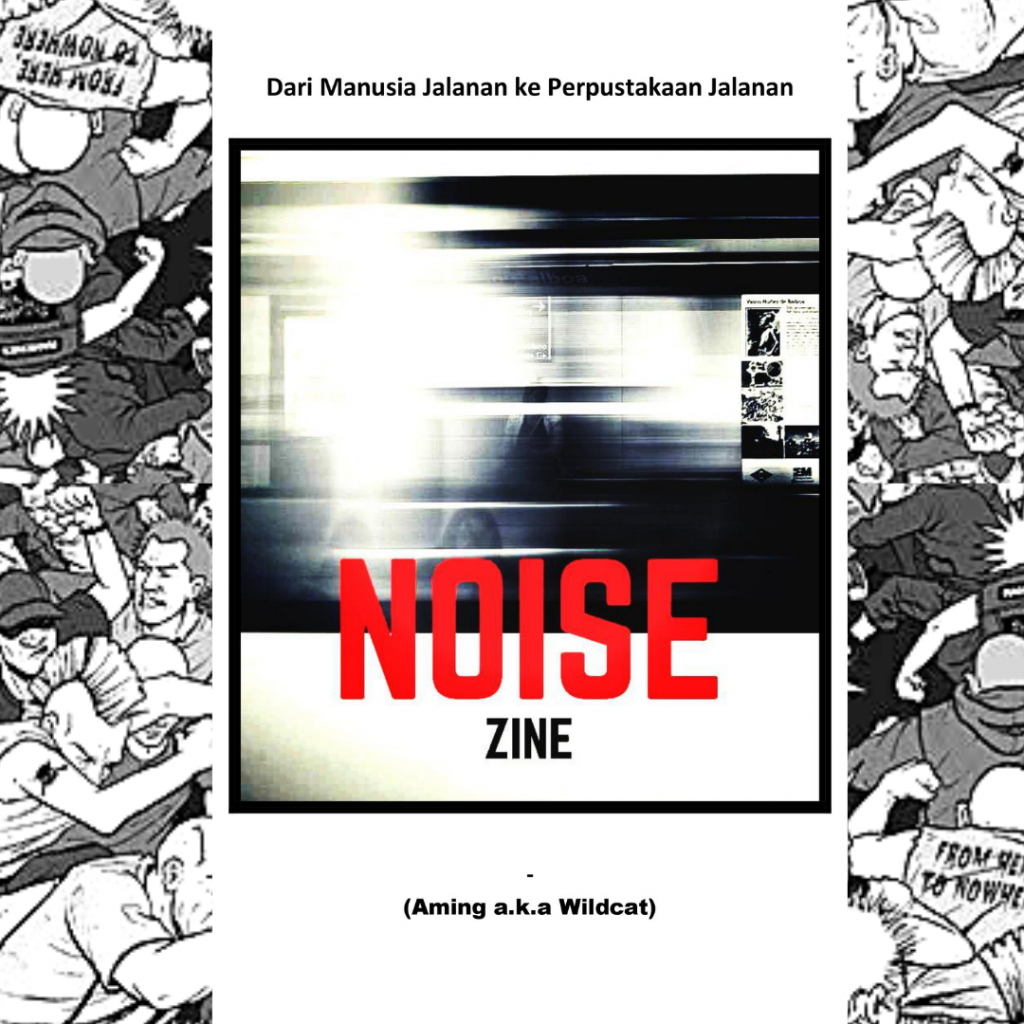Agustus 2020, kami tengah nongkrong di beranda rumah hingga larut pada suatu malam. Pembicaraan berputar pada apa saja; terutama hal-hal seputar budaya pop macam musik-musik yang kami suka, serta tak luput ngomongin urusan politik lokal. Tentunya, kegagapan dan kelatahan orang-orang sekitar kami menghadapi Covid-19 pun tak luput dari bahasan.
Sebagai orang-orang berumur kepala dua yang menghabiskan masa anak-anak hingga remaja di Cilacap, tuturan kami tak lepas dari memori masa lalu di kota pesisir selatan Jawa ini. Apa yang kami tonton, sukai, dan kagumi akan mengalir begitu saja pada teras pembicaraan. Salah satunya adalah topik mengenai ebeg; atau pertunjukan seni tari tradisional tatar Banyumasan yang acap dikenal sebagai kuda lumping.
Malam itu, awal mulanya, seorang teman menyebut nama seorang tokoh ebeg yang kami tahu. Tokoh itu sangat populer pada memori masa anak-anak kami karena ia gemar memainkan tarian atraktif saat pentas digelar.
Kami yang berbeda asal tempat tinggal dan sekolah ini ternyata sama-sama mengenali tokoh tersebut. Artinya, pada masa lalu, ebeg memang terbilang masif merasuki alam penghiburan orang-orang Cilacap. Buktinya, anak-anak kecil di masa lalu macam kami ini pernah mengagumi dan mengingatnya hingga kini. Bekas yang masih menapak di kenangan tentunya bukan kebohongan bahwa seni tradisi macam ebeg adalah pemikat yang strategis—bisa diterka dari perpaduan stigma mistik dan kecanggihan berestetika massalnya.
Gagasan pun mencuat; mengapa kami tidak menarasikan ebeg dalam bentuk zine? Setidaknya, jika suatu zine ini bisa terbit, ada artefak rekam memori yang bisa dipelajari atau dijadikan penyelia kearifan di masing-masing benak pergaulan orang-orang lokal. Tak muluk-muluk memang, karena kami bukan kumpulan sosiolog, antropolog, peneliti sosio-humaniora, atau budayawan yang tengah melangit-langitkan laku masyarakat yang seringkali amat sederhana. Dengan begitu, kami pun sepakat.
***
Sepekan kemudian, dua dari kami berangkat. Bukan untuk menemui satu sosok tokoh yang kami kenal atraktif sejak kecil pada skena ebeg Cilacap—yang kami bicarakan sebelumnya. Keputusan kami mengarah pada Poni Haryono untuk kami hampiri.
Ia juga sosok yang kami kenal via tontonan ebeg pada masa kecil. Kami mengenalnya sebagai pembawa kelucuan di lapangan. Kini, ia dianggap “mapan” secara berkesenian oleh banyak penggemar ebeg kawasan Cilacap. Bersama Turangga Edan, kelompok seni ebeg yang dirawatnya, ia malang-melintang melintasi jagat pementasan. Kelompoknya pun dikenal sebagai kubu mahir pembawa banyolan di tengah-tengah riuh serta ketegangan mistik ala ebeg.
Satu hal yang tak kami bayangkan kala duduk bersama di beranda rumah sekaligus markas sanggar ebegnya; bahwa hal-hal seputar mistik tak harus terasa pekat saat membicarakan ebeg. Stigma yang selama ini melekat pada ebeg mengenai penggunaan roh untuk prosesi menari cenderung ditepis oleh Poni dengan lagi-lagi membawa prinsip estetika—sebagai alasan kenapa orang-orang pandai menari dan penontonnya tetap memiliki tresna pada pagelaran ebeg.
Bagi Poni, ebeg tak bisa lepas dari klenik, namun ada banyak hal penting lainnya yang selama ini membersamai ebeg agar tetap hidup di pusaran kesenian dan hiburan masyarakat. Tentunya, ia menawarkan beragam taktik untuk menghidupi “roh” itu. Nah, itulah yang perlu diketahui.
Dengan maksud mengurai kekonyolan stigma sekaligus merekam memori seni, simak saja aliran tutur kami bersama Poni pada memo-memo di bawah ini.
Gimana awalnya suka ngebeg?
Awal mulanya, saya memang senang seni tari. Kelihatannya tari-tari Jawa itu unik. Kenapa? Karena bisa dipadukan dengan suara gendang; karena setiap gendang dipukul menghasilkan bunyi yang berbeda–beda. Nah, di situlah kenapa saya tertarik seni tari. Juga, karena melihat teman-teman yang sudah dulu terjun di seni tari.
Aku mikir “yang lain bisa, kenapa aku nggak”. Akhirnya saya ikut rombongan 5-6 orang sampai saya berhasil. Tidak berhenti di situ, saya pun belajar ke pendahulu-pendahulu saya (sowan); supaya saya memiliki keberanian memiliki rombongan sendiri. Intinya, saya hanya saling percaya satu sama lainnya. Semisal, kamu percaya sama saya, dan sebaliknya, saya percaya dengan saya; hanya modal nekat sampai memberanikan diri untuk membuka sanggar tari sendiri.
Modal awalnya, saya hutang, nanti mengembalikannya setelah dapat tanggapan (order pertunjukan) ebeg. Allhamdullilah, sampai bisa membuat barongan sendiri ada 13 biji, punya banyak murid mudah diatur, sedikit-sedikit mulai banyak tanggapan—dari situ mulai bisa membuat alat sendiri. Semua itu karena saya belajar dari sistem nitor (tutur-tinular) yang saya dapat dari pendahulu saya.
Cara tutur-tinular adalah cara mengambil ilmu yang baik-baik dari pendahulu saya, dan saya sebarkan pula ilmu yang baik-baik kepada orang lain. Saya pernah dicela, dikatai, dan menerima umpatan kotor; tapi bukan itu yang saya bagikan kepada murid-murid saya, tapi hal-hal baik yang saya sebarkan. Contohnya, kalau pendahulu saya mengasihkan sesuatu yang menurut ia baik, saya ambil—namanya juga nitor. Beda sama orang yang sekolah di seni; pasti sekolahnya mengeluarkan banyak duit; jadi seninya itu hanya sebatas mencari uang—beda dengan saya yang sistemnya nitor dari pendahulu saya. Tapi dari situ menjadi motivasi untuk bagaimana kesenian ebeg di Cilacap semakin banyak.
Saya juga mikir bagaimana caranya nguri-uri (menghidupi) rombongan sendiri. Setelah dirasa mampu menghidupi rombongan, syukur-syukur dapat menghidupi saya dan keluarga saya. Itulah keinginan saya dari kesenian ebeg.
Awalnya ngebeg secara swadaya atau ikut rombongan?
Waktu masih swadaya, saya ikut ngalor-ngidul (sana-sini)—dalam arti, masih ikut rombongan si A dan si B; karena saya masih ingin nitor ilmu. Dari situ jadi tahu, ternyata tariannya si A seperti ini, tarian si B seperti itu; ternyata setiap rombongan karyanya beda-beda.
Kesenian ebeg dekat dengan lagu “Eling-Eling”. Sebenarnya itu lagu khas Cilacap atau kebudayaan Jawa?
Dari kebudayan Jawa, tapi entah dari mana datangnya, kita belum tahu kebenarannya. Ada versi lain menyebutkan bahwa ebeg datangnya dari keraton karena diciptakannya tari ebeg itu awalnya dari tarian keprajuritan.
Zaman dulu, menari masih menggunakan kuda. Sampai ketika menari dengan kuda terasa menyulitkan, akhirnya dibuatlah kuda kepang supaya orang-orang lebih mudah menggunakannya saat menari. Dengan adanya tarian keprajuritan tadi, orang-orang menjadi simpatik. Respon baik itu yang nantinya membuat ebeg meluas sampai daerah Banyumasan.
Dari keraton di daerah wetan (timur) akhirnya menyebar hingga ke kulon (barat), seperti Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Kebumen—dan sebutannya pun sudah menjadi berbeda-beda. Cilacap menyebutnya ebeg, Purbalingga menyebutnya ebleg, Wetan (Jawa bagian timur) menyebutnya jathilan. Semua sebenarnya hanya satu nama, yaitu kuda lumping—hanya penyebutan di setiap daerahnya beda-beda. Jadi awal mulanya ebeg dari mana, tak ada yang bisa membuktikan. Semuanya bilang dari keraton, hanya siapa yang menciptakan dulunya, belum ada yang bisa menemukan.
Lagu “Eling-Eling” mengingatkan supaya kita mengingat kematian tetapi disimbolkan oleh tarian. Maka dari itu, tarian “Eling-Eling” adalah tarian sakral. Ketika tarian mulai, pasti ada lelembut (semacam roh atau jin) itu jelas.
Konon katanya, sinkretisme awalnya diajarkan Sunan Kalijaga. Apakah itu yang menjadi tujuan ebeg sekarang?
Nah, Sunan Kalijaga sebenarnya menyebarkan agama Islam di Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa supaya mudah dimengerti. Saat Sunan Kalijaga bertanya “Apa yang kamu sukai?”, ternyata jawabannya adalah tabuhan (musik). Dari tabuhan itu, dikembangkanlah wayang sehingga tercipta beberapa tembang—seperti eling-eling, macapat, padhangwulan, dan semisalnya. Ketika terdapat tembang-tembang saja dirasa kurang bagus, akhirnya muncullah wayang.
Di samping itu, gamelan sudah ditemukan. Akhirnya orang-orang berpikiran untuk membuat tari keprajuritan, tapi yang jangan jauh-jauh dari tembang “Eling-Eling”. Sampai sekarang, siapa yang menciptakan “Eling-Eling” belum diketahui. Itu adalah bawaan dari orang-orang sebelumnya. Dan, “Eling-Eling” ala Wetan dan Banyumasan berbeda, tapi tujuannya sama; yaitu untuk mengingatkan kematian. Yang jelas, ada kaitannya dengan Sunan Kalijaga karena ia yang menciptakan gamelan.
Untuk masalah kuda lumpingya, ada beberapa versi. Ada yang menyatakan dari Sunan Kalijaga, adapula versi yang menyatakan tidak berkaitan dengan Sunan Kalijaga. Tetapi, Sunan Kalijaga adalah pencetus gamelan. Sedangkan, ebeg hanyalah sebuah tari keprajuritan untuk disajikan kepada tamu keraton.

Mas Poni tertarik tari Jawa dan mempelajarinya kira-kira sejak kapan, Mas?
Saat SD, saya sudah diajak oleh bapak saya, karena bapak dulunya penari ebeg juga. Di Cilacap (kota), dulu hanya ada 5 komunitas ebeg; ada di Jalan Ciberem, Jalan Anggrek, Jalan Kendeng, Jalan Bakung, dan Jalan Bandengan. Dulu ebeg masih sedikit, kualitasnya selalu bagus.
Karena sering diajak oleh bapak, ibu saya tidak suka; saya dimarahi. Kata ibu saya: kamu fokus sekolah saja. Masuk kelas 3 SMP, saya mulai suka, saya mulai ikut rombongan bersama Ucok (artis ebeg Cilacap) untuk pertama kali. Nah, di situ, saya bertahan 2 tahun. Saya selalu bertahan 2 tahun sambil pindah-pindah rombongan. Sampai pada waktunya, saya sempat ikut 7 rombongan. Saya mulai main sendiri (tanpa rombongan) di umur kurang-lebih saya menginjak bangku STM.
Lalu, kapan berani mendirikan rombongan sendiri?
Saya diingatkan oleh orang tua yang dulu saya ikuti. “Jadi, kamu boleh mendirikan ebeg sendiri tetapi ada waktunya setelah umur 30 tahun,” katanya. Kenapa? Dia bilang, “Ketika kamu menjadi ketua di umur masih bocah, nanti kamu hanya dimarahi saja. Tapi jika kamu umurnya lebih dari bocah, semisal kamu umur 30 tahun, sedangkan muridmu umur 18 tahun, jika kamu memarahi bocah pun masih pantas.”
Jadi, awal saya mendirikannya sekitar umur 30 tahunan. Saya sudah mulai berani mentas (mandiri). Sekarang, rombongan saya sudah berumur sekitar 10 tahunan. Ada versi lain juga yang menyatakan boleh jadi ketua asal bisa tanggungjawab, tapi saya sendiri masih mengikuti pakem orang-orang tua yang pernah mengingatkan saya.
Ada yang beda, tidak, antara pakem ebeg Turangga Edan dengan lainnya?
Jelas sama. Kenapa saya namai “Turangga Edan”? Awal mulanya, bernama Tri Jati Turangga Edan. “Tri Jati” adalah konsep kekuatan; dari kekuatan-kekuatan ebeg yang paling bagus di Cilacap, saya jadikan satu; seperti dari kelompok Jati Kusuma, kelompok ebegnya Pak Tumin, lalu saya jadikan satu. Tetapi yang membuat beda dari ebeg lainnya adalah karena punya saya pemain-pemainnya edan. Jogetnya saja konyol/lucu atau tidak pernah serius. Maka saya ganti namanya jadi Turangga Edan. Kami berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat; lain daripada yang lain. Yang lain apanya? Edannya.
“Edan” di sini, adalah edan ke pada ebeg; edan melalui lawakannya. Kami harus beda dari yang lain karena setiap rombongan harus punya ciri khas/karakter sendiri-sendiri. Punya saya ebeg paling gila karena yang lainnya pasti ebeg bisu-bisuan. Pemecah rekor pertama kali ebeg dengan lawakan/guyonan adalah punya saya.
Kenapa harus lawakan? Masyarakat pasti akan fokus tertuju kepada lawakan. Tapi ketika sedang ada lawakan, sementara di sisi lainnya ada yang kesurupan, konsentrasi akan terpecah-belah. Makanya ketika ada lawakan, yang mau mendem (kerasukan) nanti dulu. Biasanya, ada durasi 1 jam hanya untuk lawakan supaya masyarakat fokus kepada lawakan itu, dan mereka dapat memilih segmen/babak. Jadi komplet; ada lenggeran, ada barongan, juga ada lawakan. Kalau ebeg zaman dulu cuma ada tarian mendeman dan penutupnya bisuan. Makanya, saya buat beda.
Sebenarnya, bisu-bisuan juga lawakan. Tapi itu kurang bisa berkomunikasi karena hanya lawakan lewat gerak badan. Beda dengan milik saya yang lawakannya lawak asal nyangkem (asal ngomong).
Adakah yang meniru lawakan Turangga Edan?
Alhamdulillah, banyak. Banyak orang meniru itu wajar. Dulu, saya menari juga meniru, kenapa saya ditiru tidak boleh? Bagi saya, tidak apa-apa sama. Hanya, apakah mereka bisa sama konyolnya seperti kami? Pasti tetap berbeda.
Orang nitor atau ngambil/meniru itu wajar. Ebeg tidak mungkin langsung berdiri, pasti meniru dulu. Cuma, tinggal mengubah karakternya sendiri-sendiri.
Sempat diprotes ebeg-ebeg pendahulu? Kok itu ebeg malah lawakan?
Sempat, sempat diprotes; ebeg kok lawakan, kan harusnya bisu-bisuan? Silahkan berkomentar seperti itu. Saya lawakan karena ingin mempunyai karakter sendiri. Apakah ada larangan? Apakah ada keterangan tertulis harus memakai bisu-bisuan? Tidak mungkin.
Saya berani mengubah pakem, bukan berati saya mengubah pakem dasar ebeg itu sendiri, tapi saya menciptakan pakem baru. Sampai sekarang, pakem saya bisa ditiru oleh rombongan-rombongan lain.
Contohnya, perkembangan seni musik tidak mungkin menggunakan tabuhan seperti itu saja; semisal zaman dulu menggunakan corong, sekarang pakai sound system. Dulu hanya menggunakan toa, sekarang bisa berubah. Makanya, saya mengikuti zaman supaya dilihat masyarakat jauh lebih bagus. Bahkan, saya sendiri sekarang menggunakan organ. Itulah yang namanya seni. Seni itu tidak ada habisnya; tergantung bagaimana caranya kita berkembang.
Orang-orang tua yang memarahi saya, ya, banyak sekali. Ebeg saya tidak menggunakan pakem ebeg pendahulunya. Ebeg saya menggunakan tudung (caping/topi kerja petani), sementara ebeg dulu menggunakan iket (sejenis bandana/kain kepala), ya, tidak apa-apa. Saya hanya ingin menciptakan pakem baru.
Kenapa pakai tudung? Pertama, supaya yang menari tidak kepanasan. Tudungnya juga tidak sembarangan. Tudungya saya cat dengan menggunakan warna yang seragam supaya saat dilihat bagus. Tidak ada larangannya kita memiliki kreasi sendiri.
Kalau sekarang ada yang ingin menciptakan ebeg klasik, ya, tidak apa-apa. Tak apa-apa kalau mereka menyukai yang klasik. Cuma, ebeg klasik kebanyakan di-tanggap orang-orang (pecinta ebeg) zaman dahulu. Tapi jika orang zaman dulu ingin melihat seni pertunjukan yang bagus; karena berpikiran kalau ebeg klasik pernah ia tonton dan ingin melihat suasana baru, ya, itu bisa dengan melihat “ebeg kreasi” (genre pembaruan ebeg klasik). Nyatanya, anak muda zaman sekarang lebih menyukai ebeg kreasi yang dari segi musiknya rapih, padat, dan jika didengarkan terasa enak. Namun, klasik juga enak. Yang terpenting, tidak saling mematikan satu sama lainnya, karena rezeki sudah ada yang ngatur.

Pernah dianggap sebelah mata masyarakat bahwa ebeg itu musyrik, kuno, atau tidak modern?
Terutama dari kalangan beragama. Orang yang ikut ebeg itu rata-rata beragama Islam, tapi mereka kerap kena caci-maki. Memang kenapa, sih, kalau ikut ebeg dicap musyrik? Orang berbicara seperti itu (mengatakan musyrik) tidak apa-apa; karena mereka juga punya mulut.
Hanya saja, saya tidak pernah mengganggu mereka, kenapa mereka mengganggu saya? Ebeg sendiri jika terdengar suaran adzan saja, seketika itu langsung berhenti. Artinya kami menghormati. Kenapa mereka yang merasa beragama tidak menghormati adanya ebeg? Dibilang musyrik, ya, wajar. Tapi dasarnya apa? Membakar kemenyan?
Wajar saja jika ebeg membakar menyan. Kalau bakar tangki Pertamina, nanti malah kena kasus. Katanya ebeg memanggil setan; setan itu wujudnya seperti apa? Kenapa bisa dibilang memanggil? Saya sendiri sebagai penimbul (pawang ebeg)-nya saja, tidak tahu wujudnya setan seperti apa.
Menyan itu bertujuan untuk mengkhusyukkan kita pada waktu berdoa. Zama Sunan Kalijaga hidup, menyan dibakar karena belum terdapat minyak wangi. Adanya, ya, cuma batu menyan yang dibakar; baunya wangi sehingga khusyuk saat berdoa. Sama saja, penimbul juga berdoa kepada Gusti Allah; meminta agar murid-muridnya yang sedang menari tidak ada gangguan; tidak ada yang nginjak beling (serpihan kaca).
Bakar menyan itu tujuannya buat konsentrasi. Tapi, ada versi lain yang mengatakan tukang ebeg membakar menyan untuk memanggil setan. Saya heran, apa benar, mereka tahu setan? Saya sendiri pun tidak tahu setan sepeti apa wujudnya.
Di segi lain, ada yang menganggap kreasi musik-musik ebeg tidak bagus, tidak ini dan itu. Jangan salah paham, justru ebeg bisa mendatangkan ribuan penonton. Pengen bukti sejarah ebeg ditonton ribuan orang? Saya punya buktinya di profil media sosial saya bahwa ebeg ditonton ribuan orang; mungkin pernah lebih dari 70000 orang saat main di Karangsuci dengan 3 rombongan ebeg dijadikan satu. Karena memang, sukma alunan kendangnya ini mblaketaket (kental/nyandu) banget.
Jangankan ebeg, ketika OM Palapa atau Soneta manggung dengan alunan musiknya, sebenci-bencinya orang, pasti otomatis jempolnya bergoyang. Apalagi nonton ebeg, itu sudah pasti badan rasanya geregetan.
Pernah, tidak, ada masanya ebeg meredup; penontonnya berkurang atau jarang dapat job pentas?
Samasekali tidak pernah. Mohon maaf, ya, ebeg selalu pasti di “atas daun”. Misal, ebeg sering dikatakan musyrik, tapi sering tampil di hajatan; mengisi di sunatan massal, mengisi di pengajian, juga memperingati hari-hari besar. Saya lupa di hari besar apa, tapi saat itu kami diundang pihak pondok pesantren, dan ebeg dijadikan penutup rangkaian acaranya. Tempatnya di Jalan Karangsuci.
Di pesantren itu ada yang mendem (kesurupan)?
Namanya juga ebeg, ya, identik dengan mendem. Kenapa harus mendem? Analoginya seperti ini; kalau suka musik dangdut, otomatis jika musik dangdut bergema akan mengundang banyak massa yang ingin melihatnya, sama halnya dengan ebeg. Ini urusan jiwa atau kesukaan, jadi, ketika musik itu dimulai kita akan mendekati sumber suara itu. Intinya, ini seperti klangenan.
Sekarang ini, jumlah orang yang mendem lebih banyak daripada penimbul ebeg. Itu, anak-anak yang dimarahi orangtuanya—dilarang oleh orangtuanya, akhirnya ikut mendem; ikut joget. Anak-anak kecil seperti itu susah untuk diajari seni tari. Justru, mereka lebih tertarik ke yang seperti itu. Wajar jika dorongan mereka untuk mengikuti ebeg dilarang oleh orangtuanya. Intinya, jangan saling menyalahkan.
Bocah sekadar niat. Sedangkan tukang ebeg yang sudah berumur, pasti nanti ada saatnya mereka sadar; karena sudah paham, juga berkeluarga, dan bekerja menghidupi keluarga; dan otomatis tidak selamanya mengurusi ebeg. Rata-rata, mereka mulai sadar sendiri.
Orang mendem itu karena pengaruh kejiwaan atau memang ada roh yang merasukinya?
Namanya juga “seni”. Seni itu “seneng nipu”. Jadi, semua organisasi ebeg memiliki sebuah rahasia. 35% mendemnya bohongan, 65% yang benar-benar kerasukan. Tidak semua orang bisa kemasukan lelembut.
Ebeg pun seperti itu, yang bisa kerasukan hanya satu-dua orang saja. Kalau yang mendem kelihatan banyak banget, sebagiannya itu bohongan karena hanya suka joget—karena alunan musiknya bagus, jadi ada keinginan rasa untuk joget atau mendem. Mendem itu intinya, ada yang menggunakan lelembut, ada juga yang tidak.
Kalau tahu bagaimana caranya kelihatan mendem tapi tidak mendem, itu namanya seni (seneng nipu)—itu rahasia sebuah paguyuban. Tapi intinya, hanya orang-orang tertentu yang bisa mendem. Saya tahu mana yang mendem asli atau tidak. Saya bisa merasakannya.
Kalau ada yang mendem palsu, saya bisa saja ngomong, “Heh, kowe mendem palsu, ora usah melu-melu mendem (Hei, kamu kesurupan bohongan, nggak usah ikut-ikutan).” Tapi tidak mungkin saya melakukan itu, kasihan anaknya. Kecuali jika anak itu susah untuk disadarkan, baru saya pegangi lalu saya bisikkan, “Kowe mendem lemboan, aja keangelan kowe, arep mari apa arep tek siarken nang corong? (Kamu kesurupan bohongan, jangan susah diatur, mau sadar atau saya siarkan lewat corong?)”. Pasti langsung sadar karena malu.
Pernah juga, ada masa nge-hits-nya indang (roh tarian). Banyak yang ingin memiliki itu. Sebenarnya, indang itu bagian dari ebeg, bukan?
Iya, bagian. Di Cirebon, ada sebuah perguruan silat dimana silatnya hanya bisa diiringi oleh gamelan. Jadi kalau tidak ada gamelan, indang atau roh itu tidak akan masuk. Di Cirebon sendiri, rata-rata sabung silat pasti menggunakan gamelan. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa gerakan itu digerakkan oleh lelembut. Maka, merembetlah ke Banyumas. Perguruan-perguruan silat biasanya diisi dengan suatu kekuatan tersendiri. Ketika orangnya bisa masuk dalam ebeg, tariannya jadi campur. Pasti tariannya ada silatnya—tidak sesuai tabuhan gendhing kendang.
Berbeda dengan ebeg, walaupun ada pemainnya yang tidak bisa kerasukan, tapi karena sering dengar suara kendang, kalau ia sedang berpura-pura kerasukan akan pas mendemnya dengan alunan kendang. Kalau orang-orang yang punya “ilmu”, biasanya bisa mendem tapi jogetannya asal. Ngawurnya tidak pas dengan kendang dan mana mungkin bisa pas. Tukang ebeg itu sering latihan; biasa naik jarang kepang, jadi angkat kakinya sudah gampang dan pas dengan alunan kendang. Jadi, ketika ada yang mendem, tapi kok, tidak bisa joget, sudah pasti itu bukan tukang ebeg.
Oh ya, ada sebuah tarian ebeg yang dinamakan “cakilan”. Sebenarnya, cakilan itu seperti apa?
Dalam sejarah ebeg, tidak ada yang namanya Tari Cakil. Terus, kenapa disebut “cakilan”? Cakil itu nama sebuah wayang. Hanya anak yang badannya luwes yang bisa menari seperti wayang. Akhirnya, ia menguasai tarian wayang. Sedangkan di wayang itu sendiri, dilihat oleh orang, tangan wayangnya bisa luwes bergerak ke depan-belakang. Sebenarnya tidak harus Cakil. Karena tangan wayang geraknya begitu luwes ke depan-belakang, orang-orang yang melihat tarian wayang mengidentikkannya dengan tokoh Cakil, maka disebutnya “cakilan”.
Setahu saya, yang ada justru Tari Bambangan Cakil. Itu tarian susah; dan itu sudah termasuk dalam kesenian wayang orang. Saya belajar menguasai tari itu sampai sebulan. Tidak bisa, seni di pewayangan dimasukkan dalam seni ebeg. Kalau ada orang bisa Bambangan Cakil, tidak ada sangkut-pautnya dengan seni ebeg.
Terkadang, ada anggapan bahwa yang menggerakkan cakilan itu lelembut.
Bukan. Lelembut sendiri tidak tahu cakilan. Semisal itu lelembut, di zaman kuno adanya macan, naga, monyet, dan sebagainya. Makanya jin-jin sendiri bisa menyerupai hewan seperti macan, ular, kera, dan jarang yang selain itu. Kalau ada penari yang menyerupai kuda, itu saja karena orangnya lincah di bagian kakinya.
Kalau misal ada seribu orang yang kesurupan lelembut itu cakilan, tidak mungkin ada orang-orang bisa sama semua gerakannya seperti itu, kecuali jika mereka latihan tari wayang itu.
Indang sendiri memang ada dalam tradisi ebeg?
Ada. Mereka itu sifatnya seperti diri kita sendiri. Hanya saja, ia kasat mata. Mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Mereka bisa dipakai di mana saja. Mereka bisa diletakkan di rumah-rumah, di barongan, di kuda kepang, di gong, di kendang, sebagainya. Apalagi di zaman sekarang, ketika pohon-pohon sudah ditebangi, mereka mau menempati mana lagi? Kebetulan mereka juga menyukai kesenian ebeg. Maka dari itu, mereka masuk di ebeg; menempel di barongan dan alat-alat yang digunakan untuk perhelatan ebeg.
Kalau kita bisa kerasukan lewat ebeg, tidak mungkin tidak akan sembuh selama 3 hari atau lebih. Mesti akan sadar pada saat itu juga. Tapi indangnya berbeda dengan indang yang ada di semak-semak (tempat-tempat liar)—yang suka mengganggu orang, membuat orang terluka, atau jin yang diperintahkan untuk membuat orang lain sengsara.
Intinya, sama halnya dengan manusia. Manusia ada yang suka tari, suka hiburan malam, dan lain-lainnya. Indang pun seperti itu; ada yang suka jahil, suka tari, atau suka datang hanya untuk meminta makan saja. Banyak jenisnya.
Berarti seni ebeg tidak mewajibkan memiliki indang?
Tidak. Tapi setidaknya, kita harus tetap menghormati bangsa lain, karena Gusti Allah tidak menciptakan manusia saja. Tuhan menciptakan hewan dan juga jin, kenapa kita manusia tidak mau saling menghormati. Kuncinya cuma satu: jangan “meminta” kepada jin.
Jikalau mereka meminta makan, selagi kita masih mampu, ya, kasih. Jika kita tidak mampu, mereka tidak akan marah kepada kita. Mereka bisa mencari makan sendiri. Analoginya begini, jika kita berteman, ketika anda meminta kopi, bisa saya kasih.
Saya sendiri, ingon-ingon (piaraan)-nya banyak. Jika mereka datang, ya, saya kasih. Jika tidak ada sesuatu, ya, tidak saya kasih. Mereka tidak memaksa. Kecuali kalau mereka meminta darah manusia, tidak akan saya kasih, saya sendiri tidak punya. Kalau saya bisa memberinya, lalu timbal-baliknya buat saya, apa?
Ketika seseorang kerasukan lalu meminta kopi, itu salah satu bukti kita dapat melihat bangsa jin, meskipun kita tidak tahu wujudnya. Mohon maaf, ketika anda duduk di sini, ada dua ingon-ingon saya di sini yang sedang sama seperti kalian—sedang mendengarkan saya juga.
Saya tidak memaksa orang untuk percaya. Akan tetapi, setiap orang yang menyukai kesenian ebeg pasti 90%-nya percaya, sedangkan orang yang tidak suka atau orang-orang fanatik agama pasti memberinya stigma.
Kalau indang bisa dimiliki, apakah bisa diwariskan?
Kamu punya rasa bosan? Sama dengan jin-jin itu sendiri, apabila mereka sudah tidak dirawat, atau kalau kamu sudah tua, sudah meninggal dunia, pasti mereka akan pergi dengan sendirinya—tidak perlu dibuang. Kadang-kadang, ada seseorang dibawa ke kyai untuk membuangnya. Sebenarnya, itu tidak perlu dilakukan, pasti akan hilang dengan sendirinya. Mereka pun memiliki rasa bosan—sama seperti manusia.
Seandainya saja bukan untuk seni, saya pasti bisa mewariskan ke anak-anak saya atau ke murid-murid saya. Karena saya suka joget, pasti nantinya mereka akan menjadi seorang penimbul. Yang sering terjadi biasanya seperti itu. Ketika semakin tua dan mengajari ke generasi-genarasi selanjutnya—ketika sudah jadi pamong, biasanya indang-indang sudah tidak mau menempel. Tapi mereka menjadi semakin penurut; mau melaksanakan apa yang diperintahkan si pemiliknya.
Bagaimana hubungan ebeg dengan kepercayaan lainnya—semisal Kejawen?
Identik. Namun, orang yang ikut ebeg tidak diwajibkan sowan (mengunjungi tempat keramat). Apabila diajak sowan, mau, ya, ayo. Nah, konteksnya sowan itu seperti apa? Jika maksudnya sowan adalah untuk “meminta”, kamu sudah termasuk orang-orang musyrik.
Contohnya, kalau kamu sowan dan meminta “aku pengen bisa mendem”, itu musyrik. Karena meminta itu, ya, kepada Gusti Allah. Jangan sampai meminta kepada yang di dalam kuburan. Tapi, makam-makam tua seperti panembahan itu marwahnya sudah sampai ke atas, dan “yang jaga” di sana banyak sekali. Makanya kuburan-kuburan yang seperti itu jangan sampai dirusak; karena tempat dikuburkannya orang yang dulunya berjasa.
Mesti banyak pula yang jaga di tempat seperti itu. Setiap ada orang yang meminta, pasti mereka senang sekali dan mencoba menjerumuskannya ke neraka. Tapi ketika kamu datang sowanan untuk mendoakan seseorang supaya seseorang itu masuk surga atau doa-doa positif lainnya, mereka juga ada yang ikut senang, sehingga jin-jin itu menyuruh teman-teman jinnya untuk mengikuti mereka yang menurut bangsanya baik. Maka tanpa disadari, kalian akan memiliki “pegangan” sendiri seperti itu. Bila kalian memiliki batu-batu tua di rumah, tanpa kalian sadari, jin itu bisa langsung masuk dalam batu tua tersebut, atau masuk ke dalam lemari dengan bahan kayu tua. Bisa jadi, mereka justru merasa senang tapi kamu tidak merasakannya.
Bahkan, semua manusia ada jinnya. Hanya saja, tinggal bagaimana jin tersebut mengganggu atau tidak, atau suka menari atau tidak. Sebenarnya kuncinya cuma satu; yaitu jin itu sendiri bisa menyerupai. Keberadaan indang tidak diwajibkan untuk dipercayai atau tidak oleh pemain ebeg. Tapi hal itu identik ada.
Kita tetap perlu sowan agar meminta doa restu kepada sang pendahulu. Kalau kita mau mendirikan sebuah rombongan ebeg, nantinya akan diberi wejangan oleh juru kuncinya. Juri kunci tersebut yang bisa berkomunikasi dengan jin-jin itu.
Kenapa orang mati sering lebih pengaji (dihormati) daripada orang hidup? Kenapa panembahan lebih ramai dibandingkan rumah kita?
Ketika ada orang memerintahkan bahwa merawat kuburan itu dianggap musyrik, itu salah besar. Meskipun nantinya nyawa kita sudah ke mana-mana, tapi ada saja orang yang merawat kuburan sebagai penanda. Apa salah seperti itu?
Pernah pula, ebeg dituduh sebagai kebudayaan orang-orang penganut aliran Kepercayaan. Tidak apa- apa, mereka mengklaim seperti itu karena itu suatu alirannya orang Jawa. Tapi padahal, memang ada orang Islam yang main ebeg. Hanya saja, tidak mau dibilang orang Kejawen. Kenapa bisa begitu?
Karena Islam cenderung memegang teguh Al-Qur’an, sedangkan aliran Kepercayaan tidak memegang teguh kepadanya—mereka hanya percaya adanya Tuhan. Tapi menurut saya, kalau digarisbawahi, aliran Kepercayaan itu sebenarnya Islam. Hanya, Islamnya mereka itu Islam Jawa, dan babadnya bebarengan dengan Sunan Kalijaga.

Bisa dibilang, trah ajaran Islam segaris dengan kebudayaan Jawa.
Kalau bilang Jawa, itu luas. Sebelum ada Walisongo, sudah ada beberapa syekh. Mereka (syekh) bukan dari Jawa, biasanya dari Sumatera. Konon, ada 21 syekh yang datang ke Jawa untuk babat alas. Tapi karena tanah Jawa itu angker banget, jadinya mereka tidak sanggup, akhirnya mereka pulang. Sehingga, diutuslah Walisongo.
Walisongo pun menyebarkan Islam dengan berbagai cara, serta di antara mereka saling bertentangan. Contohnya, ketika Sunan Kalijaga menggunakan gamelan saat itu, ia dimarahi oleh yang lainnya. Ya, wajar saja, kalau beragama ada lain-lain versinya. Intinya, kita tidak perlu mencari kesalahan orang lain; biarkan orang lain mencari kesalahan kita, tidak apa-apa.
Saya sendiri sering berdebat, kalau kamu perhatikan di sosial media saya. Pernah, ada orang yang bilang bahwa ebeg itu diharamkan Islam. Saya cuma bisa membalasnya: Sini ke rumah, ngopi bareng aku.
Saya sering bertanya balik ke mereka; apanya yang diharamkan? Togel saja, yang jelas-jelas judi, masih banyak yang beli. Kenapa kok seni-budaya diharamkan? Ya, kan, tidak masuk akal. Ada juga yang pernah update status, pas saya komen, langsung dihapus. Kemudian, orangnya nginbox saya, “Nyong ora wani debat karo rika (Aku gak berani debat dengan kamu).”
***
Saya mungkin ketua grup ebeg paling muda se-Banyumas Raya, rata-rata yang lainnya sudah menjadi sepuh. Saya masih belum berani dianggap kasepuhan. Tapi, banyak juga dari mereka yang “bersekolah” ke paguyuban saya di sini.
Dengan perkembangan ebeg saya yang pesat, yang belum pernah gagal di setiap perhelatan di setiap bulannya, mereka semuanya yang datang ke sini bertanya: bagaimana caranya ebeg saya bisa jalan terus? Ada bertanya, kalau saya pakai “ritual” apa? Saya tidak pernah menggunakan ritual.
Intinya, satu: kalau kalian hormati bangsa jin karena mereka buatan Gusti Allah, ya, kalian jangan kematos (sok keras); ketika ada yang mendem, jangan “memaksanya” keluar dari seseorang. Yang kedua, memasang sesaji secukupnya, tidak perlu terlalu macam-macam. Semisal, kamu memiliki uang sejumlah 75000, ya, kamu belikan dengan harga segitu.
Jangan sampai merasa dengan harga segitu masih kurang, karena tidak perlu seperti itu juga. Terkadang, ada yang untuk beli sesaji saja, sampai seharga 250 ribu. Itu berlebihan. Kenapa? Toh, yang makan sesaji juga orang paguyuban kita sendiri. Kalau adanya uang 75 ribu, ya, belikan saja pisang, meskipun rasanya sepat, ya, tetap saja kita yang makan. Apa, iya, kalau kita mendem terus kelaparan, kita mau minta makan lalu masuk rumah orang?
Kadang, ada juga yang kerasukan dikasih makan bunga tapi tidak mau, ya, karena itu bukan makanan kesukaannya. Malah ada juga yang dikasih pisang, tidak mau, tapi memilih makan mawar yang rasanya manis karena itu kesukaannya. Apalagi yang suka banget kelapa muda, mau dikasih 20 biji, tetap saja habis dimakan. Jadi begini, misalnya kalau kalian mendem atau menari sampai kecapekan, apa cocok langsung dikasih air es? Ya, pantasnya diberi air degan (kelapa muda). Nah, ketika perhelatan sudah selesai, barulah wajar untuk meminum semacam es teh.
Segar juga, sih, kalau menunggang jaran kepang sambil minum es teh. Tapi, apa ya, sesuai dengan konsep jaran kepang? Terkadang ketika air degan habis, saya kasih saja air bening biasa untuk penggantinya. Mereka juga tidak pernah komplain. Ketika mereka tidak sadarkan diri, mereka hanya meminum apa yang diminta dan apa yang dikasih dari penimbul.
***
Kalau bicara soal ebeg, peradaban ebeg di Cilacap sangatlah pesat. Bahkan, dicintai oleh banyak kalangan; bukan sekadar orang-orang tua, bahkan anak-anak remaja kekinian pun larinya ke ebeg. Bisa saya buktikan lewat inbox pesan yang masuk ke saya itu rata-rata dari anak muda. Pesannya juga lucu-lucu; ada yang ingin meminta punya indang, ada pula yang ingin ikut ebeg tapi takut dimarahi orangtuanya, ada juga yang cuma ingin ikut mendem ketika ebeg itu dihelatkan di suatu tempat. Aneh-aneh, kan?
Makanya, saya ajak mereka datang ke rumah; saya belajari main gendingan (gamelan Jawa) sampai pintar. Sekarang, justru para orangtua menjadi senang karena anak-anaknya tidak ikut mendem, tetapi menjadi penabuh gamelan. Anak-anak juga senang dapat memainkan gamelan, serta bisa menghasilkan uang saku sendiri dari sini. Sementara, para panayagan (penabuh gamelan) tua juga sudah tergerus oleh umur dan tenaganya semakin berkurang. Sehingga, mereka sering digantikan oleh anak muda yang tenaganya masih kuat. Sekarang, hampir kebanyakan anak muda sudah mengisi semuanya (keterampilan seni tradisi); seperti lengger (tarian Banyumasan) pun kini banyak digandrungi anak-anak muda. Orang-orang tua masih bisa diandalkan untuk mengisi suara sinden karena suara khas melengkingnya belum tentu bisa diikuti anak muda.
***
Ketika kaum Kejawen melakukan kegiatan sedekah laut atau sedekah bumi, mereka cenderung tidak menggunakan organ tunggal, justru menggunakan ebeg. Itu karena mereka identik dengan alunan-alunan musik tradisional yang terdapat di zaman dulu. Pertanyaannya juga, apakah sedekah bumi itu terdapat dalam Al-Qur’an? Itu, kan, warisan.
Kenapa harus ada ebeg atau wayang? Supaya menarik massa yang banyak. Ebeg atau wayangan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memberi tahu masyarakat bahwa ada kegiatan semacam sedekah bumi; karena ebeg dan wayang adalah media paling cepat untuk menarik massa berdatangan. Bahkan sekarang, mohon maaf sebelumnya, bukannya saya bermaksud untuk menyingkirkan perhelatan organ tunggal, tetapi untuk perihal tontonan, tetap banyak yang tertarik datang ke ebeg, justru lebih banyak. Jadi di setiap tabuhan gendangnya, seakan terdapat ajakan, “Ayo nonton, ayo nonton.”
Sebenarnya juga karena saling mengisi. Ketika ada ebeg, alhamdulillah, kios-kios penjual menjadi laris. Contoh kecilnya, ketika kami tampil di Lapangan PJKA, di sana itu pajaknya besar; ada uang kebersihan, serta uang sewa lapangan—itu pun sudah sama halnya dengan berbagi rezeki. Apalagi, ketika jualannya para pedagang jadi laris. Jadinya, ketika saya beli es saat itu pun tidak bayar, hehehe… Pas kelompok ebeg saya yang tampil, justru pedagang yang menawarkan gratisan ke saya. Intinya, ya, saling mengisi.
Pada dasarnya, tontonan ebeg di Cilacap sendiri, itu tontonan yang di “atas angin”. Tapi dengan keadaan adanya Covid-19 seperti ini, kita tidak bisa tampil. Ketika saya memperjuangkan hal ini bersama teman-teman, justru respon kebijakan dari bupati masih menutup kemungkinan tentang adanya tontonan di Cilacap. Tapi, kenapa hiburan malam seperti karaoke sudah dibuka? Kenapa tontonan semacam ebeg belum diperbolehkan? Mungkin karena sekali ebeg tampil, yang nonton ribuan.
Sementara di desa-desa, ebeg sudah diperbolehkan. Sedangkan di perkotaan Cilacap masih belum diperbolehkan. Hal yang menjadi pertanyaan ini bisa saya jawab, tapi tidak oleh bupati. Di desa-desa, lurahnya itu dipilih warga. Ketika ia dicopot jabatannya karena mengizinkan tontonan, ia tinggal menjawab mengikuti kehendak warganya. Berbeda dengan lurah di kota, ketika dipecat karena melanggar protokol Covid-19, ia bakal pensiun dini—dari PNS. Maka dari itu, di kota, sulit diperbolehkan izin. Akhirnya, bupati malah menghimbau untuk meminta izin ke lurah atau camat masing-masing.
Sebentar lagi, juga akan ada peringatan bulan Sura (kalender Jawa) yang jatuhnya berada di bulan September (2020). Kemungkinan besar, tontonan adat belum bisa dibolehkan. Apalagi masuk bulan Agustus, APBD pengeluarannya besar. Apakah Cilacap memiliki uang besar untuk saat ini?
Maka kemungkinannya, Agustus ini tidak ada helatan apa-apa alias bebeh ngetokna duit (tidak mau mengeluarkan dana). Takutnya juga, ketika ada orang yang terpapar Covid-19 juga. Setiap orang memiliki hak untuk sehat. Saya yang punya sebuah paguyuban ebeg ini punya hak untuk tampil, tapi di satu sisi lain, ada yang memiliki hak untuk sehat juga. Nah, bagaimana caranya agar saya bisa tampil tapi kalian sehat juga? Itu suatu hal yang sangat sulit. Jalan satu-satunya, ya, saya menurut kepada pemerintah; ketika belum ada izin, saya belum memberanikan diri untuk tampil.
Tetap saja ada suatu rombongan ebeg yang tidak mau nurut, ya, itu terserah mereka. Nanti mereka sendiri yang malu kalau dibubarkan paksa polisi. Ada juga pegiat yang meng-update di dunia maya, “Deneng aku ora ijin, aman. (Buktinya, aku tidak berizin, aman).” Mungkin sedang beja saja. Coba saja kalau kasusnya sama seperti yang terjadi di Sidareja; dirazia polisi, diangkut semua gamelannya.
Ada juga yang komen ke saya, “Karuan, kowe entuk gaji wulanan. Lah, kayak nyong pengendang arep ngapa? Ya, ora entuk nggo mangan. (Karuan, kamu dapat gaji bulanan. Kalau saya, cuma penabuh gendang, mau bagaimana? Ya, tidak bisa dapat makan).” Bayangkan saja, selama 3 bulan kamu masih bisa makan, masih hidup, tapi hutangnya menjadi banyak. Namanya juga manusia, pasti punya hutang dan simpanan, tapi sekarang perputaran hidup sedang di bawah. Harus gimana lagi? Setahu saya, belum ada sejarahnya pekerja seni mati kelaparan. Tapi harus tetap bertanggungjawab kepada anak-istri. Ya, caranya seperti jual motor, kulkas, atau kalung istri, hahahaha…
Ebeg itu tidak bisa menjamin untuk mencari nafkah, itu tidak bisa. Hanya saja, bagaimana carannya agar kita bisa nguri-uri budayanya supaya tetap urip. Urip, ya, syukur, syukur-syukur bisa ngurupi budayane dhewek (Bisa hidup, ya, syukur, syukur-syukur bisa menghidupi budaya kita sendiri).
Contoh kecil yang saya alami, saya mencoba menghidupi kebudayaan dan kebudayaan itu hidup. Sementara, saya memiliki peralatan yang komplet. Terus, bagaimana caranya untuk menghidupi saya? Ya, lewat penyewaan pakaian seragam ebeg.
Pas saya tidak sedang bekerja, anak-anak sekolah datang ke sini; ada dari AMN (Akademi Maritim Nusantara), SMP Negeri 3, dan banyak lagi. Ketika ada acara perpisahan, Agustusan, atau pentas seni tari, mereka ke mari. Apalagi sekarang, anak-anak SMP kelas 3 harus ada penilaian seni tari. Dari situlah, baju seragam bisa dipinjamkan dan dapat menghidupi saya saat tidak memiliki uang samasekali. Dari pada hutang, kan, ada rezeki dari situ. Itu yang namanya me-nguripi.
Kalau jadwal pentas berbarengan jadwal kerja, bagaimana?
Saya punya jatah cuti 12 hari selama setahun. Kalau misal ada tanggapan (undangan pentas) pas hari kerja, kalau jatah cuti masih banyak, maka saya ambil cuti. Karena saya tidak mau merugikan orang lain, juga saya juga tidak mau rugi dalam pekerjaan. Kalau saya lebih mementingkan ke ebeg, saya tidak ambil cuti, saya bisa dipecat dari pekerjaan. Eman-eman. Terus, menafkahi anak-istri pakai apa?
Makanya, saya tidak pernah cuti; saya hanya cuti ketika ada tanggapan ebeg saja. Baru dari situlah, saya manfaatkan hak cuti saya. Namanya juga orang nanggap, kan, tidak mungkin dadakan; mesti satu bulanan sebelumnya, saya sudah bikin surat cuti. Paling-paling, satu tahun hanya 4-5 kali cuti, karena yang nanggap kebanyakan pas hari Minggu. Kecuali kalau acara seperti sedekah laut yang sudah pasti jatuh pada hari Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon di bulan Sura.
Kalau caranya mengatur jadwal latihan?
Latihan rutinan pada hari Minggu. Entah ada pentas atau tidak, hari Minggu, ya, tetap latihan. Nanti ketika ada tanggapan di hari lainnya, malamnya kami latihan; supaya tak ada yang terlupakan.
Di setiap pementasan, tarian kami berbeda; karena menyesuaikan tempatnya juga. Tergantung pada pola lantai atau struktur tanahnya seperti apa. Dengan begini, orang-orang yang melihat pun tidak bosan. Itulah gunanya latihan.
Saat waktunya semakin mendekati perhelatan, serta untuk mengurangi kemungkinan adanya kesibukan mendesak dari para penari, kami akan mendata dulu siapa yang bisa dan tidak bisa mengikuti acara tersebut, sekaligus menentukan posisi-posisinya supaya tidak berubah lagi. Ketika nanti kendang berlabuh, mereka akan mengikuti dengan sendirinya. Dengan begitu, sudah bisa terdapat konsep panggung dan sistem artistiknya. Kalau kita menarinya acak-acakan, bagaimana ada orang mau menyewa kepintaran kita?
***
Sekarang, ada berapa anggota Turangga Edan?
Secara keseluruhan, dari paling senior sampai junior ada sekitar 120 orang. Sementara, yang masih aktif ada sekitar 35 orang. Tapi untuk pemain gamelannya, seringnya kami nyewa. Kalau anak wayang-nya, kami pakai punya sendiri karena banyak yang bisa. Bahkan sebenarnya, gamelan pun milik saya sendiri, tetapi sering digunakan untuk rombongan. Itu, gamelan dari hasil uang saya sendiri.
Cara bagi hasil uang pentasnya, bagaimana?
Dinilai dari tingkatannya. Tingkat paling tinggi itu tukang gendang, kedua itu sinden, terus pemain alat balungan (saron), lalu pemain gong, kemudian penimbul, pengurus, dan anak wayang. Anak wayang sendiri justru paling sedikit bayarannya, padahal dia kerjanya paling capek di antara yang lainnya; karena memang, ya, senang, bukan karena pekerja.
Adakah standarisasi harga pentas?
Soal harga, sih, bebas. Tapi kalau harganya mahal, pasti bawa “rupa” (kualitas baik). Rata-rata harga pentasnya sekitar 5-6 juta untuk sekali tampil. Kalau harga pasaran punya kelompok saya sekitar 7 jutaan untuk setiap kali tampil. Kalau ada diskon, ya, itu untuk teman sendiri.
Ada stigma terhadap mahalnya harga pentas?
Tergantung pada kesukaannya. Sama halnya, kalau kamu beli HP seharga 1,1 juta, tapi ada orang lain yang beli dengan harga 1,7 juta karena chase-nya bagus, ya, itu karena kepuasannya masing-masing pembeli dengan yang dibelinya. Sama halnya dengan ebeg saya. Meskipun pentas ebeg saya harganya mahal, tapi tetap lebih banyak peminatnya dibanding ebeg-ebeg yang lebih murah, karena masih sanggup memberikan yang terbaik.
Tatanan ebeg kami sangat banyak pada waktu pementasan. Untuk tarian pertamanya, kami memakai penari perempuan, keduanya dengan penari laki-laki, nanti yang ketiga pakai penari perempuan lagi. Sekarang ini, bisa melihat anak perempuan bisa menjadi pemain itu adalah sebuah perubahan. Meskipun ada juga yang berpikir, “Bebeh temen nonton ebeg wadon (Enggan banget lihat ebeg perempuan).”
Cara penyajian kami juga banyak sekali. Mulai dari mengadakan organ tunggal ketika istirahat, supaya penonton tidak langsung meninggalkan lapangan pertunjukan. Selain itu, pula diisi dengan tari lenggeran, tari reog, atau penari barong.
Di rombongan kami, kami punya 13 barongan. Padahal zaman dulu, hanya ada sekitar 2 buah saja; karena membuat satu barongan harganya mahal. Bahkan, saya bercita-cita untuk memiliki sebanyak 20 buah barongan. Kalau punya sebanyak itu, terus siapa yang mau memainkan? Ya, orang dari luar grup kami; karena banyak orang luar/penonton yang ingin memakai barongan. Mereka main pun, tidak perlu dibayar. Ketika sekarang ada 13 buah saja, mereka saling berebut, apalagi jika cuma 2.
Barongan atau jaranannya buatan sendiri atau membeli?
Barongannya masih beli, karena saya pribadi belum sempat bisa membuatnya. Mencari bahan kayunya susah, lalu saya juga tak ada waktu memahatnya. Untuk membuat satu barongan saja, membutuhkan waktu kurang-lebih 1 bulan; dari mulai memahat, penghalusan, memasang engsel, pengecatan, lalu dikasih baju—bisa memakan waktu sebulan. Daripada seperti itu, lebih baik beli.
Tapi jaran kepangnya, kami buat sendiri. Kalau jaran kepangnya beli, tekadang tidak enak saat dipakai. Kalau yang buatan sendiri, terasa ada kepuasan batin saat memakainya, sehingga pas untuk menari.
***
Di sini, rombongan ebeg yang mendapat binaan “perusahaan rokok” hanya punya kami dan kelompok Jalan Bakung. Tiga bulan sekali, kami dapat 1,3 juta rupiah. Yang diharapakan dari perusahaan itu adalah agar rokoknya tetap dikenal. Berikutnya, supaya dapat branding dari paguyuban ebeg. Tugas kami hanyalah mengumpulkan grenjeng (kertas dalam bungkus) untuk mendapatkan bonus, sehingga memberikan apa yang diinginkan dari sebuah paguyuban ebeg. Kami sudah 3 kali memperolehnya. Dan baru kali ini, dapat dana binaan 2 kali berturut-turut.
Kalau alat-alat ebeg dijual semuanya, itu bisa untuk membeli 2 motor baru. Gamelan kompletnya saja, bisa sekitar 13 juta, harga 1 barongan bisa sekitar 1 juta, belum lagi baju-baju pemainnya. Kami saja, memiliki 7 desain baju.
Selama ini, belum ada himbauan resmi dari pemerintah mengenai ebeg. Pemerintah tidak hanya me-ngoprak-oprak, “Ayo diuri-uri!” Orang-orang besar hanya bilang untuk diuri-uri (dilestarikan), tapi ketika mereka ada hajatan, tidak pernah menampilkan ebeg. Justru yang sering menanggap kami dari kalangan orang-orang biasa.
Dahulu, sering diadakan lomba ebeg. Berbeda dengan sekarang, sudah tidak ada lomba ebeg digelar—hampir 10 tahun ini. Waktu saya ikut grup orang lain, dulu, sempat merasakan ada 3 kali lomba. Yang diharapkan dari teman-teman ebeg adalah ingin kembali seperti semula; sering diadakannya perlombaan.
Kapan terakhir ada lomba?
Sekitar tahun 2012, tempatnya di Benteng Pendem. Waktu itu, diadakan oleh Djarum Super. Alhamdulillah, grup saya mendapat juara 2. Justru, ada grup yang jarang tampil mendapat juara 1. Sampai akhirnya, saya menanyakan itu kepada panitia perlombaan. Jawaban panitia; karena grup saya sering pentas, maka grup yang lain dijuarasatukan supaya naik daun. Jadi, tujuan panitia adalah untuk memberi jalan kepada grup ebeg tersebut. Ya, namanya juga rezeki, sudah ada yang ngatur.
***
Sekarang, hampir setiap (otoritas) kecamatan enggan menampilkan tarian ebeg untuk pentas perlombaan. Pola pikirnya, kalau menampilkan ebeg tidak akan juara. Jadi, kalau saya pribadi diminta untuk mewakili kecamatan, saya akan tetap menari, tapi bukan tarian ebeg. Orang-orang yang saya ajak menari pun dari ebeg, karena mereka bisa menguasai gerakan-gerakan tari; sehingga latihannya tidak susah.
Saya sering diminta mewakili kecamatan. Tapi saya harus pintar-pintar titiwayah (penempatan). Saya pernah main dihargai 200 ribu. Sekarang, saya memillih siapa yang bisa membayar mahal. Meskipun saya tinggal di Cilacap Selatan, saya bisa tampil untuk Kecamatan Cilacap Tengah, tergantung siapa yang berani bayar mahal.
Kenapa begitu? Karena kasihan teman-teman saya yang sering latihan dan jika bayaran yang didapatkannya tidak setimpal. Pernah ada, ketika kecamatan lain mengundang saya dengan mahar 17 juta untuk mewakilinya. Kemudian, saya langsung berpikir untuk menampilkan tarian yang belum ada di Cilacap.
Saya pun menciptakan “Tari Memedi”. Tarian itu mengangkat pembabatan alas (hutan) di Nusakambangan; tentang Nusakambangan yang diobrak-abrik oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. Maka ceritanya, keluarlah makhluk-makhluk semacam tuyul, genderuwo, kuntilanak, dan sebagainya yang diaplikasikan dengan tarian. Tetapi, memedi (makhluk halus) itu tidak bisa dikalahkan oleh kyai (tokoh spiritual). Mereka malah dikalahkan dengan uang. Jadi, ada adegan mereka mengejar-ngejar orang yang membawa dollar.
Gambarannya, kami membuat replika Nusakambangan. Di situ, ada adegan gerakan mencangkul yang disesuaikan dengan alunan. Ada juga adegan menebang pohon dan kegiatan lainnya. Karena marah, keluarlah tuyul, kuntilanak, dan lain-lainnya. Datanglah kyai, tapi mereka itu tidak takut sambil menari-nari. Begitu ada satu orang membawa uang dollar, barulah mereka berlarian mengejarnya.
Jelas ada maksud di dalam tarian tersebut, dan hanya orang-orang politik yang tahu. Nusakambangan telah diambil untuk perusahaan semen, sedangkan pihak otoritas mendapat bagian dari bisnis terselubung. Maka dari itu, saya mengkritik sangat dalam lewat sebuah tarian. Saya hanya mendapatkan juara 2 dari perlombaan.
Lalu, bagaimana respon pemerintah setelah melihat tariannya?
Ada beberapa orang pemerintahan yang tersinggung dan melontarkan ucapan kasar—seperti “bangsat“ dan “anjing”. Sementara, camatnya sendiri mendapat kritikan. Kebetulan waktu itu, saya mewakili Cilacap Selatan. Sebenarnya, saya juga menyinggung DPRD.
Berapa kali tarian itu ditampilkan ke masyarakat?
Dua kali. Pernah juga dibawakan di Semarang.
Ketika di Semarang, kami mebawakannya masih tapi dengan cerita yang berbeda. Di sana, kami menceritakan tentang perebutan bunga wijayakusuma di Nusakambangan. Soalnya ketika kami berlomba mewakili Cilacap, kami harus membawakan identitas atau simbol-simbol Kota Cilacap. Jadi, yang kami bawa itu bunga wijayakusuma. Di situ, kami mengisahkan wijayakusuma menjadi rebutan para raja, lalu memedinya keluar banyak sekali. Kami pulang ke Cilacap dengan mendapatkan posisi juara ke 2.
***
Saya sering kesulitan ketika proses mengarang sebuah cerita atau semacam babad alas. Untuk itu juga, saya harus kesulitan ketika membuat properti. Semisal ketika membuat replika wijayakusuma, saat mencoba pakai styrofoam tidak bisa jadi, juga menggunakan kertas minyak tidak jadi. Akhirnya saya memutuskan untuk membayar sewa properti seharga 3 juta. Dipikirkan juga bagaimana caranya agar properti itu ringan untuk dipikul.
Sewaktu mengikuti lomba di luar kota, saya mendapat banyak sripilan (uang saku) karena kami mengamen di sekitaran Simpang Lima, Semarang. Saat mengamen, saya menggunakan daster hamil. Kami juga membawa alat-alat musik; seperti 2 buah saron, 1 gong, dan 1 kendang.
Kami mencoba melawak menggunakan sebuah tarian. Di situ, saya merasa kesulitan bagaimana caranya menari sambil membuat orang sekitar tertawa. Semalam, kami mendapat uang sebesar 1,3 juta. Di sana, banyak sekali pakar kesenian dan mereka semuanya mau memberi.
Transkrip wawancara ini dimaksudkan sebagai kontribusi pada lembaran zine Semilir yang digagas semenjak Agustus 2020. Sebagai stimulan warganet, naskah ini turut dihadirkan pada blog ini. Selamat menikmatiii… [Kru Zine Semilir]