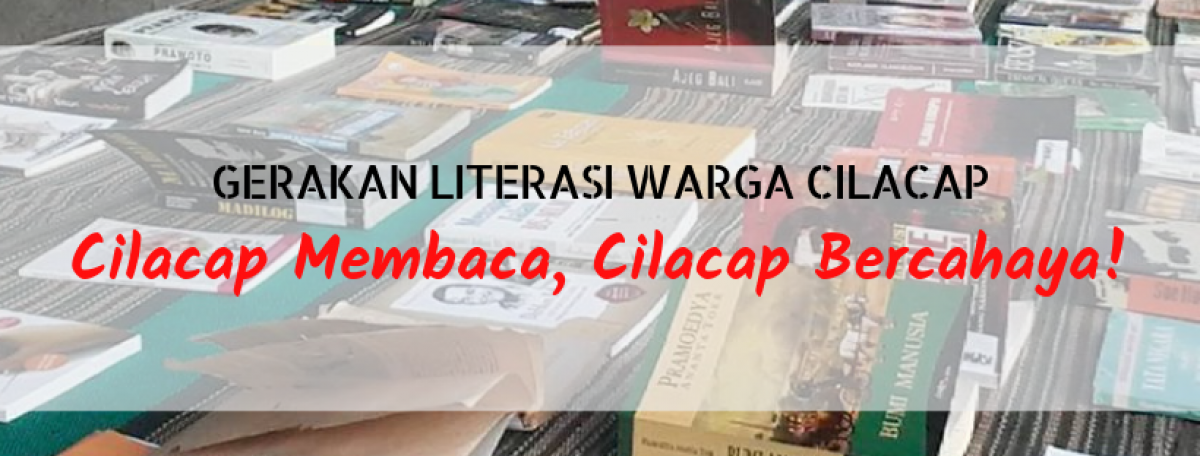–
*)Ditulis oleh David Livingstone Smith. Profesor filsafat Universitas New England dan direktur Human Nature Project. Menerbitkan buku “Less Than Human” pada 2011.
–
Dari waktu ke waktu, kenapa banyak orang menyambut pemimpin yang tirani dan otoriter?
Beribu-ribu tahun, para filsuf dan teoritikus politik mencoba menjelaskan alasan kita bersedia berpartisipasi dalam penindasan diri kita sendiri dengan menjadi tunduk kepada para pemimpin otoriter. Dan hari ini, kebangkitan rezim otoriter yang tidak menyenangkan di seluruh dunia membuat pertanyaan ini menjadi mendesak seperti saat sebelumnya.
Plato merupakan salah satu pemikir pertama dan paling berpengaruh untuk membicarakan masalah tirani. Dalam karya “Republic”-nya yang ditulis sekitar 380 SM, ia berpendapat bahwa negara-negara demokratis ditakdirkan untuk jatuh ke dalam tirani.
Plato menjadi seorang yang tidak menggemari demokrasi mungkin dikarenakan guru kesayangannya; Socrates, dihukum mati oleh demokrasi Athena. Dia percaya bahwa bentuk pemerintahan demokratis dapat menciptakan masyarakat tak bermoral dan tidak disiplin sehingga mudah menjadi mangsa bagi politisi yang cakap dan terampil dalam memainkan nafsu keinginan mereka.
Dalam naskah “Gorgias” yang ditulis pada sekitar waktu yang sama dengan “Republic”, ia memberitahukan kita bahwa politisi semacam itu memikat massa dengan janji-janji tidak sehat daripada memelihara kebaikan publik. “Kue pastry telah bertopeng sebagai obat dan berpura-pura mengetahui makanan yang terbaik untuk tubuh. Sehingga jika pembuat kue dan dokter harus bersaing di depan anak-anak atau di depan pria yang sama bodohnya dengan anak-anak—untuk menentukan yang mana di antara keduanya; dokter atau pembuat kue, yang memiliki pengetahuan sebagai ahli makanan yang baik dan buruk, maka si dokter akan mati kelaparan,” begitulah yang ditulis Plato.
Ada karya sosiolog Jerman; Max Weber, yang dipertimbangkan pada masa dua setengah milenium atau awal abad ke-20 lalu. Weber; salah seorang pendiri sosiologi, mengembangkan konsep “otoritas kharismatik” atau kualitas tertentu dari kepribadian individu yang kebajikannya tidak seperti manusia biasa dan diperlakukan sebagai orang yang diberkati daya supranatural atau sebagai manusia super; atau setidaknya memiliki kekuatan khusus atau kualitas luar biasa. Para pemimpin kharismatik akan menginspirasi orang untuk mengabdi dan dianggap sebagai figur kenabian oleh pengikutnya.
Pandangan Weber memperdalam catatan samar Plato. Kebangkitan tirani memiliki aura tertentu yang hampir magis. Para pengikutnya percaya bahwa ia dapat melakukan mukjizat dan mengubah hidup mereka. Namun bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan orang-orang rasional menjadi berserah diri untuk mengadopsi pandangan berbahaya nan tidak realistis seperti itu? Untuk menjelaskannya, kita perlu menggalinya lebih dalam.
***
Saat Weber sedang mengembangkan “teori kharisma”-nya di Berlin, Sigmund Freud sedang bergulat dengan pemikiran serupa di Wina (Austria). Pemikirannya memuncak dalam buku “Group Psychology and The Analysis of The Ego” (1921). Buku itu berfokus pada dinamika psikologis para pengikut.
Seperti kebanyakan karya Freud, buku tersebut merupakan teks yang rumit. Tetapi, ada dua tema utama yang menonjol dari dalamnya. Pertama, Freud berpendapat tentang mereka yang tertarik pada pemimpin otoriter yang diidealkannya. Pemimpin dipandang sebagai teladan atau manusia heroik untuk mengatasi setiap kesalahan serius. Kedua, ia berpendapat bahwa pengikut mengidentifikasikan dirinya dengan pemimpin dan menggantikannya dengan sesuatu yang disebut “ego ideal” oleh Freud. Ego ideal adalah representasi/cerminan mental dari nilai-nilai panduan seseorang; yang terdiri dari kepercayaan tentang “benar” dan “salah” atau apa yang menjadi “wajib” dan “tidak boleh”. Hal ini menjadi semacam kompas moral kita yang pada dasarnya sama dengan hati nurani seseorang. Dalam menggantikan cita-cita ego mereka, pemimpin otoriter menjadi suara hati para pengikutnya dan suaranya menjadi suara hati nurani mereka. Sehingga apapun kehendak pemimpinnya, akan menjadi baik dan benar menurut pengertian para pengikutnya.
Tesis Freud sangat sesuai dengan kasus yang terjadi pada era kekuasaan Hitler di Jerman. Sebagai pertimbangannya adalah kasus Alfons Heck. Sebagai seorang anak muda, Heck telah menjadi anggota Hitler Youth. Dalam buku “The Nazi Conscience” (2003), sejarawan Claudia Koonz menuliskan bahwa saat Heck menyaksikan Gestapo mengumpulkan orang-orang Yahudi di desanya untuk dideportasi—termasuk sahabatnya Heinz, ia tidak berkata dalam hati, “Betapa mengerikannya mereka menangkapi orang-orang Yahudi.” Malahan, setelah menyerap pengetahuan tentang “bahaya Yahudi”, Heck berkata, “Celaka sekali, Heinz adalah orang Yahudi.” Sebagai seorang yang dewasa, Heck menyimpulkan, “Saya menyepakati deportasi sebagai keadilan.”
Fakta bahwa komunitas para pengikut memiliki identifikasi yang sama dengan pemimpin otoriter mempunyai konsekuensi penting lainnya. Para pengikut mengidentifikasi satu sama lain sebagai bagian dari “gerakan” dan mereka mengalami diri mereka bergabung menjadi satu kesatuan kolektif. Rasa persatuan yang memabukkan ini dan penyingkiran kepentingan diri pribadi demi tujuan yang lebih besar adalah komponen yang sangat penting bagi sistem otoriter. Hal tersebut ditemukan dalam banyak retorika otoriter—seperti yang dicontohkan oleh Reich Ketiga.
Gagasan bahwa seorang individu hanya penting sebagai kendaraan perlombaan atau “Volk” dan ide tentang tugas seseorang adalah untuk roh transenden yang lebih besar telah mengalahkan kepentingan pribadi—dan itu tersebar luas di Jerman era Hitler. Anak-anak Jerman diperintahkan untuk menjaga “kemurnian” darah mereka—yaitu untuk mencegah percampuran darah antarsukubangsa atau antarras. Mereka diberitahu bahwa darah mereka bukan hanya milik mereka melainkan milik ras Jerman—sejak masa lalu, sekarang, hingga masa depan—dan dengan itu, mereka akan memiliki kehidupan yang kekal.
Berpartisipasi dalam sistem otoriter jelas mempunyai suasana religius yang berlebihan. Sebab ini melibatkan penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi dan melepaskan batas-batas ego individu—demi suatu kemurnian; yang membangkitkan misi kehidupan kekal, kelahiran kembali, dan penyelamatan. Sifat semi-religius dari kebangkitan Hitler telah dijelaskan dalam “The Dark Charisma of Adolf Hitler” (2012) oleh sejarawan Laurence Rees:
Gerombolan orang Jerman melakukan perjalanan—hampir seperti peziarah—untuk memberi penghormatan kepada Hitler di rumahnya di Berchtesgaden, ribuan petisi pribadi dikirim ke Hitler di Kekanseliran Reich, ikonografi pseudo-religius dari demonstrasi di Nuremberg, & fakta bahwa anak-anak Jerman diajari bahwa Hitler “dikirim oleh Tuhan”, “iman”, dan “cahaya” mereka; semua ini adalah fakta yang berbicara bahwa Hitler dipandang bukan sebagai seorang politisi normal dan lebih sebagai seorang nabi yang disentuh oleh yang ilahi.
Mengingat hal tersebut, akan menjadi bermanfaat dengan beralih ke monograf karya Freud; “The Future of An Illusion” (1927). Meskipun sebagian besar isinya peduli terhadapa psikologi agama, namun menjadi suatu kesalahan apabila mengabaikan konteks dan konten politiknya. Tidak ada orang Yahudi di area “Wina Merah” yang tidak bisa perihatin dengan munculnya politik anti-Semitisme pada tahun 1927 (sebagai tahun pertama dari demonstrasi Nuremberg di era Hitler). Freud mengatakan kepada pewawancaranya pada kurang dari setahun sebelumnya—yakni pada 1926:
Bahasaku Jerman. Budaya yang kuperoleh adalah Jerman. Secara intelektual, aku menganggap diriku orang Jerman sampai aku melihat tumbuhnya prasangka anti-Semit di Jerman dan Austria-Jerman. Sejak saat itu, aku lebih suka menyebut diriku seorang Yahudi.
Satu ilusi yang ia sebut dalam teks bukunya adalah pandangan bahwa “ras Jerman adalah satu-satunya ras yang mampu beradab”.
Pada saat itu, wilayah politik Austria terbagi antara kaum Sosialis Kristen sayap kanan yang memiliki laskar Heimwehr sebagai home guard & didanai oleh kaum fasis Italia dan Sosial Demokratik yang lebih condong ke Kiri dengan unit Schutzbund sebagai paramiliternya.
Tensi antara kedua kelompok tersebut meletus pada 15 Juli 1927 ketika kaum Kiri melakukan demonstrasi besar-besaran sebagai upaya permulaan menduduki Universitas Wina—yang hanya berjarak beberapa menit dengan berjalan kaki dari apartemen Freud. Demonstrasi itu berpuncak di depan Palace of Justice dengan berjalan kaki sekitar 20 menit, kemudian kerumunan demonstran menyerbu dan membakar gedungnya. Polisi menembaki para pengunjuk rasa dan tiga jam kemudian; 89 demonstran dan lima polisi terbaring mati di trotoar. Hari itu dan dua hari berikutnya dikenal sebagai schreckentage atau hari-hari menakutkan. Bagi kalangan intelektual Wina seperti Freud, ancaman politik otoriter terasa sangat dekat dengan rumah.
***
Mengikuti tradisi filsafat Jerman—seperti pemikiran Ludwig Feuerbach dan Karl Marx, Freud berpendapat bahwa kepercayaan religius adalah ilusi namun ia memiliki pandangan yang unik: yang membedakan antara “ilusi” dan “non-ilusi” bukanlah berdasarkan sesuatu itu benar atau salah; tetapi berdasarkan bagaimana hal tersebut terjadi.
Ilusi adalah kepercayaan yang kita adopsi karena kita menginginkan hal itu benar. Keyakinan semacam itu biasanya salah, tetapi kadang-kadang ternyata benar. Misalkan Anda bangun pagi untuk membeli tiket lotre dengan keyakinan yang membara bahwa Anda akan memenangkan lotre. Dan anggaplah, secara kebetulan, Anda benar-benar memenangkan lotre. Meskipun keyakinan Anda yang menganggap Anda akan menang menjadi benar, namun hal itu masih dianggap sebagai ilusi oleh Freudian.
Ilusi yang paling meyakinkan bisa memenuhi syarat sebagai delusi. Delusi adalah ilusi yang salah dan sangat resisten terhadap revisi rasional karena didorong oleh kekuatan hasrat yang sangat besar. Keyakinan religius adalah contoh utama delusi ala Freud. “Itu adalah pemenuhan keinginan umat manusia yang tertua, terkuat, dan paling mendesak. Rahasia kekuatan mereka terletak pada kekuatan hasrat ini,” ujar Freud.
Hasrat yang menopang kepercayaan religius memiliki hubungan dengan pelepasan ketidakberdayaan manusia. Kita rentan terhadap kekuatan alam; seperti penyakit, bencana alam, dan akhirnya kematian, juga terhadap tindakan manusia lain yang dapat membahayakan kita, membunuh kita, atau memperlakukan kita dengan tidak adil. Dalam mengenali ketidakberdayaan kita, Freud berpikir bahwa kita dilemparkan kembali pada prototipe kekanak-kanakan; tentang ingatan akan ketidakberdayaan yang kita alami sebagai bayi; ketergantungan kita yang sepenuhnya dan mengerikan kepada orang dewasa yang merawat kita (atau gagal merawat kita). Ia menyatakan bahwa orang-orang yang religius menghadapi perasaan tidak berdaya mereka dengan berpegang teguh pada ilusi tentang dewa pelindung yang kuat yang akan memberikan mereka kehidupan setelah kematian.
Ada hubungan jelas antara dorongan religius dan kekuatan psikologis yang berperan di ranah politik berdasarkan analisis Freud. Politik, secara eksplisit, merupakan respon terhadap kerentanan manusia. Harapan dan ketakutan kita yang paling dalam bisa menembus arena politik dan ini membuat kita menjadi rentan terhadap ilusi politik; yang sering melekat dengan kegigihan yang begitu kuat dan begitu keras kepala terhadap argumen masuk akal sehingga cocok dengan karakter delusi menurut Freud. Dari perspektif ini, sistem politik otoriter menggemakan agama monoteistik. Seperti Tuhan sendiri; pemimpin otoriter adalah sebagai yang mahatahu, mahakuasa, dan mahabaik. Kata-katanya mendefinisikan cakrawala realitas. Dia harus dipuji dan ditenangkan tetapi tidak pernah ditantang. Musuh-musuhnya bisa diartikan sebagai sekutu kekuatan jahat.
Jika agama-agama hanyalah tentang fantasi pengabul harapan, semuanya akan terasa manis dan ringan. Tapi nyatanya tidak demikian. Janji manis atas surga hanyalah bermakna jika dihadapkan dengan ancaman neraka dan keselamatan membutuhkan sesuatu yang harus diselamatkan—bahkan dengan ganjaran kesederhanaan, penderitaan, dan—dalam kasus para martir agama—penyiksaan, dan kematian. Hal yang sama juga berlaku untuk wacana politik otoriter. Dengan ini, artinya tidak semua “kue” (demokrasi) itu beracun.
***
Saya beralih ke karya psikoanalis lain yang kurang terkenal demi menganalisis sisi gelap pola pikir otoriter. Ada pula gagasan dari Roger Money-Kyrle yang berasal dari keluarga aristokrat Inggris. Dia mendaftar ke Royal Flying Corps pada usia 18 tahun demi berperang dalam Perang Dunia Pertama. Ia pun ditembak jatuh di atas Prancis utara pada tahun 1917—yang mengakhiri karier militernya. Setelah perang, ia mendaftar di Universitas Cambridge untuk belajar fisika dan matematika namun ia segera beralih ke filsafat. Seperti sejumlah pemikir Cambridge pada saat itu, Money-Kyrle menjadi tertarik pada psikoanalisis dan melakukan perjalanan ke Wina pada tahun 1922 untuk menyelesaikan PhD-nya bersama filsuf Moritz Schlick (pemimpin Lingkaran Wina) dan menjalani analisis bersama Freud. Setelah kembali ke Inggris pada tahun 1926, ia memperoleh gelar PhD yang keduanya untuk bidang antropologi dan akhirnya berpraktik menjadi seorang psikoanalis.
Tahun 1932, Money-Kyrle mengunjungi Berlin atas undangan temannya; diplomat Arthur Yencken (yang kemudian tewas akibat bom waktu yang dipasang Nazi di pesawatnya). Yencken membawanya ke rapat umum Partai Nazi; tempat Joseph Goebbels dan Hitler berbicara. Money-Kyrle terpesona sekaligus terganggu dengan apa yang dilihat dan didengarnya, serta mencoba memahami apa yang terjadi dengan cara meneliti pidato dan dinamika kerumunan melalui sudut pandang psikoanalitik. Hasil pengamatannya ini berupa artikel “The Psychology of Propaganda” (1941).
Saat ia mengunjungi Jerman, Money-Kyrle dipengaruhi sangat kuat oleh intelektual psikoanalis Inggris kelahiran Hungaria; Melanie Klein. Klein berpendapat bahwa semua manusia dihantui oleh ketakutan yang mendalam dan mengerikan—yang disebutnya “kecemasan psikotik”. Dia berpikir bahwa kecemasan ini dan tanggapan kita terhadapnya bisa mendorong manusia untuk berperilaku—secara baik maupun buruk. Dalam skema Kleinian, ada dua bentuk utama kecemasan psikotik. Kecemasan paranoid merupakan kecemasan karena dianiaya oleh teror kejahatan dan kekuatan abadi. Sementara kecemasan depresif, adalah perasaan seseorang yang bersalah karena telah menghancurkan nilai-nilai dan sesuatu dicintai manusia. Klein juga menggambarkan apa yang disebutnya sebagai “pertahanan manik”; yang merupakan penolakan ketidakberdayaan dan ketergantungan pada orang lain berdasarkan delusi kekuasaan, keagungan, dan kemandirian yang diekspresikan melalui sikap kemenangan, kontrol, dan penghinaan.
Money-Kyrle menggunakan kerangka kerja Klein untuk memahami kekuatan retorika Nazi. Dia menyimpulkan bahwa Hitler dan Goebbels menginduksi sesuatu seperti psikosis massa di antara audiens mereka dan membentuknya untuk tujuan politik. Dia pun menulis:
Dia mengatakan bahwa mereka tidak terlalu mengesankan. Tapi kerumunan itu tak bisa dilupakan. Orang-orang tampaknya kehilangan individualitas mereka secara bertahap dan menyatu menjadi monster yang tidak terlalu cerdas tetapi sangat kuat yang berada di bawah kendali penuh oleh sosok di mimbar yang membangkitkan atau mengubah gairah mereka menjadi beberapa organ raksasa dengan mudahnya.
Mengamati aksi Hitler dan Goebbels, mengantarkan Money-Kyrle pada gagasan bahwa: agar propaganda politik berhasil, para propagandis harus memperoleh perasaan tidak berdaya di antara para pendengarnya (sebagai “racun”) dan kemudian menawarkan mereka solusi ajaib (sebagai “kue”). Pertama, mereka membuat pemirsanya tertekan; untuk membuat mereka merasa telah kehilangan atau menghancurkan sesuatu yang sangat baik dan berharga. Sehingga mereka pun berlutut dan menjadi bahan olok-olokan. Mereka juga merasa telah mengkhianati nasib besar rakyat Jerman. Seperti halnya yang digambarkan oleh Money-Kyrle, “Selama 10 menit, kami mendengar tentang penderitaan Jerman sejak perang. Monster itu sepertinya menikmati pesta mengasihani diri sendiri.”
Langkah kedua adalah dengan mengidentifikasi beberapa minoritas atau kelompok orang luar sebagai pelaku penderitaan seseorang. Mereka dianggap sebagai “kekuatan jahat” yang menganiaya kita dari luar atau menghabisi kita dari dalam. Money-Kyrle menulis hal demikian:
Kemudian selama 10 menit berikutnya, muncullah kemarahan paling hebat terhadap orang-orang Yahudi dan Sosial-Demokrat sebagai penyebab satu-satunya penderitaan mereka. Mengasihani diri sendiri memberikan tempat pada kebencian; dan monster itu tampaknya akan menjadi pembunuh.
Langkah ketiga adalah dengan menawarkan penyembuhan manik atas teror ketidakberdayaan:
Belas kasihan terhadap diri sendiri dan kebencian saja tak cukup. Mengusir rasa takut juga diperlukan. Karenanya, pembicara beralih dari penghinaan ke pujian diri. Dari permulaan yang kecil, Partai telah menjadi tak terkalahkan. Setiap pendengar merasakan bagian dari kemahakuasaannya dalam dirinya & dipindahkan ke psikosis baru. Melankolia yang diinduksi masuk ke paranoia dan paranoia menjadi megalomania.
Puncak terkahirnya ialah fase manik dari performa Hitler yang merupakan daya tarik bagi persatuan; yang menurut Money-Kyrle sangat penting bagi keberhasilan propaganda otoriter. Karena jika ia tidak memiliki tawaran menggelegar apapun, ia hampir tak bisa ditetapkan sebagai dewa. Menggaungkan kekuatan semacam ini, maka nada-nada positif disuarakan; Hitler pun menjanjikan surga di muka Bumi. Surga ini, bagaimanapun, hanya untuk orang Jerman sejati dan Nazi sejati. Semua orang di luar itu tetaplah dianggap penjahat dan karenanya menjadi obyek kebencian.
Meskipun terinspirasi dari pengamatannya terhadap retorika Nazi, Money-Kyrle tidak memaksudkan bahwa analisisnya hanya berlaku untuk kasus Nazi. Pada tahun 2016 menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat, jurnalis Gwynn Guilford menghadiri beberapa demonstrasi Donald Trump dan dia menggunakan catatan pengamatannya untuk menguji tesis Money-Kyrle. Dia melaporkan dalam sebuah artikel menarik yang diterbitkan di majalah online Quartz, “Saya telah menghabiskan banyak rim untuk hasil pengamatan yang saya tulis ketika saya meneliti unjuk rasa Trump. Hampir setiap paragraf sesuai dengan urutan metode Money-Kyrle.”
Apakah diagnosa psikoanalitik terhadap daya tarik para pemimpin seperti itu bisa benar? Untuk itu, diperlukan beberapa analisis psikologis yang bersumber dari hasrat para pemimpin otoriter. Dengan memahami daya tarik ilusi otoriter, kita dapat terbantu untuk melawannya. Pula dengan demikian, kita sekali lagi bisa terhindar dari pembawaan menuju ke jurang (penderitaan) yang dalam.
12 Februari 2018
–
[Pengalihbahasa: Taufik Nurhidayat. Terlalu malas untuk berlaku tirani.]