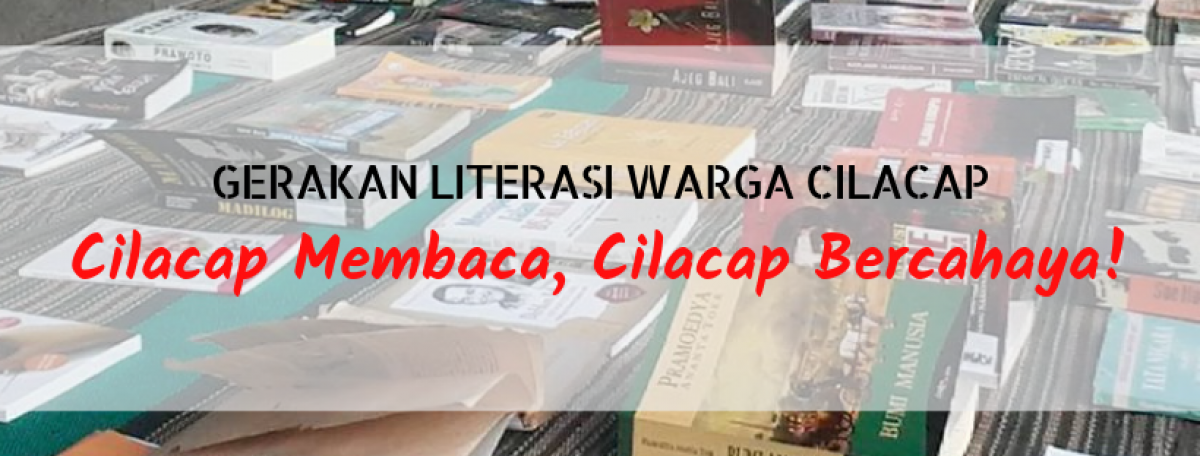___
*)Ditulis oleh Toto Priyono. Esais peminat sosio-humaniora, bermukim di Cilacap.
–
Seperti kehilangan satu bab dalam kehidupan. Memang di saat manusia memaknai sebuah rasa pada setiap bentuk kehidupannya, ia bukan hanya akan menjadi sepucuk kepentingan tetapi menjadi hal-hal yang tentunya meyakinkan. Bahwasannya kehidupan ini tetap akan menunjukkan bagaimana manusia akan menjalani hidup yang pada dasarnya ia tidak dapat bertumpu pada orang lain; melainkan ia harus menjalani hidup ini dari dan untuk dirinya sendiri.
Setiap bentuk kekhawatiran dari hidup, ia tidak akan berarti di kala perut-perut manusia itu sendiri mulai lapar. Panas, hujan, ataupun badai menghadap manusia sekalipun, yang dalam ruang hidupnya sendiri telah menjadi teman tidak dapat ditinggalkan. Namun manusia dalam wacana pemikirannya, apa yang merugikan haruslah dihindari.
Tetapi kenyataan hidup itu merupakan buah-buah dari sisi kontradiktif yang harus diterima oleh manusia. Karena kebutuhan untuk makan sendiri lebih wajib daripada setiap hari ia, manusia, harus ibadah menatap surga. Sebab tanpa perut merasa kenyang, surga adalah janji yang bohong dikhayalkan oleh manusia. Bahkan dalam situasi di mana mencari makan disandingkan dengan potensi terkena penyakit melalui virus corona atau COVID-19, misalnya, atau dengan ancaman-ancaman penyakit lain.
Apakah benar manusia akan menurut pada ketakutannya akan penyakit itu jika kepentingan akan kebutuhan makannya sendiri tidak terpenuhi? Seringkali, saat pikiran ditaburi berbagai informasi ragam ketakutan, keganasan, atau dengan doktrin-doktrin yang mereka terima tentang kehidupan sengsara menjadi manusia, adalah wadah sebuah kekhawatiran.
Tentang bagaimana pikiran itu mempengaruhi, dalam satu titik, pikiran manusia mampu melampaui ketakutan untuk menjadi sebuah keberanian. Karena tentu permainan pikiran merupakan salah satu kelemahan manusia di balik gagahnya sifat alamiahnya menaklukan alam dengan berbagai ancaman yang akan diterima. Di sini jelas, alam dan interpretasi keganasannya seringkali mengancam. Namun perkara ancaman itu, bukankah kehendak manusia hanya untuk bertahan hidup di dunia—di mana salah satu cara yang tidak dapat ditinggalkan adalah kebutuhan untuk makan?
Oleh sebab itu, seberapa pun takut pikiran manusia mempengaruhi kehidupannya, ketakutan paling nyata adalah bagaimana ia sendiri tidak dapat makan; sebab di sana, manusia tidak dapat melanjutkan kehidupan. Maka ancaman apa pun, tidak akan pernah mempan dalam pikiran jika manusia memang belum tercukupi kebutuhannya untuk makan.
Kebutuhan makan merupakan distrosi dari pikiran, karena seberapa hebat pemikiran, ia tidak akan pernah jalan ketika perut manusia belum merasa kenyang. Ketakutan apa pun yang timbul dalam semesta wacana pemikiranya memalui media keterpengaruhan sebenarnya ia hanya mempengaruhi perut-perut manusia yang sudah kenyang dan hidup tanpa kekhawatiran. Maka kabar yang setiap hari berhembus di media sana merupakan alat untuk menyasar orang-orang yang sudah kenyang perutnya tersebut untuk mempengaruhi pikirannya, lalu ia akan mempengaruhi manusia-manusia lain di sekitarnya. Sebagai argumen sendiri, apakah dengan berbagai isu ketakutan masyarakat dunia akan virus COVID-19 ini mempengaruhi manusia-manusia yang lapar butuh makan?
Tentu tidak demikian. Seseorang yang lapar dan tidak punya apa-apa lagi untuk memenuhi kebutuhan makannya seperti uang atau bahan makanan. Manusia akan berontak mencarinya meskipun dengan rasa ketakutan untuk melawan pikirannya sendiri—begitupula dengan negara di mana mereka takut dan melakukan karantina wilayahnya. Mereka adalah negara-negara lapar yang takut dan khawatir tidak dapat makan atau berjalan hidup di hari depan; yang dalam semesta wacananya sendiri tetap yang dipikirkan adalah ekonomi. Sebab jika negara bangkrut secara ekonomi, orang-orang yang ada di dalam negara sendiri justru sebenarnya takut mati kelaparan.
Indonesia Juga Negara Lapar
COVID-19 dan ungkapan karantina wilayah merupakan satu dari berbagai kata ketakutan pikiran masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Dalam wacananya sendiri, media di indonesia sangat gencar memberitakan kasus COVID-19 dengan narasi ketakutan. Tetapi dari sekian banyak pengonsumsi kuat media adalah kelas menengah yang mapan secara ekonomi; memungkinkan perut mereka dapat tetap kenyang walaupun jika selama setahun ini isu virus corona atau COVID-19 tetap berlaku.
Berbeda dengan kelas bawah—yang secara ekonomi sendiri untuk kebutuhan makan sangat rentan, mana peduli mereka terhadap media atau tentang omongan tetangga. Bahkan omongan para birokrat sendiri yang menganjurkan tetap di rumah atau tidak mudik untuk warga perantauan ke kampung halaman karena takut menularkan virus COVID-19. Untuk itu, mungkinkah anjuran-anjuran dalam bentuk pesan sendiri tanpa tindakan yang terasa akan benar-benar dilaksanakan?
Tentu ini bukanlah pilihan yang baik dan bijaksana bagi para perantau dengan adanya isu-isu terhadap penularan COVID-19 yang melumpuhkan ekonomi kota; yang penduduknya didominasi kelas menengah-atas. Jika ekonomi lumpuh dan perantau hanyalah menghuni pos kelas bawah rentan secara ekonomi di perantauan—yang bergantung pada aktivitas ekonomi kota dan aktivitas itu lumpuh, bagaimana mereka akan bertahan hidup di kota? Mungkinkah manusia akan makan aspal dan beton-beton di kota?
Warga kelas bawah kota yang didominasi pengungsi ekonomi dari desa tentu juga sama; masih manusia yang tidak takut apa pun meskipun pikirannya terpengaruh ketakutan akan informasi di media terkait dengan virus COVID-19 itu ketika perutnya sendiri lapar dan takut akan kelaparan di masa yang akan datang dengan tetap nekat mudik ke desa. Ketika di desa, para pengungsi ekonomi di kota masih dapat makan. Karena dalam kondisi krisis, desa lebih tahan secara ekonomi daripada perkotaan sebab pertanian masih dapat berjalan; memungkinkan manusia masih dapat makan.
Maka wacana hanya sampai kepada wacana kembali. Mungkin gembor-gembor stay at home atau work form home hanya berlaku untuk para karyawan kerah putih (kantoran) atau keluarga kalangan menengah ke atas yang tidak rentan secara ekonomi. Berbeda dengan karyawan rendahan (pekerja kasar) atau buruh-buruh rendahan yang dibayar sesuai pekerjaan.
Meskipun anjuran dari birokrat negara dan elit negara untuk menjaga diri supaya tidak terpapar virus COVID-19 dengan tetap di rumah atau kerja dari rumah, hanyalah status saja seolah-olah negara melalui pemerintah memberi perhatian terhadap warganya. Namun dalam pelaksanaanya sendiri, birokrat—dalam hal ini orang-orang dalam pemerintahan negara—yang secara ekonomi berstatus menengah ke atas dan menumpang hidup dari keberadaan negara juga sebenarnya takut jika negara melakukan karantina wilayah. Mereka takut negara bangkrut dengan mematuhi undang-undang negara yang harus memberi makan masyarakat selama karantina wilayah. Oleh sebab itu, istilah “Negara Indonesia juga lapar” sebenarnya bukan negaranya yang miskin tetapi para birokrat yang takut miskin ketika negara bangkrut.
Mungkin inilah sebab mereka melakukan kebijakan terkait kesehatan masyarakat dalam hal pencegahan virus COVID-19 cenderung kontradiktif. Mereka menginginkan kebijakan karantina wilayah dengan tetap di rumah atau kerja dari rumah namun lepas tanggungjawab; tidak mau menanggung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan dasarnya, yakni kebutuhan makan.
Negara Indonesia yang lapar ini melakukan kebijakan yang arahnya tetap pada tujuan ekonomi supaya tidak bangkrut. Maka dari itu, kebijakan termasuk penggelontoran dana beratus-ratus triliyun dalam pencegahan virus COVID-19 sendiri merupakan kebijakan yang tidak ramah penanganan COVID-19 untuk kesehatan masyarakat.
Penghapusan biaya listrik sendiri selama masa darurat bencana COVID-19 bukanlah solusi tepat karena di masa selanjutnya harganya listrik sendiri dapat dimonopoli negara. Bisa terjadi, ketika sudah tidak darurat bencana, harga listrik dinaikkan; mengamankan lagi uang negara. Pada akhirnya, masyarakat-masyarakat juga yang terkena imbasnya nanti. Atau dengan program-program pemerintah melalui Keluarga Harapan, Kartu Pra Kerja, dan sebagainya—yang dapat angin segar tambahan anggaran, bukankah itu program rutin pemerintah; bukan upaya penanganan kesehatan masyarakat terkait kesehatan? Upaya apa yang dilakukan pemerintah Negara Indonesia tidak lebihnya hanyalah politik etis dalam penanganan virus COVID-19?
Di sisi lain, ketika proyek-proyek pemerintah seperti pekerjaan umum di jalan raya dengan pembuatan saluran air masih berjalan, anehnya birokrat berjalan-jalan keliling di jalan-jalan raya nasional dengan menyemprot cairan disinfektan. Bukankah jika kesehatan masyarakat nomor satu, maka proyek-proyek tersebut diberhentikan dahulu; sebab dalam pengerjaannya sendiri merupakan elemen masyarakat yang bekerja dan mereka juga butuh kesehatan?
Negara yang para birokratnya lapar akan selalu lamban dalam penyelesaian masalah, baik bencana atau apa pun yang melibatkan anggaran negara. Maka tidak heran, di saat negara lain bereaksi atas pandemi virus COVID-19 mementingkan kesehatan masyarakat, Indonesia sendiri justru mementingkan ekonomi dan membuat kebijakan yang justru tidak ramah kesehatan masyarakat. Membuat aturan dan himbauan ini dan itu tetapi hanya omong tanpa tindakan sesuatu yang berarti. Seperti janggalnya keputusan yang dapat berubah setiap jam yang tadinya tidak dihimbau mudik, kini berubah menjadi diperbolehkan demi untuk terjaganya iklim ekonomi negara Indonesia.
COVID-19 adalah tentang sebuah kejengahan aturan dan himbauan maupun gemboran media abal-abal yang ingin hidup dengan isu—karena terpenting ada konsumsi dan ekonomi untuk media tersebut jalan. Pada dasarnya, Pemerintah Indonesia yang lapar tidak pernah serius untuk penanganan kesehatan masyarakat. Umumnya negara lapar, ia butuh makan, makan, dan makan. Siapakah yang kurang makan tersebut dan tidak pernah kenyang, adalah orang-orang yang ada dalam pemerintahan negara.
Di saat masyarakat butuh sehat, negara melalui pemerintahannya justru lamban dalam mengambil kebijakan, bahkan membuat kebijakan tetap tidak pro-rakyat (masyarakat). Maka selamanya, negara juga termasuk penjajah yang mementingkan dirinya; bukan rakyatnya sebagai prioritas utama; membuat kebijakan justru lebih menguntungkan banyak gelintir orang yang ada di dalamnya.