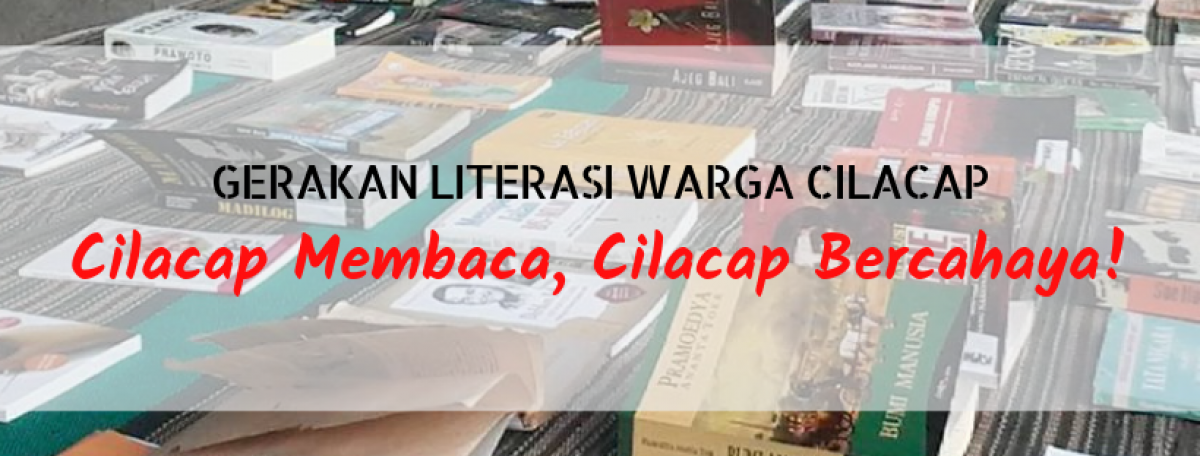–
*)Ditulis oleh Florian Schui. Sejarawan di Royal Holloway, Universitas London. Telah menulis buku Austerity: The Great Failure pada 2014.
–
Orang-orang Barat terus-menerus mengkhawatirkan konsumsi yang berlebihan dan hidup yang terlalu baik. Ini bukanlah masalah baru. Paling tidak, selama 2000 tahun terakhir, kita khawatir karena harus membayar biaya-biaya kemakmuran. Yang mungkin lebih mengejutkan ialah kita akan terus-menerus merasa khawatir.
Selama ribuan tahun pertama keberadaan manusia, peningkatan konsumsi berjalan sangat lambat. Namun selama 200 tahun terakhir ini, industrialisasi menyebabkan peningkatan kemakmuran masyarakat Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara super, peningkatan kemakmuran terjadi terakhir kali pada era 1950-an dan 1960-an. Akan tetapi, kita masih belum memperoleh timbal-baliknya. Sebaliknya, kebanyakan orang Barat merasa bahwa hasil utama peningkatan kemakmuran tersebut adalah hidup yang terasa lebih langgeng dan lebih nyaman.
Ada pernyataan bahwa masalah sosial-ekonomi yang paling mendesak di zaman kita ialah sangat tidak meratanya distribusi manfaat kemakmuran yang menumbuhkan ketidaksetaraan. Ketimpangan terasa paling kuat dalam hal konsumsi. Menariknya, hal ini bukan disebabkan oleh konsumsi berlebihan pada kalangan atas, melainkan karena meningkatnya kekurangan di kalangan bawah.
Jika kita ingin memperbaiki ketidakseimbangan ini melalui redistribusi, kita perlu menyadari bahwa hal ini akan meningkatkan substansi konsumsi keseluruhan yang selanjutnya tak bisa dihindari. Peningkatan substansi ini mungkin bukan hal buruk sebab para pembuat kebijakan selalu berusaha memahami tradisi panjang mengkritik konsumsi yang hampir setua peradaban Barat.
Kritik konsumsi tertua dan paling berpengaruh mungkin muncul dalam tradisi Yahudi-Kristen. Penghancuran wilayah Sodom dan Gomora dipahami secara umum sebagai hukuman ilahi atas kebejatan seksual. Namun seperti yang ditunjukkan oleh Stephen Long—teolog Amerika—melalui “Christian Ethics” (2010); dosa-dosa yang dilakukan di kedua kota itu “lebih berkaitan dengan ekonomi daripada homoseksualitas”. Karena terobsesi kemewahan, orang-orang Gomora menjadi gagal menunjukkan keramahan dan kasih tanpa pamrih yang dikehendaki Tuhan kepada mereka.
Hubungan antara dosa dan keserakahan materi dimunculkan kembali dalam pembahasan Perjanjian Baru. Dengan menggunakan perumpamaan yang aneh, Yesus memperingatkan bahwa orang kaya akan menghadapi kesulitan dalam perjalanannya menuju ke Firdaus yang sama halnya seperti unta yang mencoba melewati lubang jarum. Dia menyarankan caranya mencapai surga adalah dengan mengurangi konsumsi secara radikal; yakni dengan memberikan semua harta benda.
Versi duniawi dari argumen semacam di atas—yang tidak bergantung pada kepercayaan kepada Tuhan atau kehidupan setelah kematian—diusulkan oleh Jean-Jacques Rousseau pada abad ke-18. Rousseau menyuarakan keprihatinannya terhadap latar belakang revolusi konsumen yang terjadi pada masanya. Dalam karyanya “Discourse on the Moral Effects of the Arts and Sciences” (1750); ia menyesalkan kepemilikan dan penampilan yang menjadi motif utama tindakan manusia dalam tatanan komersial; sementara sentimen dan keyakinan sejati telah menjadi motif kedua. Sebaliknya, yang menjadi perhitungan adalah perbuatan yang membantu seseorang naik ke tonggak kekayaan dan prestise secara licin. Maka, hasilnya adalah korupsi moral; sehingga pria dan wanita hidup dengan cara-cara yang palsu demi orang lain dan melalui orang lain.
David Hume dan para pemaklum masyarakat komersial abad ke-18 lainnya juga mengakui bahwa ketertarikan terhadap konsumsi menghentikan banyak ekspresi perasaan dan dorongan hati manusia yang tulus. Tetapi mereka juga menyarankan bahwa hal ini tidak perlu menjadi perusak. Sistem baru ini membantu menyalurkan perilaku manusia yang sesuai dengan cara-cara berdampingan yang damai. Pria dan wanita yang terbentuk dalam semangat masyarakat komersial mungkin mendambakan kepemilikan yang bergemerlapan dari orang lain. Akan tetapi, daripada mengikuti dorongan sejati mereka dan memperolehnya secara paksa; mereka akan melakukann kerja keras demi membeli obyek-obyek hasrat ini sendiri atau mencari orang kaya untuk bersenang-senang dalam gemerlapan konsumsinya. Dalam masyarakat komersial, sentimen yang sejati sering diabaikan. Tapi ada juga orang yang lebih sedikit menahan nafsu seperti era sebelumnya yang lebih sejati.
Secara teori, hal tersebut merupakan kebangkitan kembali yang kuat. Namun argumen tersebut didasarkan pada pandangan negatif yang berlebihan mengenai apa yang disebut sebagai “zaman kegelapan” sebelum munculnya perdagangan yang mencerahkan. Dan efek pemberadaban perdagangan segera diliputi keraguan lagi oleh penyebaran kolonialisme, perbudakan, dan pemusnahan massal kaum pekerja—ketika Eropa menyebarkan tentakelnya ke seluruh dunia. Karenanya, pemikiran Rousseau tidak dapat disepelekan secara mudah.
Saat industrialisasi berkembang, muncullah untaian kritik baru terhadap konsumsi. Pada 1798, dengan menggunakan matematika dasar; Thomas Malthus berpendapat bahwa konsumsi tanpa batas akan menghukum umat manusia untuk hidup dalam kesengsaraan. Jika populasi menyebabkan konsumsi tumbuh secara eksponensial, sementara sumber daya—yang terpenting seperti lahan subur—jumlahnya terbatas, maka akan tercapainya titik kehancuran sistem yang tak terhindarkan. Menurut Malthus, kelaparan akan mengurangi jumlah populasi secara berkala, namun nafsu seksual yang tak terpuaskan dari kelas bawah (yang diartikan sebagai massa) tidak akan pernah bisa naik ke atas tingkat taraf hidup yang paling menyedihkan.
Kalkulasinya Malthus tampak tak terbantahkan namun ramalannya tak menjadi kenyataan. Kemiskinan masih menjadi masalah di Barat tapi hampir tiada yang hidup dalam kesengsaraan yang diprediksinya dan oleh karenanya kita bisa berterimakasih atas kemajuan teknologi. Teknologi memungkinkan manusia menyerah pada dorongan seksualnya tanpa menghasilkan anak (semacam konsumsi tanpa konsekuensi). Kemajuan ilmu pengetahuan juga mengisyaratkan bahwa sumber daya yang ada dapat digunakan lebih efisien dan sumber daya baru bisa disadap. Hasil pertanian telah tumbuh secara dramatis sejak zamannya Malthus hidup dan kita hari ini menggunakan sumber energi dan persediaan lain yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang sezamannya. Prediksi spesifiknya Malthus ternyata salah tetapi logikanya yang mendasari skenario malapetaka semacam itu terus menghantui imajinasi orang-orang Barat.
***
Sebagai akibat Perang Dunia Kedua, revolusi konsumsi kedua membawa kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya pada orang-orang Barat. Televisi, lemari es, mobil, dan perjalanan udara menjadi barang konsumsi umum yang pada gilirannya menyebabkan reaksi kritis baru pada akhir 1960-an.
Club of Rome; sebuah think tank global yang baru dibuat pada 1972, mengerjakan sebuah laporan yang diterbitkan dengan judul “The Limits to Growth” yang melahirkan kebangkitan pengaruh ide-ide Malthus. Para penulisnya berpendapat bahwa pertumbuhan populasi dan perluasan konsumsi yang salinng berkaitan akan menyebabkan menipisnya sumber daya, polusi yang berlebihan, dan—pada akhirnya—kehancuran lingkungan. Laporan tersebut membentuk kesadaran publik dan memberikan kontribusi berpengaruh terhadap kebangkitan gerakan Politik Hijau pada masa ini.
Tahun 2012, Jørgen Randers; futurolog Norwegia yang ikut menulis dalam “The Limits to Growth”, menyajikan serangkaian prediksi suram untuk 2052. Argumen dasarnya tetap tak berubah; bahwa populasi dan konsumsi semakin tumbuh, peningkatan konsumsi energi dan emisi menyebabkan perubahan iklim; yang menuntut biaya ekonomi yang besar, dan menyebabkan kerusakan lingkungan; yang pada akhirnya menjadikan kehidupan di bumi menjadi tak berkelanjutan.
Kritik sosial-psikologis Rousseau mengenai konsumsi kembali terlihat pada era 1970-an. Melalui karya seminalinya “To Have or To Be?” (1976), Erich Fromm; psikoanalis Jerman, menawarkan sebuah pilihan nyata kepada para pembacanya; antara kehidupan yang terpenuhi dengan memperoleh kepuasan dari hidup itu sendiri atau eksistensi palsu yang berputar di sekitar kepemilikan materi. Prinsip yang pertama adalah tentang berkolaborasi dan hidup berdampingan yang saling bersahabat antarsesama pria dan wanita. Lalu prinsip berikutnya adalah suatu kompetisi agresif yang berputar pada sekitaran cara menipu konsumen, menghancurkan pesaing, dan mengeksploitasi para pekerja. Meskipun perolehan materi seolah-olah terpenuhi, keinginan material kita yang tak dibatasi membuat kita fokus pada kepemilikan selamanya yang justru menahan pemenuhan itu sendiri.
Pemikiran yang lebih kekinian dari tradisi kritik konsumsi ini adalah kritik politik konsumsi yang ditawarkan oleh filsuf Slovenia; Slavoj Žižek dan kritikus lainnya. Žižek berfokus pada upaya konsumen untuk berbuat baik dengan membeli yang “benar”. Khususnya, ia mengkritik konsumsi makanan organik dan produk-produk yang diperdagangkan secara wajar—yang diharapkan membawa manfaat bagi konsumen, produsen, dan masyarakat pada umumnya. Ia berargumen jika semua orang membuat keputusan yang tepat di supermarket, dunia yang lebih baik dapat diciptakan. Namun kenyataannya, pilihan konsumen selalu terbatas dan juga dikondisikan oleh struktur politik-ekonomi yang hanya bisa diubah melalui aksi politik kolektif. Bagi Žižek, kepercayaan akan kedaulatan konsumen adalah naif dan akhirnya menjadi faktor perusak karena mengalihkan kita dari aktivisme politik yang nyata. Atau dengan menggunakan pernyataan Fromm: keasyikan dengan apa yang dimiliki akan membuat kita tidak menghadapi pertanyaan tentang siapa yang kita kehendaki sebagai individu dan sebagai masyarakat.
Meskipun secara intelektual menarik, sebagian besar dari berbagai kritik ini telah ditenggelamkan oleh keberhasilan ekonomi kapitalisme industri. Seperti yang pertama kali dikatakan filsuf Belanda; Bernard Mandeville dalam “The Fable of the Bees: Or, Private Vices, Public Benefits” (1714), konsumsi memang mungkin tak bermoral tapi juga merupakan bahan bakar yang mendorong perdagangan dan membawa kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Voltaire dan tokoh-tokoh penting Zaman Pencerahan lainnya segera mempertahankan argumen ini. Sehingga sejak saat itu, argumen yang berusaha menyeimbangkan antara manfaat publik atas konsumsi dan keserakahan pribadi ini bisa membuat peredaran uang bisa dinikmati. Berlawanan dengan latar belakang krisis ekonomi saat ini, argumen semacam itu berpengaruh sangat kuat pada zamannya. Apabila rute menuju pemulihan dan kesetaraan yang lebih besar membutuhkan lebih banyak konsumsi, tentunya akan banyak komentator yang cenderung mengabaikan keterlibatan moral dan lingkungan. Selain itu, ada indikasi kuat bahwa peningkatan konsumsi mungkin menjadi jalan keluar dari krisis ekonomi saat ini.
***
Semakin jelas bahwa permintaan konsumen yang lemah memainkan peran dalam menyebabkan krisis keuangan baru-baru ini dan sekarang memperpanjang kemacetan ekonomi. Segera setelah krisis pada 2008, ada beberapa upaya untuk mencegah krisis kembali dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Bank dan lembaga keuangan lainnya diselamatkan dan paket stimulus dirancang untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi. Namun ketika jumlah hutang meningkat dan pertumbuhan anjlok, maka kebijakan ekonomi berubah. Ekonom terkemuka seperti Carmen Reinhart dan Kenneth Rogoff—keduanya profesor di Harvard—menyarankan bahwa pertumbuhan akan dihasilkan dari pembatasan hutang. Pada saat yang sama, aliran lama Hayekian (pelopor neoliberalisme)—yang memangkas peran negara—akan membebaskan kekuatan ekonomi sektor swasta dan membuat kemunculannya kembali menguat. Dalam pidatonya pada 2013, Perdana Menteri Inggris; David Cameron, menghimbau agar melakukan “more with less” (lebih banyak mengurangi). Pernyataannya ini pun menjadi pepatah penghematan para politisi dan anggaran pemerintahan menjadi berkurang. Pantangan kolektif juga diberlakukan pada seluruh masyarakat dengan harapan bahwa ini akan menyelesaikan krisis keuangan dan ekonomi negara-negara Barat.
Enam tahun setelah krisis, kebijakan tersebut terus berlanjut namun gagal memberikan hasil positif. Di sebagian besar negara Barat, tingkat hutang belum menurun secara signifikan dan pertumbuhan masih lemah. Akibatnya, alasan ekonomi di balik politik abstinensi (penghematan) semakin dipertanyakan. Titik baliknya ditandai oleh pidato Larry Summers; ekonom Amerika Serikat, di Forum Ekonomi-International Monetary Fund 2013. Seorang profesor ekonomi Harvard sekaligus mantan Menteri Keuangan era Bill Clinton dan penasihat ekonomi Presiden Barack Obama ini mengatakan bahwa ekonomi Barat mungkin telah memasuki periode “stagnansi sekuler” dalam sambutannya.
Pengistilahan “stagnansi sekuler” memang signifikan. Istilah yang diciptakan Alvin Hansen; ekonom Amerika Serikat, pada 1930-an ini digunakan untuk menjelaskan penyebab Depresi Hebat (Great Malaise). Mengikuti gagasan John Maynard Keynes; pelopor gagasan walfare state, Hansen melihat kurangnya konsumsi sebagai penyebab utama krisis. Dia berpendapat bahwa krisis jenis ini merupakan efek dari berlebihnya penghematan tabungan dibanding berinvestasi. Sebagai persoalan akuntansi nasional, ketidakseimbangan seperti ini membikin depresi ekonomi karena tabungan musti sama besarnya dengan investasi. Jika investasi terlalu sedikit sebagai jalan keluarnya semua tabungan, maka dengan mengurangi tabungan akan mengembalikan keseimbangan; sebab selain dengan kontrak ekonomi, mengatasi jatuhnya pendapatan negara adalah dengan mengakali tabungan. Sekali lagi, meskipun antara tabungan dan investasi sekarang sudah selaras, kesempatan lapangan kerja dan operasi ekonomi pada tataran output masih lebih rendah. Jika permintaan konsumsi tidak meningkat, ekonomi bisa menjadi merana dengan tingkat pertumbuhan dan kesempatan kerja yang rendah dalam jangka waktu lama.
Seperti yang disarankan Summers, periode stagnansi ekonomi berkepanjangan yang kita alami saat ini mungkin juga disebabkan oleh lemahnya permintaan konsumen. Konsumen saat ini merasakan ketidakamanan ekonomi dan menahan pengeluarannya atau mereka sedang mencoba melunasi hutangnya—jika memang berhutang.
Ada juga tren jangka panjang yang menurunkan permintaan konsumen. Seperti halnya, meningkatnya ketimpangan pendapatan yang mustinya menjadi hal paling penting untuk disoroti. Orang dengan pendapatan tinggi cenderung menabung lebih banyak daripada orang berpenghasilan rendah. Jika mereka menabung terus secara lebih pesat, permintaan konsumen akan menurun. Sampai batas tertentu, hal ini akan berlawanan dengan intuisi sebab kita cenderung menganggap orang kaya sebagai pembelanja besar. Mereka sering berbelanja namun juga menabung dengan jumlah yang jauh lebih besar dari bagiian pendapatannya. Kasus ini diamati dengan baik oleh Centre for Economics and Business Research, London, yang penelitiannya mengenai pola tabungan dan konsumsi di Inggris baru-baru ini menunjukkan bahwa 20% penerima penghasilan teratas mampu menghemat hampir 20000 poundsterling selama 12 bulan terakhir. Pada periode yang sama, 40% penerima penghasilan lebih rendah menghabiskan lebih banyak pendapatannya.
Tren penting berjangka panjang lainnya yang turut menekan konsumsi ialah melambatnya pertumbuhan populasi di banyak negara Barat—yang berarti semakin sedikitnya konsumen yang membutuhkan mobil, rumah, energi, dan makanan.
***
Jika kesulitan kita saat ini memanglah krisis akibat kurangnya konsumsi, maka peningkatan konsumsi harus menjadi perhatian utama kebijakan ekonomi. Kredit murah sering berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi tujuan ini. Namun saat ini, bahkan dengan tingkat suku bunga yang rendah secara historis, konsumen swasta benar-benar berhati-hati mengambil kredit setelah hutang yang tak terkendali menjadi biang keladi kebangkrutan pada akhir-akhir ini.
Tentu saja, pemerintah dapat ikut serta dalam program-program belanja publik secara kredit. Akan tetapi, hal ini hanya bisa menjadi solusi jangka pendek. Cara lebih baik untuk meningkatkan konsumsi dalam jangka panjang-berkelanjutan adalah dengan redistribusi. Jika orang-orang berpenghasilan rendah (dengan simpanan rendah) secara bersamaan menaikkan tingkat konsumsinya lebih cepat daripada mereka yang berpenghasilan tinggi, ini akan sangat memperkuat daya konsumsi. Nyatanya, permasalahan ketidaksetaraan sosial dan stagnansi sekuler ekonomi mempunyai solusi yang sama.
Pastinya, semua solusi seperti di atas tidak membantu kita mengatasi masalah moral dan lingkungan yang menjadi konsentrasi kritik terhadap konsumsi. Persoalan demikian memberikan dilema klasik untuk kita: apakah kita akan meningkatkan konsumsi sambil menerima penurunan moral dan kerusakan lingkungan sebagai imbalan atas kemakmuran dan kesetaraan? Atau kita musti menerima kemunduran ekonomi demi menyelamatkan jiwa kita dan planet ini?
Pilihan dramatis seperti itu membuat kita berimajinasi. Tapi dalam praktiknya, pilihan-pilihan yang ada mungkin tidak terlalu ekstrem. Pengamatan akut Rousseau dan Fromm tentang prospek keberadaan manusia dalam kapitalisme hanyalah kritik terhadap konsumsi jika kita membuat kesalahan dengan menyamakan konsumsi sebagai belanja. Pada zaman Rousseau, ini adalah persamaan yang adil karena sebagian besar konsumsi melibatkan individu yang memperoleh obyek atau layanan material. Tetapi jika kita melihat periode yang lebih baru, sebagian besar dari apa yang kita konsumsi tidak diperoleh secara individual. Pendidikan, perawatan kesehatan, dan keamanan merupakan bagian yang sangat besar dari apa yang dikonsumsi orang Barat saat ini dan kita melakukannya secara kolektif melalui pemerintah atau organisasi lainnya.
Perubahan persoalan pola konsumsi ini dikarenakan efek yang merusak dari kehidupan kompetitif yang berpusat pada kepemilikan materi yang tidak berkaitan dengan bentuk konsumsi kolektif. Setahun berpendidikan di sekolah negeri, seorang murid memperoleh smartphone baru keduanya sebagai bentuk konsumsi dengan harga yang jauh lebih murah daripada smartphone pertamanya. Namun saat melihat bagaimana cara seorang temannya bersekolah, malah tidak mungkin membuatnya iri. Sementara saat seorang temannya di Facebook membual tentang ponsel baru, mungkin bisa memicunya melakukan perlombaan konsumsi sehingga membuatnya memiliki ponsel yang lebih baik tetapi jiwanya menjadi lebih miskin.
Secara historis, bentuk konsumsi kolektif juga memainkan peran penting dalam membuat masyarakat menjadi lebih egaliter. Sebagian besar redistribusi yang mengatasi tingkat ketimpangan era Victoria membentuk perluasan layanan publik yang digunakan secara tidak proporsional oleh orang miskin dan didanai secara tidak proporsional oleh orang kaya. Di masa lalu, pertumbuhan sektor publik menjadi cara untuk meningkatkan kesejahteraan massa tanpa merusak jiwa mereka. Sekali lagi, ini adalah soal waktu untuk memperluas layanan publik serupa; paling tidak, untuk mengurus pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai bidang-bidang utama yang paling menunjukkan meningkatnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
Kritikan kaum Politik Hijau terhadap konsumsi pun perlu dibongkar dengan cara yang sama. Dampak lingkungan dari barang dan jasa yang kita konsumsi sangat bervariasi. Emisi gas rumah kaca dan polutan lain yang terkait dengan perjalanan dari A ke B akan sangat berbeda sesuai dengan sarana transportasi yang digunakan. Hal yang sama berlaku untuk mandi air panas, bir dingin, dan sebagian besar bentuk konsumsi lainnya. Untuk perubahan iklim, masalah yang paling penting adalah efisiensi penggunaan energi dan sumber energi yang digunakan. Kedua efisiensi tersebut pun akan terus berkelanjutan dan ditingkatkan dengan cara memajukan teknologi.
Meski demikian, para doomsayers (pengabar kehancuran) tak akan bisa tenang. Mereka berpendapat bahwa menggunakan teknologi ramah lingkungan yang tersedia dan mengembangkan yang baru akan menciptakan biaya yang mungkin tak mau ditanggung oleh para individu. Jørgen Randers memperingatkan dalam ramalan suramnya tentang kehancuran tahun 2052. Bahkan menurutnya, jika kita mengatasi masalah ini secara kolektif, biayanya akan terlalu tinggi. Dalam pandangannya, tidak ada harapan keselamatan ekologis tanpa perubahan radikal dalam gaya hidup kita.
Namun langkah-langkah substansial masih dapat diambil dengan biaya sangat rendah. Regulasi baru tentang peraturan pembangkit listrik di Amerika Serikat yang diusulkan belakangan ini akan mengarah pada perubahan besar menuju energi yang lebih hijau dengan perkiraan biaya sekitar 50 milyar dolar setiap tahunnya; dari sekarang hingga tahun 2030. Hal ini terdengar begitu mahal tapi nyatanya proyek ini hanya menggunakan 0,2% dari total produk domestik bruto Amerika Serikat sehingga tidak akan membutuhkan perubahan radikal dari warga negara yang gaya hidupnya biasa-biasa saja. Seperti yang dikatakan Bjørn Lomborg dalam bukunya yang sangat berpengaruh; “The Skeptical Environmentalist” (2001); manusia telah berhasil memecahkan masalah lingkungan di masa lalu dan jika kemauan politik ada di sana, hal ini juga akan mungkin terjadi di masa depan.
Tidak ada kontradiksi yang melekat antara pola konsumsi yang lebih setara, lebih hijau, dan lebih manusiawi. Pertanyaan sebenarnya adalah: bagaimana memastikan bahwa sumber daya yang ada cukup untuk dicurahkan demi membawa perubahan yang diperlukan?
Seperti yang ditunjukkan oleh Žižek dengan benar, ini adalah tantangan yang tak dapat diwujudkan oleh konsumen yang tercerahkan melainkan hanya oleh warga yang peduli. Pemerintah sendiri memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan perubahan yang diperlukan demi membuat konsumsi kita lebih ramah lingkungan. Pula, hanyalah bentuk konsumsi kolektif yang dipimpin pemerintah yang dapat menyelesaikan masalah ketidaksetaraan secara progresif. Pertanyaan tentang apakah pengalaman konsumsi kita akan mewujudkan kesejahteraan atau menghancurkan kita di masa depan, nyatanya akan diputuskan lewat kotak suara dan bukan pada mesin kasir.
21 Juli 2014
–
[Pengalihbahasa: Taufik Nurhidayat. Jarang konsumtif karena nggak bakat berpansos.]