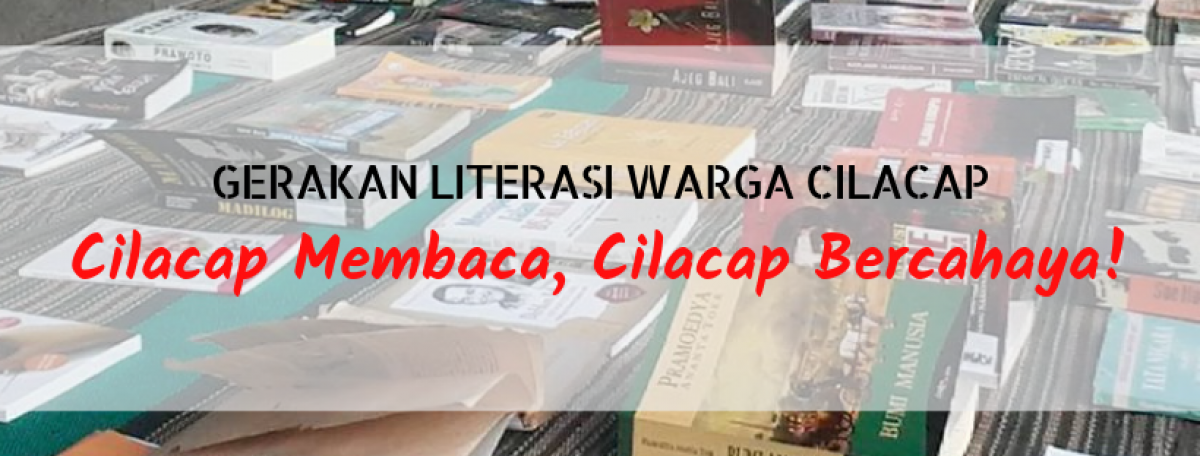*)Ditulis oleh Toto Priyono. Esais, penekun sosio-humaniora, dan bermukim di Cilacap.
–
Permainan kosakata seperti telah menjadi hal yang lumrah dalam memandang pergaulan masa kini. Setiap zaman pasti akan menciptakan suatu narasi yang; kita, “manusia”, seperti dituntut untuk menelanjangi diri; dimana apa yang dibutuhkan dalam menjalani hidup seyogianya hanyalah untuk sebuah candaan, tentu agar keinginan kita menjadi kabur dan tidak memperkeruh perkara-perkara apa yang harus dibutuhkan dalam menjadi manusia termasuk memandang cinta itu sendiri.
Mungkin akan menjadi aneh ketika manusia tidak menyadari sebuah kata “tren” di abad 21 ini. Memang tidak semua manusia dapat diseragamkan; bahwa mereka—manusia abad ke-21—harus hidup mengikuti tren. Namun di sini yang harus disadari: tidak semua orang hidup bersama dengan “tren”. Seperti yang banyak terlihat sekarang, tren sendiri bukan berarti hanya isu yang diperbicangkan orang secara berlebihan.
Barang dan bahasa juga termasuk dalam “tren” yang di dalamnya hangat juga untuk diperbincangkan; yang terkadang tidak disadari tetapi hal tersebut merupakan identitas budaya baru yang menjadi pijakan manusia untuk menanggapi suatu feonomena diri bersama dengan zamannya. Namun tentang budaya yang terbangun itu, sebenarnya sudah lama ada, hanya saja tidak disadari dan belum sempat ternamai sebagai simbol itu sendiri.
Perkara menjadi anak muda dan berbudaya, bukan saja ia harus mengubah segala sesuatunya sebagai identitas dari zamannya, tetapi juga sebagai titik pijak; dimana akan ada sesuatu yang mengingatkan dari hidup manusia ketika kita membangun budaya “tren” dalam menjalani hidup ini. Yang mungikin kini menjadi ingatan kolektif para generasi milenial di sana, tren akan grup band dan karya-karyanya di tahun 2010-an ke belakang yang mereka banyak menyinggung kata cinta di dalamnya. Waktu itu, generasi mereka—“milenial”—berada di dalam gelora anak muda yang mencirikan sebagai “pemain cinta”. Dan, hiburan dari apa yang disebut patah hati, bahagia atas nama cinta, dan kenangan-kenangan pengalaman dari menjalani cinta itu seperti termanifestasikan dari karya-karya berupa lagu dari grup band pada masanya.
Saya kira, milenial yang patah hati mengenal baik lagu Vagetoz atau dengan mereka yang menginginkan indah dan bahagianya “cinta” akan terus-menerus mendengarakan lagu dari grup band Naff. Kemudian dengan mereka yang menatap impian, mencoba mengais-ngais karya dari J-Rocks dengan musik yang menghentak untuk meraih mimpi.
Tidak disadari juga sebagai budaya masa itu oleh milenial; bahwa mereka mengikatkan diri pada wadah “fans” dimana grup band yang menjadi representasi perasaannya; itulah yang menjadi identitas dalam pergaulannya. Pada masa itu, semua bertanya; grup band apa yang menjadi karya-karya favoritnya? Tentu grup band tersebut yang membawa diri dan perasaan mereka sebagai yang; entah itu sedang patah hati, bahagia, bahkan yang sedang mengejar mimpinya. Dan saya membayangkan, mungkin yang menjadi kenangan akan karya-karya lagu dari musik sendiri saat ini—mencerminkan sebuah tren pada zamannya, akan menjadi sebuah ingatan masa lalu oleh Generasi Z di masa depan. Dan karya dari lagu tersebut adalah lagu-lagu yang menjadi tren masa kini: 2019.
Nantinya, Generasi Z ketika mendengar lagu Mundur Alon-alon atau Kartonyono Medot Janji, ia teringat masa lalunya. Praktis jika ingatan mereka atau karya dari lagu-lagu saat ini mencirikan narasi patah hati, tentu mereka—Generasi Z—merupakan generasi yang mengingat patah hati.
Bucin: Berakar dari Ingatan “Romansa” Masa Lalu Milenial
Berangkat dari ingatan, mungkin apa yang terjadi sebagai sebuah wacana ingatan saat ini bagi milenial adalah perkara romansa cinta yang terbangun di masa lalu yang saat ini sulit untuk diwujudkan sebagai tujuan dari merawat ingatan itu sendiri. Dimana ia sudah bukan lagi pemain cinta yang percaya diri; karena bagi milenial kini, bermain cinta tanpa kerelaan waktu, biaya, dan fasilitas-fasilitas yang mengakomodasinya akan menjadi cinta yang hambar; mungkin salah satu contoh dari cinta kaum milenial kini adalah menjadi pernikahan itu sendiri.
Dan tentang yang banyak manusia sana anggap sebagai “bucin” merupakan produk masa lalu yang harus tetap ada di saat masa lalu sebagai ukuran yang dibutuhkan oleh generasi milenial saat ini. Jelas, untuk tetap merasakan romansa bahagia, patah hati, dan mimpi-mimpi akan keabadian diri dalam memandang cintanya karena masih riskan dengan pernikahan.
Bucin atau budak cinta sepertinya memang bukan stigma yang buruk. Pada dasarnya, semua orang berpotensi menjadi budak di kala manusia itu butuh sesuatu. Kebutuhan adalah perbudakan dan itu mengapa kaum budak diadakan di dalam sistem masyarakat dunia untuk menjawab apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam arti; majikan butuh pembantu, pembantu juga sebaliknya butuh majikan, karena tentu untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing.
Maka tidak heran, kebutuhan akan cinta sendiri pun tetap akan mengundang sistem-sistem baru dalam saling membutuhkan antar relasi manusia. Tetapi nahasnya hidup manusia memang menderita karena manusia ingin bahagia. Yang perlu menjadi garis bawah itu sendiri, bahkan pertanyaan yang belum ada habisnya dari awal lahirnya manusia adalah jawaban dari manusia yang ingin bahagia menempuh jalan cinta.
Secara harafiah, mungkin kata “cinta” jika dijabarkan merupakan sesuatu yang universal. Bukankah universalitas dari cinta itu sendiri tergantung dari manusia itu sendiri dalam menafsirkannya?
Inilah yang tidak dapat disamakan atau disama-samakan. Penafisran akan sesuatu bergantung pada kesadaran manusia itu sendiri, dimana cara berpikir menentukan cara manusia untuk sadar. Dan kini, penafsiran akan cinta sendiri begitu disempitkan; hanya sebatas antara pria dan wanita yang diharapkan akan saling butuh untuk saling membahagiakan satu dengan lainnya. Padahal filsuf “cinta” Cina, Jenderal Tiang Feng atau Cu Pat Kay pernah berkata, “Cinta, penderitaannya tiada akhir.”
Namun bucin yang sudah menjadi fenomena zaman berakar dari masa lalu manusia yang mengikuti tren pada masa dimana mereka merindukan sesuatu. Jelas, di sini, bucin merupakan produk zaman yang menjadi budaya dalam percintaan itu sendiri yang bertransformasi tetapi tidak disimbolkan melainkan hanya sebagai sebuah wacana
Dan saat ini oleh milenial, bucin adalah simbol baru para pemain cinta yang merindukan saat-saat mereka bahagia menjadi cinta itu sendiri. Namun yang tidak disadari; di dalam kebahagiaan selalu terselip kesengsaraan. Bermain cinta ibarat bermain di dua kaki yang sama, yakni antara kebahagiaan dan kesengsaraan itu sebagai bentuk dari mewujudkan cinta.
Menjadi manusia apapun namanya; baik label, stigma, atau juga khas dari candaan yang mereka bawa, sepertinya yang dicari dalam menjadi manusia adalah pembeda dan menjadi bucin mungkin merupakan bagian dari pembeda hidup manusia tersebut. Seperti ungakapan Zarathustra, bahwasannya jiwa manusia dimetaforakan menjadi tiga bentuk: yaitu jiwa Onta, Singa, dan Bayi. Mungkin kejiwaan dari kebijaksanaan seorang bucin ada pada jiwa Onta; dimana Onta makhluk penurut dan jika dibebani semakin berat, ia semakin bahagia dengan bebannya tersebut dalam menjalaninya.
Tetapi perlu dicatat; bahwa semua manusia berpotensi menjadi bucin tergantung dari bagaimana manusia itu sendiri memandang bahagia. Jika bahagia dari cinta menjadi “bucin” merupakan realitas yang harus dijalankan itu, tidak dipungkiri manusia akan menjadi bucin pada waktunya.
Oleh karenannya, pengejaran-pengejaran akan bentuk cinta itu sendiri memang sah-sah saja sebagai manusia yang ingin dibahagiakan cinta. Derita dan bahagia yang dibawa dari konsep cinta seperti telah melampaui saat kita harus menjadi budak cinta atau membutuhkan cinta itu sendiri sebagai sebuah pembeda dari hidup manusia.
Bersama dengan kebahagiaan; memang rasa bahagia tidak dapat diukur oleh logikanya sendiri. Setiap dari satu manusia dengan manusia lain mempunyai caranya untuk menjadi manusia yang berbahagia. Mungkin dengan “mem-Bucin” itu sendiri adalah titik tertinggi bahagia mereka, yang akan menjadi bahagia dengan laku membudakkan diri pada cinta.
Ingatan memang hanya menjadi ingatan. Saya kira bucin sebagai tren zaman sendiri tetap akan dijadikan sebuah kenangan pada masanya juga oleh milenial. Seperti karya dari lagu-lagu masa lalu, yang dalam kenangannya, manusia mengingat saat-saat itu di masa depan. Romansa kisah dari generasi milenial yang mungkin dalam dekade ke depan sudah tidak dapat lagi menjadi muda diganti dengan muda-mudanya generasi Z. Dan bucin akan tetap menjadi produk bahasa kebudayaan zaman yang akan terkenang nanti oleh generasi milenial ketika mereka sudah mempunyai anak; yang mana “bucin” itu hanya untuk bagaimana anak dapat tumbuh dan berkembang secara layak.
Yang perlu tetap harus diikuti adalah bagaimana nanti generasi Z membanaun budaya cintanya sendiri; apakah mereka akan seperti milenial yang membangun romansa cintanya dengan dan sebagai “bucin” karena pada saat itu menjadi pemain cinta yang menghamba pada karya-karya dari lagu cinta sangat begitu komplit seperti di sebelum tahun 2010-an?
Bukankah karya lagu-lagu saat ini yang banyak berisi patah hati dikombinasikan dengan dangdut koplo untuk bergoyang seperti Kartonyono Medot Janji atau entah apa yang merasukimu versi gagak menjadi pertanyaan sendiri yang sangat ambigu sekaligus bermakna dua? Jadi sekiranya fenomena apa nanti di masa depan yang akan di buat oleh generasi Z dalam memandang budaya baru akan cinta mereka? Mungkin jika saya mau berhipotesa membaca zaman; “bucin” tidak mungkin akan menjadi warisan yang abadi untuk setiap zaman.
Nantinya, generasi berikutnya—yakni generasi Z yang patah hati sekaligus berjoget dangdut koplo—akan membuat sebuah wacana; bahwa mereka bukan budak cinta yang terlahir dari romansa, tetapi menjadi budak bahagia yang tidak peduli cinta; yang penting joget saja saat bahagia maupun menderita karena cinta.