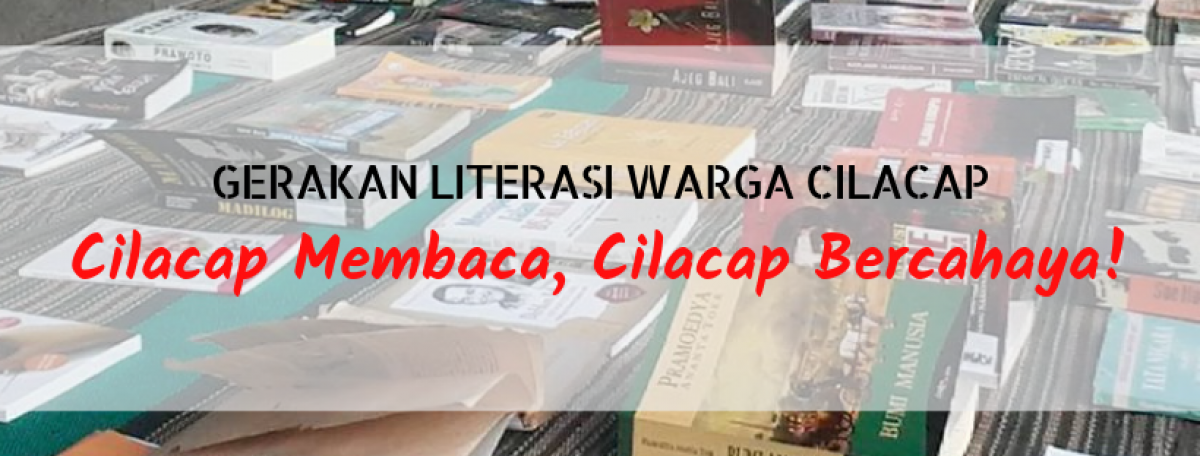–
*)Penulis Kathleen Vandenberg. Dosen senior di Universitas Boston. Pengamat desain urban, retorika visual, periklanan, gaya hidup, serta penulis esai.
–
Berkelana ke utara menyusuri Broad Walk, tepat memasuki Taman Kensington yang luas nan terawat indah sambil melewati kemegahan istananya di barat London; akan bisa segera sampai di Orangery dengan melalui lengkungan Wiggly Walk yang berbatasan dengan Taman Sunken.
Saat musim panas yang cerah, permukaan batu bata dan kaca paviliun taman ini memancarkan cahaya hangat kepada mereka yang berkumpul di beranda megahnya untuk menyesap teh panas dan menikmati brunch. Diri saya berada di sana pada suatu sore yang cerah baru-baru ini. Saya menduduki kursi besi bersama seorang murid saya. Sambil menikmati luasnya pemandangan taman di selatan, kami menunggu teman sekelasnya tiba.
Cahaya matahari sore itu memancar melalui awan tipis. Lalu-lintas jalanan dikelilingi oleh pagar yang bertebaran; area tersebut terlihat begitu manis dengan aroma rumput dan mawar. Tupai melompat dari jalanan ke jalanan untuk mencari makanan. Sementara taman bermain dan komidi putar di dekatnya menguarkan sayup-sayup suara kegembiraan.
Semua itu memanglah sangat menyenangkan dan mungkin menjadi suatu kesalahan apabila mengeluh karena harus menunggu di tempat seperti itu. Tapi 15 menit telah berlalu, kemudian menjadi 20 hingga 40 menit dan siswa yang ditunggu juga tidak muncul. Satu-satunya bukti keberadaannya adalah tulisan “ping” yang tak henti-henti darinya yang dikirimkan ke ponsel teman sekelasnya—yang hanya terasa menenangkan dan memulihkan keadaan barang sejenak; ternyata hanyalah latar belakang dari sebuah “drama” yang sangat familiar.
Siswa yang “menghilang” itu tampaknya samasekali tidak terbiasa dengan daerah tempat tinggalnya selama enam pekan. Karenanya, ia tidak menyadari bahwa menuju Orangery bisa dilalui dengan berjalan kaki setengah mil yang sangat nyaman, aman, dan indah dari pintu depan kediamannya—ia malah memesan Uber. Apa yang bisa didapati dengan berjalan-jalan di sepanjang Broad Walk yang indah dan semarak adalah sekilas pemandangan kuncup-kuncup bunga Flower Walk yang wangi dan kita bisa melewati angsa-angsa di Round Pound. Hal tersebut malah berubah menjadi perjalanan yang panik, mahal, dan menghabiskan waktu ketika ia sedang berjalan-jalan mengelilingi taman. Ia datang terlambat 45 menit, terasa lelah, dan memohon maaf. Dengan meneguk teh dinginnya, ia masih belum sadar dimana dirinya berada atau bagaimana ia bisa tiba di sana.
Masalahnya, bukanlah seberapa sering ia berkendara dibanding berjalan kaki dalam menempuh jarak pendek. Dari jutaan perjalanan yang dilakukan orang-orang di London setiap hari, hanya seperempatnya yang berjalan kaki. Yang dialaminya menandakan bahwa ia tak cukup sadar dengan kehidupan urbannya; yang seharusnya mengetahui bahwa berjalan kaki adalah rute yang jauh lebih pendek, lebih langsung, dan lebih menyenangkan ke tujuannya.
Ketidakmampuan siswa saya untuk menempatkan dirinya dalam suatu ruang, kegagalannya menavigasi lingkungannya sendiri, dan kepercayaan sepenuhnya pada teknologi adalah perbuatannya untuk ingin berada di tempat yang ia tandai sebagai “kerumunan warga kota abad ke-21”. Navigasi outsource di teleponnya atau satnav dari pengemudi Uber kepadanya adalah fakta kehidupan lain bagi begitu banyak orang yang berlalu-lalang di jalanan kota-kota modern.
Menurut data World Health Organization (WHO), lebih dari 50% populasi dunia sekarang bertempat tinggal di perkotaan. Dengan jumlah tersebut, perkiraan peningkatan jumlah menjadi 60% akan terjadi pada tahun 2030. Dan, sebagian besar pejalan kaki menggunakan smartphone untuk bernavigasi.
Di negara asal saya; Amerika Serikat (AS), sekitar 77% orang memiliki ponsel pintar. Hasil survei Pew Research Center pada 2014 mengungkapkan bahwa sekitar tiga perempat orang dewasa di AS mengatakan bahwa mereka tidak bermasalah terhadap orang yang menggunakan ponselnya saat sedang berjalan kaki di jalanan, berada di angkutan umum, atau mengantri. Studi Pew lainnya pada 2012 menemukan bahwa tiga perempat pemilik ponsel pintar menggunakan ponselnya untuk memperoleh informasi berbasis lokasi; seperti pemetaan dan ulasan obyek wisata terdekat. Dan pada 2016, sebuah laporan dari The Wall Street Journal mencatat bahwa antara tahun 2010 hingga 2014 telah terjadi kenaikan pasien ruang gawat darurat sebanyak 124% akibat perhatiannya terganggu oleh perangkat seluler saat berjalan kaki.
Sebuah video NBC pada tahun 2017 menunjukkan seorang wanita 67 tahun di New Jersey terjungkirbalik jatuh ke ruang bawah tanah terbuka dengan bagian kepalanya yang pertama kali tersungkur. Ruangan itu menganga lebar dengan pintu-pintu berdiri di atas trotoarnya; sehingga memberikan kesan visual yang menakjubkan soal seberapa terganggunya perhatian dari sebagian kita akibat ponsel. Beberapa kota di Jerman dan Cina bahkan merespon hal seperti demikian dengan membangun atau mengadaptasi jalur pejalan kaki dan persimpangan demi mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat berjalan kaki sambil berbalas pesan.
Ketidakpedulian kita terhadap lingkungan hidup kita tentu saja tidak universal. Buktinya, masyarakat dengan pola berburu-meramu masih ada di tempat-tempat yang kelangsungan hidupnya bergantung pada kemampuan membaca alam. Tetapi budaya mayoritas telah memandang keberadaan mereka terputus dari lingkungan—yang alami maupun terkonstruk—yang tumbuh selama ribuan tahun. Dalam bukunya; “The Spell of The Sensuous” (1996), filsuf AS; David Abram merujuk alfabet sebagai teknologi paling awal untuk menjauhkan manusia dari lingkungan alam. Dahulu, kaum pemburu-peramu bergantung pada hubungan sensual dengan alam; sangat akrab dengan aroma binatang yang mereka buru, peka terhadap suara predator, dan dapat menavigasi dengan penglihatan. Akhirnya, keberadaan teks memastikan bahwa penglihatan manusia dibelokkan dari representasi dunia nyata.
Sekarang, defleksi semacam ini tercipta melalui layar-layar berwarna yang mengkilap dan bukan oleh piktograf (papan huruf) yang pada awal penemuannya digambar secara kasar dan tidak banyak menimbulkan masalah. Bagi sebagian besar orang—terutama kita yang di perkotaan, sudah sejak lama hubungan kita dengan lingkungan kita tidak dimediasi oleh teknologi dan kita tidak akan merasakan kehilangan koneksi langsung dan sensualitas kepada bumi secara akut.
Lagipula, tidak perlu bagi penghuni kota untuk menghirup aroma predator supaya mengetahui sebidang tanah mana yang layak dipagari sebagai area paling baik untuk menanam sereal. Warga kota juga tidak perlu tahu cara mengidentifikasi kotoran binatang di taman kota. Bahkan tanpa aplikasi cuaca, kita tak ada kebutuhan mendesak dalam memindai langit untuk mandi atau mencatat curah hujan di barometer demi menilai kapan kemungkinan datangnya hujan—apalagi berada dalam ruangan. Menurut kebanyakan orang, perubahan hari tidak berarti jika mereka tidak dapat lagi (atau tidak pernah bisa) menemukan Polaris (rasi bintang Kutub) di langit musim dingin atau saat mereka menghancurkan kacang kastanye dan pecan dengan bagian bawah kaki.
***
Masalah sebenarnya adalah apa yang “dilalui” dan “melalui”; yang tidak terlihat atau disalahpahami di lingkungan buatan itu sendiri. Lanskap kota mungkin diabaikan tetapi kota tersebut tidaklah sunyi. Secara desain, ia berbicara. Desain itu bergerak, mendorong, memotivasi, dan meyakinkan. Lengkungan yang mengesankan di atas St. Paul Cathedral akan memojokkan desain Shard—bangunan di dekatnya—yang parah dan minimalis. Layaknya cahaya keemasan dari patung Prince Albert yang bertengger tinggi di atas Taman Kensington; hal itu menarik perhatian kita ke atas dan ketinggian mereka menandakan kekuatan mereka; dengan garis-garis vertikal dan skala yang mendominasinya menggambarkan kita menatap “surga” melalui penyembahan kepada Tuhan, uang, dan monarki. Desain itu menyatakan sejarah Kekaisaran Inggris, dominasi global dan budaya, serta kekuatan finansial.
Kesenjangan sosial-ekonomi tampak besar di lingkungan perkotaan. Kota-kota kita mengomunikasikan batas-batas sosial-ekonomi, ras/etnik, dan gender sejelas pemetaan kemiskinan abad ke-19 karya Charles Booth. Kota-kota kita menyiarkan aturan tentang “siapa yang diundang” dan “siapa yang harus diusir”. Ketika kita “membungkam” (kenampakan/aspirasi) kota demi mengangkat telepon kita; ketika kita mengalihkan pandangan kita dari cerita kota ke peta digital, kita hanya melihat pilihan realitas yang terdistorsi, dibatasi oleh bingkai, dan didekontekstualisasikan; yang memberi kita perasaan palsu bahwa perjalanan kita dibebani oleh kota karena kita memilih memetakannya daripada melewatinya.
Peta dan aplikasinya akan meratakan, menyederhanakan, dan menetralkan ruang yang pada kenyataannya adalah tiga dimensi, kompleks, dan retoris. Sentuhan layar smartphone yang terlihat keren dan lembut tidak memberi kita petunjuk tentang kemungkinan interaksi oleh sentuhan ataupun motivasi arsitektural. Setiap baris yang dipetakan dari titik A ke B tampaknya sama-sama dapat diakses semua orang tanpa memandang usia, kelas, ras, atau jenis kelamin. Masalah dengan pembangunan jalan dan lalu lintas hanyalah satu-satunya kendala yang dicatat oleh peta digital; seolah-olah kota merupakan taman bermain terbuka bagi semua orang.
Di jalanan, dengan berjalan cepat dan—mungkin yang paling penting—tanpa layar, orang dapat tetap sepenuhnya selaras dengan pesan yang disampaikan oleh lingkungan buatan. Meskipun kita mungkin sudah lama melarikan diri dari akar sejarah berburu-meramu, kita tetap sepenuhnya manusia ketika tidak terikat dengan perangkat elektronik. Indera kita menjadi panduan paling pasti untuk apa yang menarik dan melibatkan diri kita. Seperti yang dijelaskan oleh arsitek Denmark; Jan Gehl,“Kecepatan kita bergerak sangat penting. Berakar dari sejarah biologis, alat sensorik manusia dirancang untuk memahami dan memproses sensor tampilan saat bergerak pada kecepatan sekitar 5 km/jam.”
Perangkat tersebut tersedia untuk memindai cakrawala dan mengambil peranan saat berada di luar ruangan. “Semakin cepat kita pergi, semakin luas pandangan kita” seperti yang dikatakan oleh seorang perencana kota; Nick Jackson dari Toole Design di Boston. Semakin lambat kita pergi, maka semakin banyak kita melihat-lihat; semakin besar kemungkinan kita bereaksi terhadap elemen desain seperti papan tanda yang melarang kita berperilaku, fasad rumit yang mendominasi ruangan pribadi, jalan yang diaspal tanpa jalur sepeda untuk pengendara sepeda, tanaman pot besar yang menghambat kita berkeliaran, atau gerbang hiasan yang menutup akses berjalan—atau dengan kata lain sebagai retorika lanskap perkotaan.
Ruang publik di kota adalah palimpsest (sejenis naskah bertumpuk-red) yang mengalami penghapusan dan revisi terus-menerus. Jejak kekuasaan dan hak istimewa yang turut membentuk setiap lininya terlihat oleh pengamat dan pihak yang terlibat. Sama halnya seperti prestise yang tertulis di ruang publik; hal itu terdapat di distrik-distrik keuangan yang menjulang tinggi, menara-menara gereja, lengan-lengan tentara yang mengangkat perunggu, dan taman-taman yang terpelihara dengan baik di Palace Gardens Terrace di Kensington—demikian pun sebaliknya.
Kaum miskin mempunyai fasilitas dan akses yang jauh lebih sedikit ke perjalanan, restoran, dan perumahan layak. Mereka sangat lebih bergantung pada trotoar yang baik, taman umum yang bersih dan dapat diakses, serta ruang publik berkualitas tinggi untuk berkumpul dan bersosialisasi dibandingkan dengan kalangan kelas menengah dan orang kaya—seperti yang dikemukakan Enrique Peñalosa; Walikota Bogotá dan jawaranya ruang publik.
Tahun 1800-an di London, orang kaya di West End tidak menyadari kerumunan, kemiskinan, dan penyakit di East End. Dengan cara yang sama, pengunjung modern Whitechapel berfokus pada peta digital yang membawa mereka langsung ke Cereal Killer Café yang trendi di Brick Lane dan ke seni jalanan Instagram-able di sekitar Old Spitalfields Market. Mereka dapat dengan mudah mengabaikan perumahan anggota parlemen di dekat Tower Hamlets yang baru-baru ini dijadwalkan untuk dibongkar sebelum mendapatkan tekanan kembali yang berhasil dilakukan oleh para warga.
Banyak kota bekerja keras memanipulasi lingkungan buatannya untuk mencegah kehadiran mereka yang dianggap “tidak diinginkan”; yang sebagian besar—kecuali untuk pemain skateboard—adalah para tunawisma. Oleh karenanya, penambahan “arsitektur defensif” adalah elemen yang dibangun untuk mendorong orang keluar dari ruangan. Mulai dari paku di puncak pagar yang mengantisipasi orang memanjat ke taman umum dan dikunci pada malamnya, hingga sandaran tangan di tengah bangku publik untuk mencegah seseorang tidur siang. Pagar, kusen jendela, dan jalan masuk sering dipenuhi dengan paku logam bundar yang tidak cukup tajam dan kurang berbahaya tapi cukup menonjol untuk mencegah orang duduk atau berbaring. Gang-gang yang terjaga keamanannya, kursi stasiun bus yang miring, dan enklave-enklave yang dilengkapi dengan shower rail guna membasahi yang tidak diinginkan; semuanya adalah instalasi saat ini di kota-kota seperti London; yang lebih dari 700 orang terlihat tidur di jalanan pada malamnya. Modifikasi terhadap lanskap perkotaan semacam itu merupakan praktik retorika yang seringkali tidak diperhatikan—bahkan oleh penduduk kota yang berniat paling baik—dan karenanya tidak tertandingi.
***
Sementara kita menatap aplikasi peta atau navigasi outsource ke Uber terdekat demi mempercepat perjalanan di jalanan kota; arsitek, pejabat kota, perencana kota, dan perusahaan desain semakin memperhatikan cara-cara desain perkotaan berbicara kepada para penduduk kota. Pengamat urban AS; William H. Whyte (1917-1999) yang menuliskan teks-teks mendasar seperti “The Social Life of Small Urban Spaces” (1980) dan “City: Rediscovering The Center” (1988), mengatur cara untuk pengumpulan banyak data dan observasi spasial yang sedang dilakukan di kota-kota masa kini. Karyanya yang inovatif tersebut terus memiliki pengaruh besar terhadapnya. Seperti Gehl—seorang arsitek yang disebutkan sebelumnya—dan perencana kota AS; Allan Jacobs, ia mengabdikan diri untuk meningkatkan kualitas pengalaman kita mengenai ruang dan tempat.
Pertanyaan yang dihadapi oleh orang-orang yang berinvestasi dalam kehidupan kota merupakan suatu motivasi. Para investor berpikir bagaimana caranya selain melalui tanda-tanda yang jelas—seperti hukuman dan larangan, mereka bisa mempengaruhi cara kita bergerak melalui ruang publik perkotaan. Lebih khusus lagi, mereka mempelajari bagaimana lingkungan yang dibangun dapat dirancang sehingga orang “terdorong” untuk bertindak dengan cara yang aman, berkelanjutan, dan diinginkan secara sosial. Intervensi skala kecil; seperti kursi yang dapat dipindahkan, fitur air dengan tambahan suara dan visual yang menenangkan, didirikannya pagar dan batas tempat bertengger; semuanya telah ditemukan untuk membuat ruang lebih menarik. Pencahayaan yang baik—terkecuali pada semak-semak yang mungkin menciptakan area tersembunyi untuk aktivitas ilegal—dan jalur sepeda yang aman bagi mereka yang tidak memiliki mobil, semuanya bisa membuat area lebih aman.
Para profesional telah bekerja mengenai bagaimana kota dapat dibuat untuk “berbicara” kepada penduduknya dengan cara-cara yang mengarah pada demokrasi, keselamatan, dan keramah-tamahan. Akan tetapi, psikolog Jerman; Julia Frankenstein memperingatkan bahwa dengan mengandalkan GPS, kita mungkin akan mengurangi peta kognitif kita dan perasaan kita tentang apa yang ada di sekitar rute sempit yang telah ditunjukkan oleh layar kita. Kita mungkin belajar untuk “melucuti” peta lingkungan kita secara mental.
Orang-orang yang menatap peta digital secara rapi bisa menelusuri garis dekontekstualisasi dari persimpangan di luar Stasiun Gloucester Road Tube ke Whole Foods Market di Kensington High Street. Mungkin bahkan tidak melihat pagar dan indahnya gerbang hiasan yang menutupi taman-taman pribadi yang mereka lewati; sehingga sangat kurang menyadari bahwa hal-hal tersebut tidak hanya menarik secara estetika tetapi juga menandai klaim eksklusif orang kaya terhadap beberapa ruang hijau terbaik di pusat Kota London. Orang yang menatap telepon untuk pergi ke toko sandwich Pret terdekat mungkin gagal untuk melihat daya pikat sudut dan celah yang melapisi jalanan di Hampstead Village.
Sejarah juga tertulis di ruang publik. Monumen dan peringatan yang dapat ditemukan di seluruh London—di dalam katedral, di atas bukit, di Royal Parks, di samping trotoar kota, dan jalur hijau yang dominan—menawarkan narasi publik yang membingkai memori historis kolektif; melegitimasi beberapa hal yang hilang sambil mengabaikan yang lainnya dengan latar belakang tokoh-tokoh tertentu dan meminggirkan sosok lain serta mendorong kesombongan dan mengandung duka sekaligus mencegahnya menginfeksi kehidupan sehari-hari.
Patung besar Prince Albert siap menarik perhatian, bahkan kepada para pejalan kaki yang paling lalai di Taman Kensington. Namun seberapa banyak orang urban yang mengikuti layar ponselnya untuk menuju ke Borough Market melalui London Bridge dengan cukup lambat untuk melihat Cross Bones; kuburan abad pertengahan kecil di Southwark atau melihat cukup dekat untuk membaca ribuan “orang buangan” yang namanya tidak disebutkan dan dimakamkan di sana? Tubuh mereka; yang diabaikan atau dieksploitasi dalam kehidupan dan dibuang dalam kematian, menceritakan kisah tentang kematian bayi, kemiskinan, pelacuran, dan rasa malu—atau kisah-kisah yang tak mungkin mencapai mata para pemirsa layar yang teralihkan perhatiannya.
Contohnya seperti murid saya, kita kehilangan diri kita dalam ketergantungan pada alat digital untuk navigasi. Ketika kita harus melihat aplikasi untuk mengetahui bahwa Sungai Thames berada di selatan kita atau harus diarahkan secara bergantian oleh Siri (semacam aplikasi asistensi via rekaman suara pada gadget–red) dengan menggunakannya dari Royal Albert Hall ke Stasiun Gloucester Road, kita tidak hanya menyangkal kesenangan flaneur (kebiasaan berjalan-jalan tanpa tujuan pasti ala cendekiawan dan seniman Perancis-red) abad ke-19; namun juga berkontribusi terhadap polusi kota dan menimbulkan sedikit risiko kematian oleh GPS. Kita juga menjadi tidak mengetahui cara kota-kota kita dibangun untuk mendorong, mencegah, mengubah rute, membujuk, atau mengusir penduduk tertentu, serta cara-cara kota kita dirancang untuk merayakan kisah-kisah beberapa orang sambil meminggirkan sejarah orang lain. Ketika kita “membungkam” kota untuk menatap ponsel kita, lingkungan perkotaan menjadi tidak terbaca; warganya menjadi tidak menyadari berbagai elemen monumental dan duniawi yang membentuk sikap, tindakan, dan akses terhadap dirinya beserta sesama warga lainnya.
3 Oktober 2019
–
[Pengalihbahasa: Taufik Nurhidayat. Sejenis kucing kusam di rimba urban.]