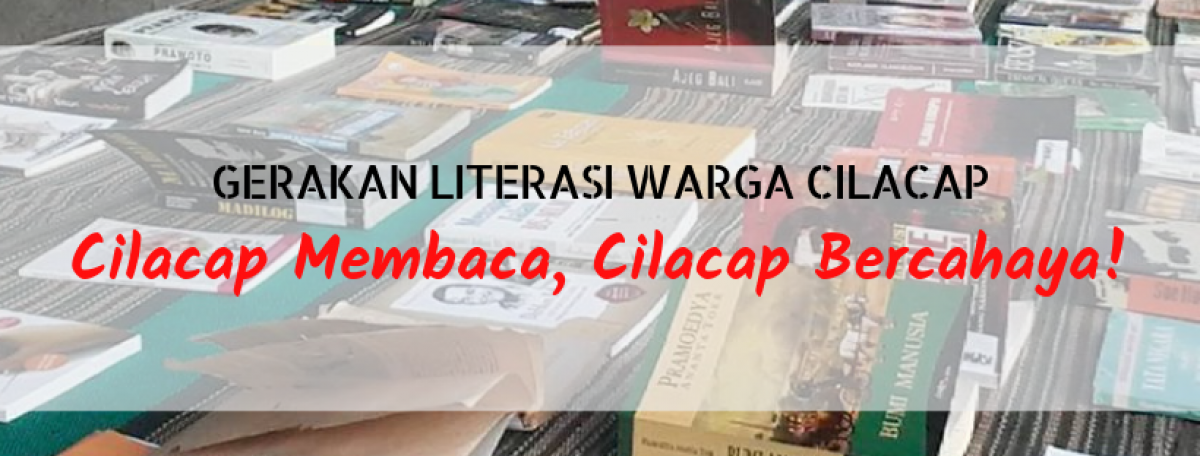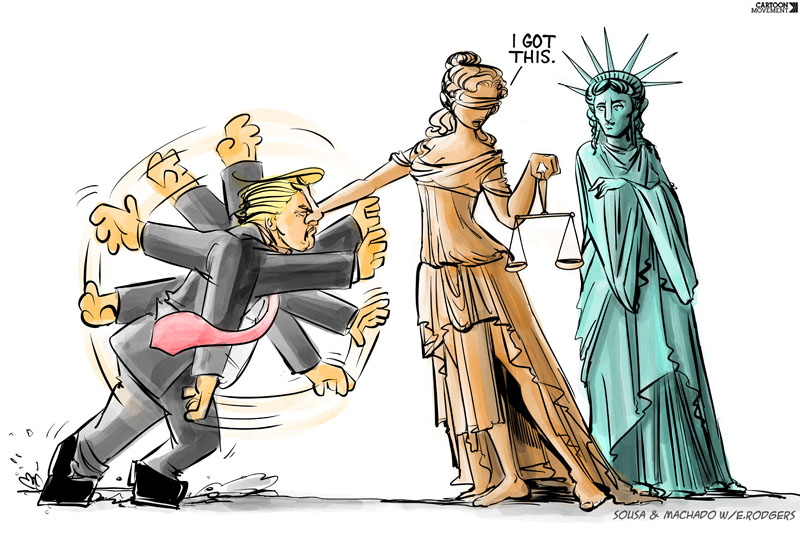
–
*)Oleh Toto Priyono. Peminat sosio-humaniora, esais, dan bermukim di Cilacap.
–
Berbicara masyarakat bukan saja berbicara tatanan; tetapi juga harus berbicara ide-ide dalam bermasyarakat. Memang, menjadi satu manusia ideal harus betumpu pada tujuan “ideal” itu sendiri yang disepakati bersama.
Namun dalam bangunan bermasyarakat, apakah konsep ideal tidak menjadi kabur ketika satu dari banyak masyarakat sendiri mempunyai gagasan bagaimana menjadi ideal itu menurut versinya masing-masing?
Tentu tidak akan menjadi mudah ketika manusia berbicara ide—apalagi saat ia harus berbicara ide—namun ide itu dihadapkan dengan kerumunan yang juga membawa ide-idenya sendiri-sendiri dalam balutan bermasyarakat. Ibaratnya menjadi satu semut dalam satu rumah diisi jutaan semut yang menghuninya; satu manusia tidak dapat mengubah apapun terkecuali: ia memang sudah punya kekuatan dalam mempengaruhi banyak manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.
Maka tidak heran, pemimpin-pemimpin diciptakan dalam struktur sosial bermasyarakat; bawasannya titah atau pengaruh mereka dapat mempengaruhi wacana ide berpikir manusia dalam hidup bermasyarakat. Tetapi apa yang tidak dapat disentuh oleh manusia berpengaruh tersebut (pemimpin) adalah ranah tradisi dan anggapan yang berbudaya secara turun-temurun menjadi keyakinan banyak masyarakat.
Secara tidak langsung, keyakinan-keyakinan tersebut menjadi dalil-dalil baru dalam hidup bermasyarakat yang diyakini secara ideologis bawah sadar mereka. Dalil tersebut seperti hukum dan apa bentuk hukum tersebut adalah adanya konsep dari stigma buruk dalam sebuah persepsi; yang menjadi acuan dalam bermasyarakat itu sendiri sebagai “ideal” dari yang dipilih atau disepakati menjadi ideal.
Sebut salah satu yang banyak terhukum masyarakat saat ini adalah stigma menjadi (sebagai) “perempuan”. Mengapa perempuan cenderung rentan terkena dampak buruk dari stigma tersebut di masyarakat?
Perlu diingat, peradaban saat ini bukan saja bentuk dari keterpengaruhan di masa lalu, tetapi pengetahuan yang dibangun cenderung maskulin dan meminggirkan perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang setara. Karena di dalam keyakinan masyarakat tradisional, perempuan bukan saja harus patuh, kalem, dan tidak mengikuti gaya hidup yang nakal, tetapi juga dari dalam strata sendiri harus lebih rendah dari laki-laki, padahal semua manusia diciptakan untuk menjadi sama; tidak ada perbedaan, baik di dalam masyarakat maupun sebagai pribadi manusia itu sendiri.
Perempuan terlihat lemah karena pandangan sosial yang memposisikan mereka lemah; bukan berarti dipandang “lemah” tidak bisa menjadi kuat. Perempuan merupakan makhluk yang paling kuat meskipun ia direndahkan secara pandangan sosial—tetapi kekuatan itu terletak pada sikap mau mengalah terhadap peradaban yang sebenarnya menindas mereka.
Pada dasarnya, perempuan adalah makhluk paling berani menata dirinya. Mereka adalah pemimpin sekaligus mampu “mengalah” untuk menjadi perempuan itu sendiri; yang bila mereka menggugat: dunia memang milik mereka (women the real leader of the world).
Mungkin inilah jawaban dari kebudayaan Jawa, misalnya; meskipun sosok pemimpin perempuan sendiri banyak di belahan dunia lain, tetapi kebudayaan Jawa merupakan kebudayaan yang terdekat dan nyata dapat kita lihat. Mengapa tempat bersemayamnya raja-raja Jawa dinamakan keraton? Bukankah keraton sendiri berasal dari kata “keratuan” (ratu: perempuan); yang dimana pemimpin sebenarnya harus berjiwa feminis?
Sosok atau figur jiwa perempuan menjadi ibu bagi kehidupan seperti harus dilibatkan dalam struktur tertinggi politik masyarakat Jawa. Ini menunujukkan bahwa peradaban memang harus feminim supaya jiwa merawat kehidupan seperti ibu yang merawat dengan baik anak-anak mereka; sebagai bagian dari menjaga kehidupan itu sendiri.
Namun kembali tentang sesuatu yang telah membudaya dari generasi ke generasi, bahwa dibutuhkan kesadaran secara total dalam bermasyarakat untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi peran maskulinitas peradaban dunia. Yang justru terjadi, faktor kejayaan, ekspansi, dan kehendak kuasa menjadi cermin peradaban masyarakat dunia saat ini; bukan merawat dunia seperti peran ibu (feminin).
Memang bukan hanya berbicara keadilan gender, tetapi juga mana peran yang baik untuk sama-sama merawat dunia dan masyarakatnya. Masih banyaknya perang di dunia, ketimpangan sosial, dan eksploitasi pada alam yang berlebihan mungkin harus berkaca pada apa sebenarnya yang salah dari peradaban dunia itu sendiri saat ini? Maskulinitas yang terkadang jumawa; mengidealkan kuasa dalam permainannya, apakah ini biang dari semakin terdegradasinya kehidupan dunia dimana alam dan masyarakat semakin mempunyai kualitas hidup yang rendah?
Bukan saja menjadi catatan, dalam menjadi manusia, memang faktor feminin dan maskulin dapat termanifestasi di tubuh yang sama. Tetapi berbicara adikodrati sebagai manusia, mereka akan optimal ketika mereka menyadari tubuhnya masing-masing dan tidak mungkin manusia akan optimal tanpa ia bersatu dengan tubuhnya sendiri; dalam arti, permpuan tetap menjadi feminin dan laki-laki akan tetap menjadi maskulin.
Stigma Moral Terhadap Perempuan
Menjadi manusia memang tidak berbeda. Setiap manusia berhak berpikir; berhak menentukan hidup sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Begitu pula menjadi perempuan, mereka bebas menjadi apapun yang mereka mau. Kita, antara perempuan dan laki-laki, terperangkap di tubuh yang sama; yakni manusia.
Tetapi, ide tentang moralitas seperti sebuah sandungan dalam menjadi manusia. Semua serba atasnama keyakinan yang dipercayainya masing-masing dalam memandang hidup. Norma-norma yang masyarakat pandang seperti sebuah dalil sosial padahal sosial terbentuk dari pribadi-pribadi antara laki-laki dan perempuan; dimana wacana menghakimi sebagai masyarakat haruslah bagaimana menjadi manusia secara pribadi terlebih dahulu.
Hidup di dalam keyakinan pada tradisi seperti gampang yang susah. Di samping gampang telah memiliki pakem yang ada, susah ketika pakem tersebut tidak sesuai dengan apa yang manusia kehendaki di dalam menjadi masyarakat itu sendiri sebagai pribadi. Menjadi masyarakat ibarat manusia menjadi dua kaki; satu kaki harus taat pada norma masyarakat, satu kaki lagi harus dapat menjadi bebas sebagai pribadi manusia.
Maka moralitas dan strata sosial dalam masyarakat seperti hanya akan berbuah paradoks. Namun yang tetap menang di sini yakni laki-laki yang dipandang lebih superior dibandingkan perempuan. Dalam hal moralitas juga sama; laki-laki seperti biasa dipandang dalam hal-hal merokok, mabuk, dan bekerja kasar, misalnya. Berbicara hal yang sama menjadi manusia, perempuan seharusnya dipandang sama jika mereka harus merokok, mabuk, atau kerja kasar untuk mengisi harinya sebagai manusia.
Saya tidak sepakat bahwa rokok dan apapun itu terlarang bagi perempuan secara wacana ide moralitas kepatutan menjadi masyarakat. Mau mabuk atau apapun, itu adalah kebebasan sebagai manusia, termasuk perempuan itu sendiri.
Mabuk, rokok, dan segala macamnya, termasuk mencari nafkah keluarga, bukankah sudah menjadi produk kebudayaan dari dulu yang dilabeli untuk laki-laki? Pola pikir masyarakat sudah terbentuk begitu berpakem: wanita itu harus kalem, penurut, dan tidak mengikuti gaya hidup yang nakal. Jelas, pandangan masyarakat menstigma bahwa “kalau dia perempuan tidak benar karena di luar dari pakem itu” yang menjadi perspektif ideal bagi masyarakat.
Namun lambat laun, ini hanya budaya, bisa berubah tergantung pola pikir lagi di masyarakat. Setelah masyarakat dewasa memandang kehidupan, membuat berpakem-pakem itu akan hilang dengan sendirinya, karena keadaan gaya hidup populer dan segala macamnya termasuk dalam semesta wacana pemenuhan kebutuhan keluarga akan terus mengikuti kebutuhan zaman.
Bukankah kini karena kebutuhan hidup, perempuan mencari nafkah sudah menjadi biasa untuk sama-sama memenuhi kebutuhan keluarga? Sepertinya benar perspektif yang diyakini masyarakat dalam wacana ide masyarakat sendiri, yang belum dewasa memandang sesuatu di luar pakem menurut pandangan mereka.
Dalam bergaya hidup sebagai modern sendiri, kini memang sudah tidak akan zaman lagi “ini bagian laki-laki, ini bagian perempuan”. Semua aspek kehidupan masyarakat cenderung akan menunjukkan kesetaraan di masa depan termasuk dalam ruang mencari nafkah, gaya hidup, bahkan kebutuhan hidup untuk “nakal” itu sendiri; yang kini dijadikan sebagai pelarian kebosanan pada hidup yang “mengapa harus begini-begini saja hidup sebagai manusia itu?”.
Ketika hidup manusia sudah setara dalam pandangan masyarakat sendiri, kini perempuan yang dikerdilkan peranannya dan moralitasnya untuk bagaimana menjadi perempuan, akan mendapat hak yang sama di masa mendatang. Perempuan yang sebenarnya kuat dan punya insting dalam merawat kehidupan sendiri dengan potensi yang tersembunyi dari mereka, nantinya ketika tidak ada lagi wacana ide masyarakat dalam kesetaraan lebih merendahkan perempuan, bukan tidak mungkin perempuan mengambil alih peradaban untuk memimpin dunia dengan sikap dan kekuatannya sebagai perempuan: sang pemberi dan melahirkan hidup.