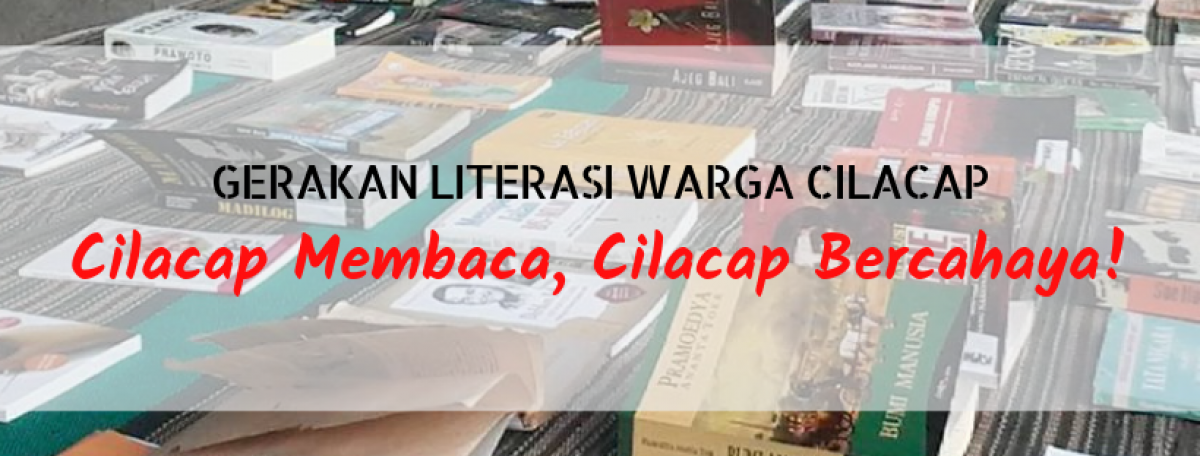–
*)Ditulis oleh Frank Furedi. Sosiolog yang dulunya menjadi profesor sosiologi pada University of Kent di Kota Canterbury, Inggris. Dia menerbitkan banyak buku; yang terakhir ialah How Fear Works (2018).
–
Sabtu, 1 November 2014. Saya sedang mencari buku di Barnes & Noble, Fifth Avenue, Kota New York. Seketika, perhatian saya tertuju pada koleksi volume yang dibuat dengan indah. Saya melihat lebih dekat dan menyadari bahwa buku-buku ini adalah bagian dari kategori Leatherbound Classic. Seorang asisten toko memberi tahu saya bahwa sampel bagus semacam itu akan turut memperindah koleksi buku saya. Sejak pemberitahuan ini, saya diingatkan berkali-kali bahwa buku sangat penting sebagai simbol penyempurnaan budaya. Meskipun kita musti hidup di era digital, pemaknaan simbolis dari buku terus-menerus menikmati penilaian budaya. Itulah sebabnya, ketika saya melakukan wawancara televisi di rumah atau di kantor universitas saya, saya seringkali diminta untuk berdiri di depan rak buku saya dan berpura-pura membaca salah satu teks.
Sejak penemuan sistem aksara paku di Mesopotamia sekitar 3500 SM dan hieroglif di Mesir sekitar 3150 SM, pembaca teks yang serius telah menikmati aklamasi budaya. Papan tanah liat dengan tanda-tanda tertulis dianggap sebagai artefak yang berharga dan terkadang sakral. Kemampuan untuk menguraikan dan menafsirkan simbol dan tanda dipandang sebagai pencapaian yang luar biasa. Hieroglif Mesir dianggap memiliki kekuatan magis dan—hingga hari ini—banyak pembaca menganggap buku sebagai media untuk mendapatkan pengalaman spiritual. Semenjak teks memiliki begitu banyak makna simbolis, maka apa yang orang baca dan bagaimana mereka membaca—secara luas—dianggap sebagai fitur penting dari identitasnya. Membaca selalu menjadi penanda karakter. Itulah sebabnya, orang sepanjang sejarah telah menginvestasikan sumber daya budaya dan emosional yang cukup besar demi menumbuhkan identitas sebagai pecinta buku.
Di Mesopotamia kuno; dimana hanya ada sekelompok kecil juru tulis yang bisa menafsirkan papan-papan aksara paku, prestise yang luar biasa diperoleh para penafsir tanda ini. Pada titik inilah, kita mempunyai satu petunjuk paling awal tentang kekuatan simbolis dan hak istimewa yang dinikmati oleh pembaca. Sebagai pembaca yang pecemburu, para ahli baca-tulis yang ambisius melindungi otoritas budaya mereka dengan membatasi akses ke pengetahuan magisnya.
Pada abad ke-7 SM, ketika penulisan Kitab Ulangan Perjanjian Lama disokong Raja Yosia di Yerusalem, pancang tinggi dipasang untuk pemujaan buku itu. Yosia menggunakan gulungan yang ditulis oleh para deteronomisnya untuk memperkuat perjanjian antara orang-orang Yahudi dan Tuhannya—dan, hal ini menginspirasi tindakan strategi politik untuk mengabsahkan warisannya atas klaim tanah itu.
Era Kekaisaran Romawi—yang dimulai pada abad ke-2 SM, buku-buku seperti diturunkan dari surga ke bumi; yang mana buku-buku tersebut berfungsi sebagai barang mewah untuk membuat pemilik kaya mereka memperoleh gengsi kebudayaan. Seneca, filsuf Romawi yang hidup pada abad pertama Masehi, menyatakan sarkasme pada pemujaan tampilan teks yang dimegah-megahkan. Ia mengeluhkan bahwa banyak orang tanpa pendidikan sekolah tidak menggunakan buku-buku sebagai alat belajar melainkan sebagai dekorasi ruang makan. Kepada kolektor gulungan yang flamboyan, ia menuliskan, “Anda dapat melihat karya lengkap orator dan sejarawan di rak hingga langit-langit karena perpustakaan telah menjadi seperti kamar mandi; menjadi ornamen penting dari rumah kaya.”
Permusuhan Seneca terhadap kolektor buku yang sok pamer mungkin dipengaruhi oleh kerisihannya terhadap mania membaca yang tampaknya menimpa publik di awal periode Kekaisaran Romawi. Periode ini menampakkan munculnya pengkajian bacaan (resitasi) di muka umum. Pembacaan di muka umum ini melibatkan sastra dari para penulis dan penyair yang dianggap layak sebagai peluang promosi diri oleh banyak warga kaya. Seneca memandang pertunjukan-pertunjukan kesombongan sastra yang vulgar ini secara jijik—dan dia pun tak sendirian.
Pembacaan yang dilakukan orang-orang penting nan sia-sia di Roma dan wilayah Kekaisaran lainnya menjadi target humor sarkastik. Banyak penulis-satiris Romawi terkemuka; seperti Horace (65-8 SM), Petronius (27-66 M), hingga Persius (34-62 M) dan Juvenal (55/60-127 M), mengarahkan humor cerdas mereka kepada kemewahan resitasi.
Menurut satiris Romawi; Martial, toilet umum pun tidak membatasi para pembaca di muka publik yang begitu mengganggu. Lewat suatu epigram sarkastiknya, ia menulis:
Anda membaca untuk saya ketika saya berdiri,
Anda membaca untuk saya ketika saya duduk,
Anda membaca untuk saya ketika saya berlari,
Anda membaca untuk saya ketika saya beromong kosong.
Saya lari ke kamar mandi;
Anda menghujami telingaku.
Saya menuju kolam renang,
Anda tidak akan membiarkan saya berenang.
Saya bergegas untuk makan malam,
Anda menghentikan saya di perjalanan.
Saat saya makan,
kata-kata Anda membuat saya muntah.
Para satiris yang mengolok-olok resitasi memahami bahwa reputasi dari bacaan yang disempurnakan adalah mewakili sumber modal budaya yang penting. Kecerdasan tajam yang mereka arahkan pada target mereka dapat dilihat sebagai bentuk kebijakan sastra. Ejekan yang dilakukan Petronius kepada Eumolpus sebagai “penggila puisi yang membosankan” di Satyrica juga dapat dibaca sebagai contoh pembijakan selera. Bukan karena apa-apa, Petronius pun dianggap oleh orang-orang sezamannya sebagai wasit elegantiarum atau seorang hakim keanggunan pada Istana Romawi di bawah Kaisar Nero.
***
Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi pada abad ke-5, orang-orang Eropa yang memiliki kekayaan materi—tapi tidak memiliki keanggunan dan kemutakhiran dari kemuliaan superioritas sosial mereka—menciptakan perpustakaan pribadi untuk mendapat perbaikan reputasi. Memang, bagi banyak orang, kepemilikan perpustakaan yang lengkap merupakan tujuan tersendiri. Hampir 1000 tahun kemudian, dengan munculnya Renaisans dan kebangkitan kancah perniagaan; kepemilikan buku menjadi meluas dan lebih banyak orang lagi yang melakukakn kebiasaan membaca sehingga perbedaan budaya yang dianugerahkan berdasarkan kebiasaan membaca menjadi pudar. Geoffrey Chaucer, dalam puisinya “The Legend of Good Women” yang ditulis tahun 1380-an, mencontohkan tren ini dengan menyatakan bahwa dirinya memegang buku-buku “dengan kondisi terhormat”.
Pada abad ke-14 dan 15, para pembaca yang mewah dan sombong muncul dengan kekuatan penuh. Esai bertajuk “Philobiblon” yang ditulis Richard de Bury pada tahun 1345 tetapi diterbitkan tahun 1473, dikatakan sebagai “risalah berbahasa Inggris paling awal tentang kelezatan literatur”. Tetapi, “Philobiblon” mengatakan sedikit tentang pengalaman aktual De Bury dalam membaca. Dia adalah seorang fetisis buku klasik yang minat sebenarnya adalah mengumpulkan buku daripada belajar.
William de Chambre; penulis biografi De Bury, menyatakan bahwa buku mengelilingi Bury di semua tempat tinggalnya. Ia menulis bahwa “begitu banyak buku terbentang di kamar tidurnya sehingga hampir tidak mungkin untuk berdiri atau bergerak tanpa menginjaknya.” De Bury tentunya telah mengantisipasi jika keserakahan hasratnya untuk mengumpulkan buku dapat menjadi sasaran kritik dan sarkasme. Makanya, ia secara eksplisit membela diri dari tuduhan berlebihan melalui prolog “Philobiblon” yang menyatakan bahwa “cinta ekstatif”-nya terhadap buku membuatnya bisa meninggalkan “semua pikiran tentang hal-hal duniawi lainnya”. Dia menulis “Philobiblon” supaya generasi berikutnya memahami maksudnya dan “untuk selamanya menghentikan gosip yang menyimpang”. Dia berharap kisah tentang hasratnya itu akan “membersihkan cinta yang kita miliki untuk buku-buku dari tuduhan yang berlebihan”.
***
Seniman potret tergoda oleh spiritualitas buku dan properti intelektual dan terus merangkulnya sebagai alat artistik yang penting.
Sebastian Brant; teolog humanis Jerman, samasekali tidak bisa menerima pernyataan di atas. Dalam satirnya; “Ship of Fools” (1494), ia menggambarkan 112 jenis orang bodoh. Dan, orang pertama yang naik kapal adalah “pecandu buku yang bodoh” yang mengumpulkan buku-buku dan membacanya untuk memperoleh pengaruh. Brant mengatakannya:
Pada kapal ini, sayalah yang nomor satu.
Demi alasan khusus untuk dilakukan;
sayalah yang pertama di sini yang Anda lihat
Karena saya suka perpustakaan saya
dari buku-buku yang tak kunjung habis saya punya;
tetapi sedikit yang bisa saya pahami.
Saya menghargai buku-buku dari berbagai zaman
dan menjaga halamannya dari ngengat.
Di mana seni dan sains diakui?
Saya katakan: di rumah saya yang paling bahagia.
Saya tidak pernah menjadi lebih puas
dibandingkan saat buku-buku saya berada di sisi saya.
Karya satir Brant menjadi buku terlaris dan dengan cepat diterjemahkan dari bahasa Jerman menjadi bahasa Latin, Perancis, dan Inggris. Tetapi sebaliknya, para pecinta buku yang bodoh tetap tak bisa dihalangi. Pada abad ke-16, idealisasi sekuler “cinta membaca” telah benar-benar terjadi. Membaca dianggap sebagai media penemuan diri dan mendapatkan wawasan spiritual tentang jalan duniawi.
Simbolisasi membaca mungkin lebih masif dari tindakan membaca itu sendiri. Orang-orang berusaha menangkap pengabdian mereka terhadap buku melalui potret terlukis yang menggambarkan mereka sangat asyik membaca teks. Dalam kancah seni Renaissance, lukisan orang-orang yang membaca dan potret individu yang merangkul buku tersebar begitu luas. Manuskrip-manuskrip era ini “bukan hanya dibanjiri dengan gambar buku tetapi juga dengan orang-orang yang membaca buku-buku itu”—seperti yang ditulis Laura Amtower dalam “Engaging Words: The Culture of Reading di In The Middle Ages” (2000).
Selama berabad-abad berikutnya, seniman potret yang tergoda oleh sifat spiritual dan intelektual buku terus menganut hal demikian sebagai penyangga artistik yang penting. Penyair humanis Dante selalu dilukiskan sedang membaca. Sebuah lukisan karya Agnolo Bronzino—seniman abad ke-16—yang berjudul “Allegorical Portrait of Dante” menggambarkan si penyair memegang sebuah edisi “Paradiso” yang sangat besar. Lukisan itu menggambarkan tentang buku seperti halnya tentang Dante. Menyaksikan performa membaca Dante adalah mengingatkan pemirsanya tentang status orang ini sebagai orang yang berprestasi secara budaya dan maju secara spiritual.
***
Kaum intelektual berusaha keras memperkuat status superiornya melalui ekspansi membaca pada abad ke-18 di kalangan masyarakat; dengan cara menekankan perbedaan antara dirinya dan orang yang kurang membaca. Sekarang ini, kritikus sastra telah menggantikan satiris Romawi. Mereka memuji pembaca berprestasi sebagai “orang-orang literer” sementara lawan-lawan moralnya dikarakterisasi sebagai “tidak melek aksara”.
“Membaca bukanlah suatu kebajikan. Tetapi membaca dengan baik adalah seni. Dan, seorang pembaca terlahir melalui perolehan seninya,” begitulah yang ditulis oleh novelis Edith Wharton yang ditegaskan dalam esai “The Vice of Reading” (1903). Wharton menulis bahwa, “pembaca mekanis tidak mempunyai ‘bakat bawaan’ , ‘bakat membaca’, dan tidak akan pernah bisa memperoleh seni.
Membaca telah diangkat menjadi sebentuk seni pada abad ke-20 melalui cara “menggambar garis di atas pasir”/memberi batasan oleh para intelektual. Di satu sisi, ada yang disebut “pembaca pura-pura” dan ada yang dianggap “elit” di sisi lain. Bahkan novelis Virginia Woolf pun turut menimpalinya. Dalam esainya “The Common Reader” (1925), ia menggambarkan bahwa rata-rata pembaca adalah seorang yang “kurang berpendidikan” daripada seorang kritikus. Seorang individu yang “secara alami tidak berbakat” akan begitu murah hati sebagai mitra berbakat. Menurut Woolf, pembaca biasa cenderung terburu-buru, tidak akurat, dangkal, dan tentu saja kekurangannya terlalu jelas untuk dikritik. Perspektif ini begitu stagnan karena terus mengklasifikasikan dan menilai para pembaca hingga hari ini. Melalui “The Pleasures of Reading” (2011), kritikus sastra Alan Jacobs berani membedakan antara “pembaca yang dibanggakan” dan “orang-orang rendahan yang membaca”.
Faktanya, tindakan tersebut menjadi sangat bergengsi. Sehingga, seorang anak yang membaca akan menandakan kompetensi orang tuanya—atau setidaknya menjadi superioritas moral dan budaya paling baik. Orang tua yang membaca untuk anaknya di ruang publik; sebenarnya sedang membuat deklarasi kepada dunia bahwa kegiatan bernilai tinggi yang kini dilakukan para ibu dan ayah adalah mencurahkan banyak waktu dan sumber daya untuk mendorong anak-anaknya bisa merengkuh buku secara fisik. Tak jarang, seorang balita pun terlihat duduk sambil memegang dan melihat buku kecil pada kursi anak-anak dalam mobil.
***
Secara kontras, seorang wanita abad ke-18 yang membaca buku dan seorang remaja yang menatap smartphone-nya adalah penggambarkan berbagai cara kita membangun identitas melalui membaca.
Sesegera mungkin, balita abad ke-21 ini akan meninggalkan kenampakannya membaca buku secara gamblang di muka umum dan mengadopsi kebiasaan memeriksa smartphone mereka secara teratur. Jika Seneca atau Martial ada sekitar hari ini, mungkin mereka akan menulis epigram sarkastik tentang “pameran membaca pesan teks dan tampilan teks di hadapan Anda”. Pembacaan digital selayaknya membaca gulungan kuno adalah pernyataan penting tentang siapa kita. Seperti para pembaca karya Martial di hadapan publik Roma; para pembaca yang keranjingan pesan teks dan media sosial lainnya ada di mana-mana. Meskipun dalam kedua kasus ini, para pembaca tanpa lelah membangun citra dirinya, namun identitas yang mereka bangun sangatlah berbeda. Orang-orang muda yang duduk di bar sambil memeriksa pesan pada ponselnya sedang tidak menyatakan status kesastraan mereka yang beradab. Mereka menandakan bahwa dirinya sedang berkoneksi dan—yang paling penting—menunjukkan bahwa mereka selalu ada perhatian.
Dengan kebangkitan teknologi digital, kinerja membaca menjadi berubah. Kontras antara seorang wanita yang asyik membaca buku dalam potret abad ke-18 dan seorang remaja yang secara sadar menatap smartphone-nya menggambarkan berbagai cara individu membangun identitas mereka melalui membaca. Saat ini, konsumen teks digital yang canggih bersaing dengan pembaca buku fisik dalam memperoleh pengakuan kultural. Akan tetapi, kinerja membaca mana yang paling dihargai?
Bagi mereka yang berhasrat mengumumkan kecerdasannya kepada dunia, pilihannya sudah jelas: teks digital tak berfungsi sebagai penanda perbedaan budaya. Mungkin itulah sebabnya, meskipun penggunaan tablet meluas, penjualan buku kertas meningkat baru-baru ini. Tidak seperti buku, tablet tidak menawarkan media untuk menunjukkan selera dan seni. Itulah sebabnya, dekorator interior menggunakan rak-rak buku untuk menciptakan kesan elegan dan beradab di dalam ruangan.
Secara aktif, bisnis mempromosikan penampilan mutakhir dengan cara menawarkan perpustakaan buatan yang sudah jadi kepada konsumen yang tertarik untuk mendapatkan tampilan sesuai selera. Suatu perusahaan online; Books By The Foot, menawarkan untuk membuat perpustakaan yang cocok dengan kepribadian dan ruang konsumen. Perusahaan ini menjanjikan untuk menyediakan buku-buku berdasarkan warna, penjilidan, subyek, ukuran, tinggi, dan lainnya; demi membuat koleksi yang terlihat megah. Bisnis online yang menjual perpustakaan khusus menunjukkan bahwa rak buku melambangkan kebudayaan yang tinggi—sekalipun di era digital.
Nyatanya, kebodohan para pecandu buku masih ada bersama kita. Tapi untungnya, masih banyak pembaca yang tidak hanya tertarik pada penampilan. Mereka masih meleburkan dirinya ke dalam teks dan benar-benar jatuh cinta dengan cerita-cerita yang mereka baca. Terlepas dari mediumnya, yang penting adalah aspirasi yang sangat manusiawi untuk mengambil bagian dalam perjalanan ini. Ini bukan soal performa dan kenampakan yang benar-benar penting. Melainkan tentang pengalaman perjalanan menuju hal yang tidak diketahui.
20 Oktober 2016
–
[Penerjemah: Taufik Nurhidayat. Penghindar ulung dari pergaulan poseur literatur.]
Esai ini diambil dari Aen.co dengan judul Bookish Fools